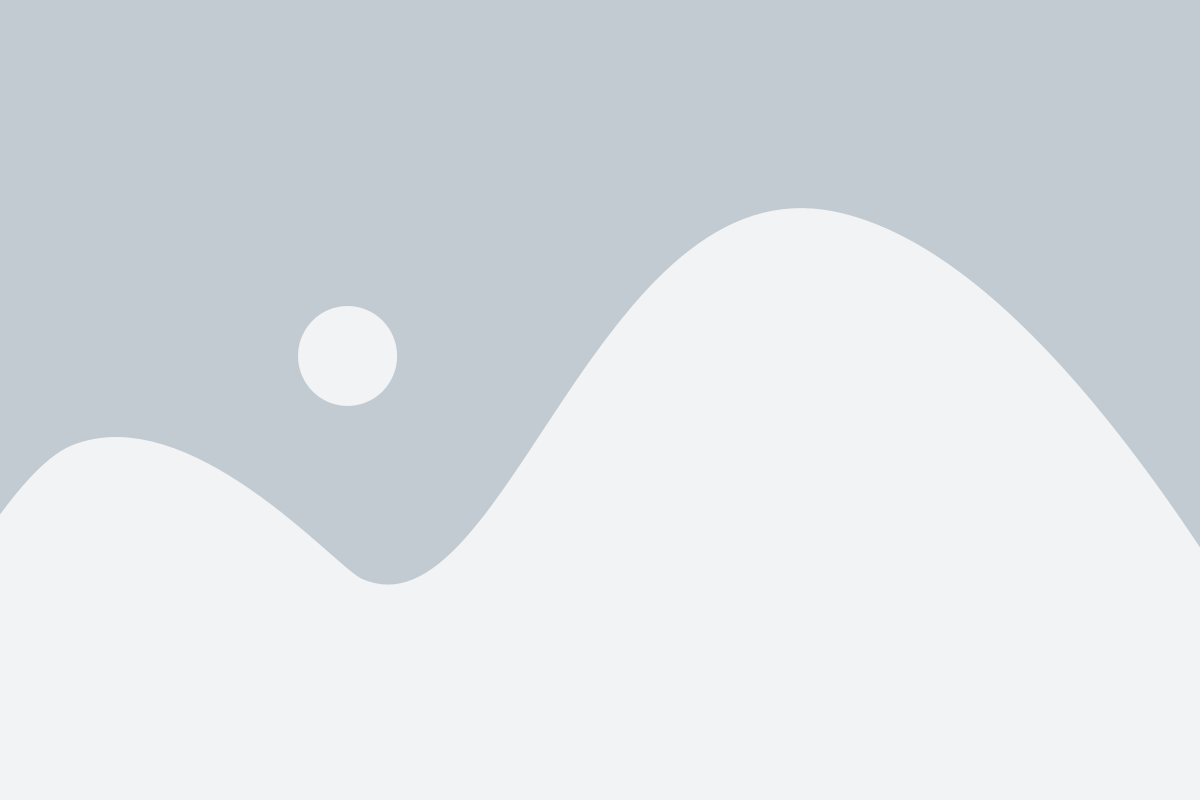Belakangan ini Pemilu 2024 sekonyong-konyong menjadi perhatian publik. Padahal waktunya masih relatif lama, kira-kira lebih dari tiga tahun lagi. Penyebab itu semua tak lain adalah munculnya pembicaraan mengenai draf Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Melalui draf RUU Pemilu tersebut menyeruak semerbak aroma pemilu. Khususnya aroma persaingan dini antara kekuatan politik yang akan berkontestasi, baik dalam bentuk praktik-praktik promosi kandidat presiden jagoannya maupun praktik-praktik marginalisasi kandidat yang dinilai akan menjadi kompetitor kuatnya.
Seperti pembicaraan tentang soal keharusan capres berlatar kader partai politik. Soal apakah Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023, ataukah tetap dilaksankan sesuai dengan skema yang terdapat dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yakni pada tahun 2024 bersamaan dengan pemilihan legislatif dan pilpres.
Publik tahu bahwa tahun 2021 ini tidak ada agenda politik praktis yang masif seperti pemilihan umum. Tahun ini digadang-gadang sebagai ‘tahun rehat’ pemilu.
Rehat Pemilu sejatinya menjadi ruang kontemplasi bahwa pemilu adalah tentang “kita Indonesia”, bukan tentang segelintir orang dengan kepentingan sesaatnya.
Pemilu adalah tentang daulat rakyat ketika ber-indonesia. Oleh karena itu, kita dituntut dan sekaligus dituntun untuk tidak lupa pada purwadaksi pemilu.
Istilah “purwadaksi Pemilu” itu sendiri terdiri dari dua kata yang berkelindan. “Purwadaksi”, kata yang berasal dari bahasa Sunda, memiliki konotasi segala sesuatu itu ada awal dan akhir.
Purwa berarti wiwitan atau mulai, dan daksi berarti wekasan atau akhir (Danadibrata, 2006 dan Hardjadibrata, 2003). Karena itu, purwadaksi menjadi kata yang mengandung kuasa agar kita mau ingat pada asal dan tujuan beraktivitas sehingga senantiasa berada pada rute perjalanan yang ajeg.
Adapun Pemilu adalah instrumen pewujudan kedaulatan rakyat dengan menghadirkan dan memastikan adanya rotasi kepemimpinan secara demokratis.
Pemilu juga merupakan sarana pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. Di samping itu, pemilu berfungsi sebagai sarana membangun legitimasi, sarana penyediaan perwakilan, dan sarana pendidikan politik.
Berdasarkan itu, purwadaksi Pemilu membayangkan bagaimana seluruh anak negeri berada pada lingkungan pemilu yang selaras dengan subtansi dan aturan main.
Keduanya adalah pagar demokrasi agar ia terjaga dari pengintaian para calon penyandera. Subtansi berhubungan dengan tujuan berpemilu, sedangkan aturan main terkait dengan prosedur-prosedur titik berangkat bagaimana tujuan itu tercapai secara efektif.
Di sini, semua pemangku kepentingan Pemilu, seperti DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, kontestan, dan masyarakat pemilih sepatutnya berada pada rute Pemilu secara subtansial sekaligus prosedural. Dengan rute itu, DPR dan Pemerintah misalnya, menjaga agar pemilu tidak keluar dari tujuan-tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam konteks itu, tujuan negara seharusnya menjadi titik berangkat dari pembahasan RUU Pemilu, bukan dari titik berangkat bagaimana memuluskan jagoannya seraya bagaimana menerjalkan jagoan dari lawannya.
Kedaulatan rakyat
Bagi masyarakat pemilih sepatunya terus saling meyakinkan, segala hak-hak politiknya akan tersalurkan dan terlindungi oleh negara. Pemilu itu sesungguhnya juga hadir sebagai ruang perjanjian masyarakat dengan para calon penyelenggara negara (pactum subjectionis).
Dalam teori asal-mula negara, perjanjian masyarakat tersebut pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari perjanjian-perjanjian masyarakat jauh sebelumnya. Terutama ketika antara kelompok masyarakat melakukan musyawarah dan kemupakatan untuk mendirikan organisasi kekuasaan bersama, yakni sebuah negara (pactum unionis). Titik ini mempertegas bahwa pemilik sah kedaulatan itu sesungguhnya adalah rakyat.
Pada konteks pemilu, kedaulatan rakyat diekspresikan melalui pemberian suara politik secara bebas bagi kontestan. Tentu suara yang diterima oleh kontestan mesti dimaknai sebagai amanat kedaulatan rakyat, bukan kemenangan atas lawan.
Konsekuensinya, melalui dan dalam pemilu, rakyat punya daulat untuk lanjut atau pun mencabut amanat yang diberikannya.
Oleh karena itu, sangat elok jika Revisi UU Pemilu sejatinya menyentuh tentang bagaimana menjaga kedaulatan rakyat. Seperti menjaga dari infiltrasi kepentingan oligarki dan kekuatan calon presiden demagog, yang keduanya bisa menyandera ekonomi negara serta membunuh demokrasi.
Salah satu cara yang bisa ditempuh, misalnya, adalah mengevaluasi pasal mengenai presidential threshold (PT). Sejauh ini pasal tersebut, yang menetapkan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional sebagai syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan capres dan cawapres, telah mempersempit kesempatan rakyat dalam mendapatkan banyak pilihan calon presiden terbaik dari yang baik-baik.
Oleh karena itu, pasal PT untuk Pemilu 2024 sewajarnya dihapuskan atau paling tidak diturunkan presentasenya agar figur-figur terbaik negeri ini bisa sama-sama ikut berkompetisi melalui partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPR (menembus parliamentary thershold). Artimya, presidential thershold bisa didorong untuk sebanding parliamentary thershold.
Dengan harapan, prinsip-prinsip kesetaraan, keleluasaan, keadilan, dan keterwakilan sebagai wujud daulat rakyat dalam pemilu tetap terlindungi. Yang pada gilirannya, pemilu bisa menghasilkan kemampuan negara untuk benar-benar menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Wallahu’alam bishawab.
Asep Sahid Gatara, Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Wakil Ketua APSIPOL; Wakil Ketua ICMI Jawa Barat
Sumber, Pikiran Rakyat 4 Februari 2021