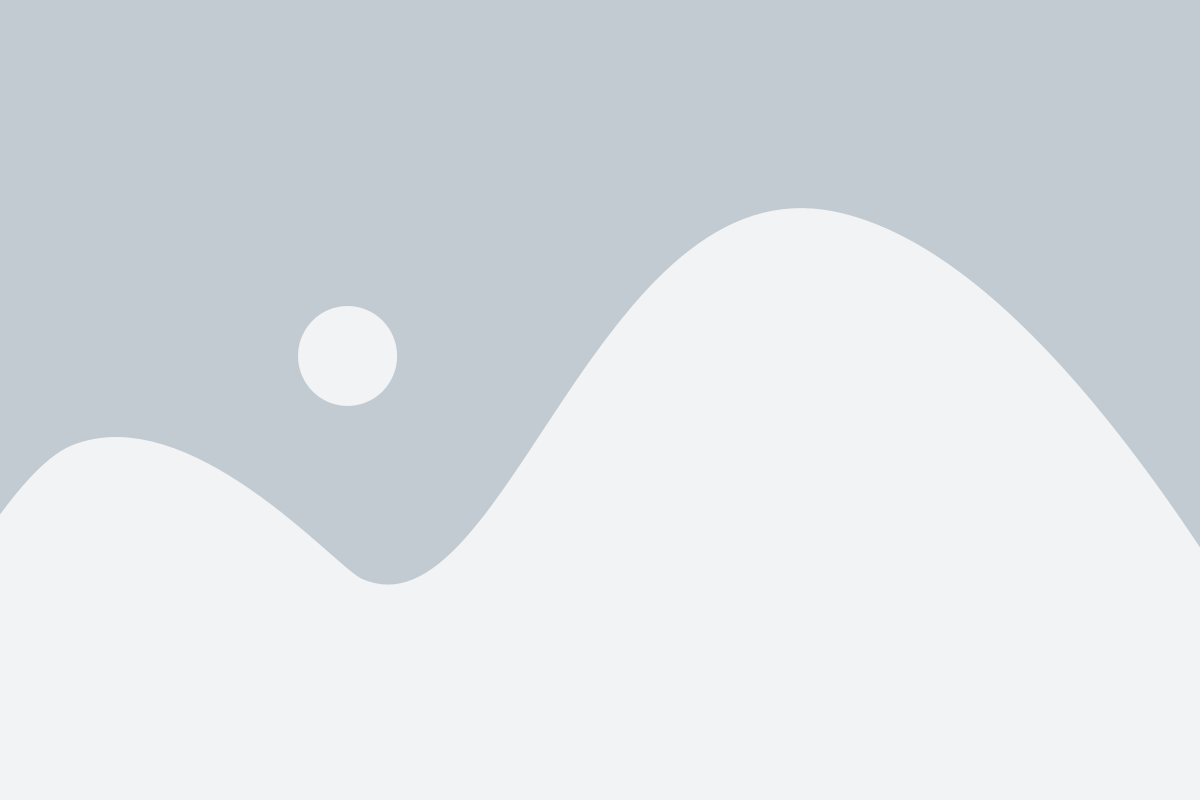UINSGD.AC.ID (Kampus I) — Tidak lama berselang pejabat dari dua lembaga negara, MK dan KPU, dinyatakan melanggar etik oleh “peradilan etika”. Dua lembaga negara ini kita tahu sangat vital kedudukannya, karena kedua-duanya memberikan legitimasi pada proses bernegara.
Muncul sebuah pertanyaan keraguan, apakah hukuman pelanggaran etika itu, baik langsung maupun tidak, berdampak negatif pada pandangan publik terhadap negara? Belum dapat dipastikan beneran bahwa hukuman etika tersebut memengaruhi kepercayaan warga terhadap institusi negara. Malah, kecenderungannya tidak berdampak besar di masyarakat umum.
Sumpah Jabatan
Saat akan mulai menjabat, setiap pejabat negara membacakan sumpah jabatan, sebagai “teks suci” perjanjian dengan rakyat. Sumpah jabatan itu menegaskan bahwa sebagai pejabat publik mereka akan berusaha untuk mengutamakan kepentingan publik dalam semua proses jabatannya. Dirinya mendeklarasikan tidak akan menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan harus menghindari kesan adanya konflik kepentingan. Masyarakat memercayai teks suci yang dibacakan pejabat itu merupakan kesadaran dan tanggung jawab etis untuk bertindak demi kepentingan publik.
Bahkan, dalam sejarahnya sumpah adalah janji ruhani yang lahir dari tradisi agama besar di dunia. Teks sumpah jabatan yang membawa nama Tuhan adalah permohonan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menyaksikan kebenaran pernyataan janji, dengan kesiapan untuk mendapatkan “kutukan Ilahiah” apabila terjadi pelanggaran oleh yang bersumpah.
Mungkin kita berpikir bahwa sumpah jabatan hanyalah retorika patriotik, yang dulu dibuat oleh founding father untuk sekadar seremoni. Tidak demikian. Teks sumpah yang tidak terlalu panjang tersebut sebenarnya adalah landasan moral spiritual perjanjian dengan Tuhan dan rakyat bahwa seorang pejabat sudah beralih dari sosok individu menjadi sosok publik yang telah bebas dari kepentingan pribadinya. Melalui teks suci sumpah seorang pengemban jabatan telah mengadaikan diri bukan untuk kepentingannya.
Komitmen pada sumpah jabatan tidak sekadar sampai di depan pintu kantor, namun terbawa sampai ke rumah, ke café, ke jalan, dan ke tempat-tempat lainnya. Bahkan, sumpah jabatan berdampak juga kepada orang-orang di sekitarnya, mengikat keluarganya agar ikut serta tidak melanggar nilai-nilai sumpahnya.
Seorang pejabat yang telah sumpah jabatan tidak bisa memisahkan dirinya dari ruangan kantor tempat ia duduk dengan di saat berada di tempat lain. Di tempat manapun ia terikat komitmen sumpah. Pejabat tidak sekadar terikat untuk berpatokan pada profesionalitas, tetapi terikat dengan etika.
Bukan Pelamar Pekerjaan
Karena dilakukan oleh para pejabat publik, yang diidolakan dan digandrungi masyarakat, praktik pelanggaran etika akan mempromosikan moralitas yang longgar dan mengajari sikap pasif. Pelanggaran etika jabatan publik, dalam jangka panjang, mengarah pada sikap yang merusak, di antaranya membentuk skeptisisme dan sinisme terhadap kerangka hukum dan terhadap gagasan kejujuran.
Memang, tidak mudah mengintegrasikan gagasan kebaikan moralitas ke dalam diri kita. Kadang terlalu jauh kita mampu menemukan kesadaran bahwa etika merupakan hal fundamental dalam diri kita, yang “kebermasalahannya” akan menimbulkan ewuh-pakewuh pada kepercayaan publik. Bahkan, terkadang kita tidak sadar dampak buruk dari masalah etik yang akan menimpa diri, keluarga, teman, tetangga dan semua orang yang berhubungan dengan kita. Seharusnya, kata Immanuel Kant, jika etika sudah terinternalisasi jauh di lubuk hati manusia nilai-nilai yang teguh dan visi jangka panjang dari tindakannya akan sangat sulit untuk menyimpang.
Hanya dengan mengintegrasikan etika ke dalam semangat pejabat publik maka moralitas tidak lagi akan jadi sebuah pertanyaan yang muncul dan mengherankan di masyarakat. Para pejabat publik akan memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan pelamar pekerjaan yang bersemangat mendapatkan jabatan publik untuk menjadi kaya dan menikmati status.
Belakang ini salah satu isu yang menyeruak dan cenderung kontroversi dalam perhelatan Pemilu 2024 kemarin, yang mendapat sorotan luas, adalah perdebatan soal etika. Seharusnya, etika tidak perlu diperdebatkan. Kita harus mufakat untuk menyediakan ruang komitmen yang menjamin perilaku beretika untuk terbangunnya budaya etis. Melalui etika kita bisa merencanakan masyarakat yang adil dan jujur, dimana nilai-nilai etis membentuk kepribadiannya.
Di antara tuntutan masyarakat di masa sekarang ini adalah simpati yang harus diterima dari para pejabat. Pemenuhan tuntutan tersebut antara lain terpenuhinya suasana etis, perilaku beretika. Para pejabat publik tidak diharapkan terjebak dalam skandal etika, yang akan mendiskreditkan citra institusi dan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Tidak Cukup Sekadar Peraturan
Instrumen pengendalian pejabat publik yang ada saat ini fokus pada peraturan perundang-undangan dan pengawasan formal. Tampilan nilai-nilai etis, yang seharusnya untuk memagari jabatan publik, baru sekadar retorika. Kesadaran tentang tindakan yang harus berorientasi pada kontrol diri belum terbentuk secara sistematis.
Etika belum diyakini oleh kita akan berdampak pada kepuasan publik dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Pelaksanaan bernegara tidak sekadar membutuhkan tatanan peraturan perundang-undangan yang benar tetapi memerlukan bangunan etika yang mengawal penyelenggara.
Pejabat yang baik tidak sekadar mengutamakan kualitas profesionalisme melainkan berpadu dengan kesadaran etika. Etika tidak akan bertuah hanya dari kata-kata, melainkan harus ditunjukkan, karena etika bukanlah objek intuisi melainkan emosi.
IJA SUNTANA, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung.