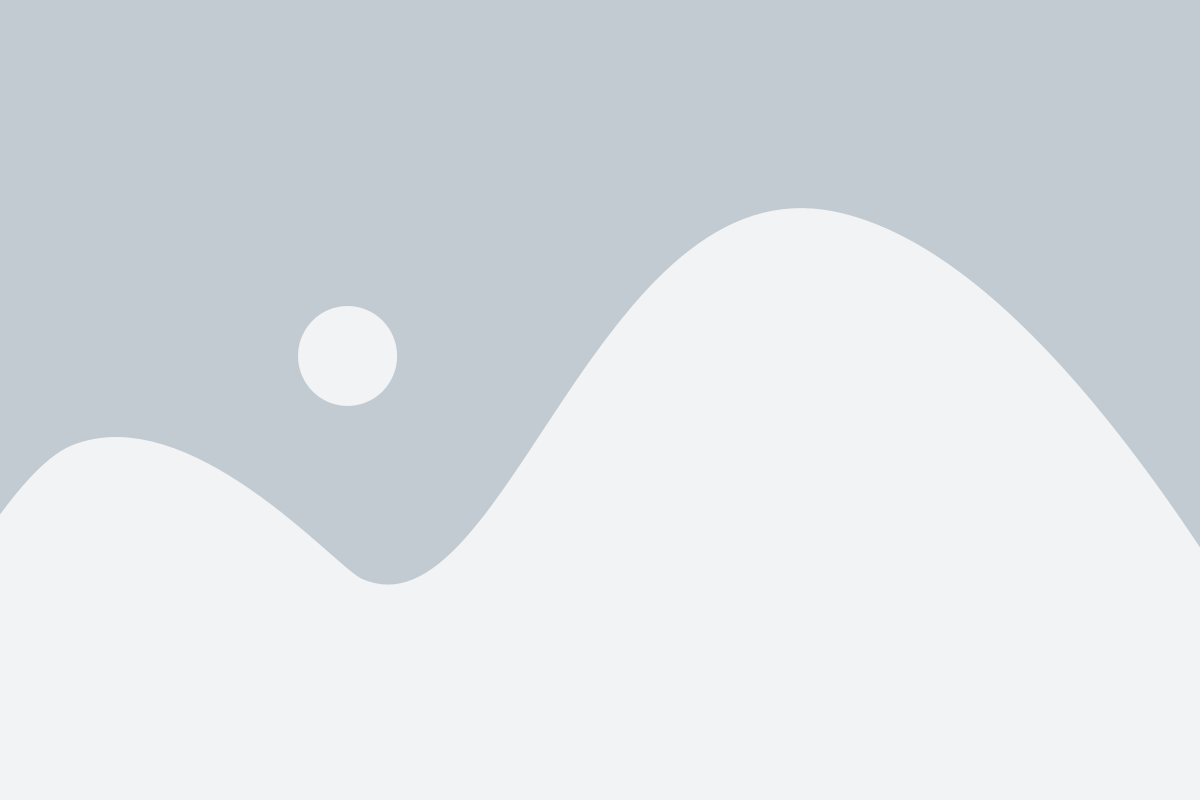Elmu (bahasa Sunda) tentu berasal dari bahasa Arab: ‘alima, ya’lamu ‘ilm, ‘alim. Proses mencari pengetahuan dalam bahasa Sunda dikatakan ngelmu atau ngalap elmu. Nyuprih pangaweruh. Tentu saja objek elmu itu beragam. Terbentang mulai elmu fisik (kadugalan, kawedukan, kadigjayaan/kasakten), sampai elmu yang bersifat metafisis semisal agama, kebatinan bahkan kepercayaan kepada ilapat, uga dan kila-kila.Semakin dia memiliki kecakapam elmu fisik, maka kian tangguh pertahanan lahirnya. Sakti mandraguna. Pun, manakala elmu metafisik yang dikuasai dengan sempurna maka dia akan meraih kajembaran hidup. Dalam literasi budaya Sunda seperti tercatat dalam Pangeran Kornel dan Mantri Jero, literer estetis berupa roman karya R. Memed Sastrahadiprawira (Suwarsih Warnaen, dll., 1983) yang menggambarkan karakteristik dan filsafat manusia Sunda buhun diteguhkan bahwa ngelmu itu musti dijangkarkan pada fungsi utama elmu yakni: 1) memperhalus dan menegakan tabeat anu luhur; 2) memberikan rasionalisasi pada pamilih; 3) mempertebal dan memantapkan kasatiaan; 4) memberikan rasionalisasi dan motivasi pada wawanen; 5) memberi kearifan dan meluruskan jalannya akal pada kapinteran; 6) memberikan dorongan dan harapan pada kerajinan.Tidak sekadar nalarDari pemahaman seperti ini nampak jelas bahwa konsep elmu dalam tradisi kesundaan tidak hanya berkutat sebatas nalar (kecerdasan akal, kapinteran), namun juga pada saat yang sama berkelindan dengan kecakapan emosional bahkan juga spiritual. Dalam bahasa yang lebih populer terangkam dalam ungkapan nyantri, nyakola, nyantika dan nyunda.Keterlibatan yang integral dimensi religiositas (spiritual) dalam konsep elmu nampak jelas dari banyaknya digunakan nama untuk Tuhan (Pangeran) kaitannya dengan dimensi ilmu yang luas seperti: Gusti Nu Murbeng Alam, Gusti Nu Maha Wisesa, Gusti Yang Manon. Bahkan tidak hanya sebatas itu sisi Pangeranpun dalam tradisi elmu Sunda ditarik dalam ranah kemanusiaan sehingga nampak citra Tuhan Yang Maha Esa memiliki agen di alam ini seperti nampak dalam roman Mantri Jero:“Sungut sambung lemek, suku sambung leumpang, kaula panghulu agung, wawakil panatagama, neda panyaksen, agungna ka Gusti Alloh nu maha wisesa, jembarna ka sakur nu hadir, batina kanu Ngayuga, lahirna ka bumi langit, ka bayu, jeung watu, lamun enya Raden Yogaswara beresih dirina, sing kebel teuleumna, ulah muncul samemeh Sang Batok Kohok titeureub” (mulut sambung bicara, kaki sambung langkah, aku penghulu agung, wakil panatamagama, minta kesaksian, agungnya kepada Gusti Alloh yang Maha Kuasa, umumnya kepada semua yang hadir, batinnya kepada sang Penjaga, lahirnya kepada bumi langit, kepada angin, kepada kuya, kepada batu kelau betul dari Raden Yogaswara bersih, semoga lama ia menyelam, jangan muncul sebelum Sang tempurung bolong tenggelam)Elmu seperti ini akan membentuk manusia Sunda menjadi manusia berbudi luhur, bernalar tinggi di samping kepekaan spiritul yang tidak disangsikan. Elmu ini yang akan menjadi pintu masuk tertanamkannya sikap-sikap positif sebagaimana dalam roman di atas. Yakni: 1) wanter (tidak pernah takut dalam membela kebenaran); 2) leber wawanen (wawasan yang luas); 3) teuneung ludeung dan taya karisi (tidak pernah dihantui ketakutan dan sikap ragu); 4) percaya kana diri pribadi teu sieun panggih jeung cilaka (percaya diri dan siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk).Secara fisik ilmu seperti ini juga akan membuahkan hidup yang sejahtera. Kecakapan sosial menjadi modal terwujudnya hurip gustina waras abdina, rea ketan rea keton rea harta rea harti. Atau dalam bahasa yang lebih populer bahwa pengetahuan itu menjadi bekal seseorang memiliki sawah ledok, bojo denok (sawah subur dan istri montok), buncir leuit (lumbungnya penuh), huma kaomean (hama tergarap) dan akhirnya selalu siap untuk mengubah rintangan menjadi kejayaan, tantangan menjadi peluang. Deugdeug tanjeur jaya perang.Elmu ajugSatu lagi kosa kata yang dinisbahkan kepada elmu dalam tradisi masyarakat Sunda namun dalam pemaknaan negatif, yaitu elmu ajug. Semacam ilmu lilin: menerangi orang lain namun dirinya sendiri terbakar. Ilmu yang sama sekali tidak pernah memberikan pencerahan (ilmuinasi), perubahan (trasformasai) dan pembebasan (liberasi) kepada dirinya.Pemilik elmu ajug boleh jadi memiliki kecakapan berbicara kepada orang lain, namun tak punya kehendak yang tulus memberikan keteladanan. Ilmu untuk memprovokasi, absen dari introspeksi dan tak memunculkan refleksi. Ilmu ke luar, bukan ke dalam. Ilmu yang berputar sebatas formalitas, dan tidak ada kemauan berubah menjadi substansi. Ilmu seperti ini ketika menjadi ajaran agama maka agama itu kehilangan etika, seandainya menjadi hukum maka kehilangan keadilan, menjadi politik kehilangan kesantunan dan manakala menjadi ekonomi ternyata kehilangan praksis mewujudkan keadilan yang merata.Derivasi (turunan elmu ajug) ketika diterjemahkan dalam administrasi kenegaraan hanya memunculkan sikap-sikap yang mendua. Menyuruh hidup penuh kesederhanaan dengan cara mengencangkan ikat pinggang, namun dirinya sendiri bergelimang kemewahan. Memaklumatkan “katakan tidak” pada korupsi, tapi diam-diam diri (dan kelompoknya) terseret arus hidup korup, rakus dan tamak. Poligami diserang, tapi diam-diam istri simpanan di setiap pengkolan. Tekhnologi dirayakan, dan pada saat yang sama aspek negatifnya tidak dipikirkan. Industri didirikan, dan analisis dampak lingkungan ditanggalkan.Inlah ilmu bunuh diri. Ilmu yang telah menyebabkan manusia bukan pinter tapi guminter. Bukan kecerdasan tapi keculasan. Tidak mendatangkan kearifan malah menimbulkan penghianatan. Tak ubahnya dalam amsal Sayyed Hossen Nasr, “…membakar tangannya dengan api yang telah dinyalakannya karena ia telah lupa siapakah ia itu sesungguhnya. Seperti yang dilakukan Faust, setelah menjual jiwanya untuk memperoleh kekuasaan terhadap lingkungan alam manusia, ia menciptakan suatu situasi di mana kontrol terhadap lingkungan berubah menjadi pencekikan terhadap lingkungan yang selanjutnya tidak hanya berubah menjadi kehancuran ekonomi tertapi juga perbuatan bunuh diri.”Elmu ajug ini, diakui atau tidak, yang menjadi penyebab tergelarnya hidup yang werit (penuh krisis dan hilangnya orientasi sejati), saheng harengreng (menggelisahkan), loba karisi ka rempan (dihantaui ketakutan), dan loba kahariwang (dihantui kekhawatiran).Jangan-jangan elmu ajug inilah yang mendominasi epistemologi kita baik dalam aras kebangsaan atau kesukuan (Sunda) sehingga kita begitu sulit berkelit dari beragam masalah. Yang terbentang mulai krisis ekonomi, krisis budaya bahkan boleh jadi krisis identitas seperti terangkum dalam diksi jati ka silih ku junti.Asep Salahudin, peminat sosial budaya Sunda, Dosen UIN SGD Bandung, dan Wakil Rektor IAILM Suryalaya TasikmalayaSumber, Galamedia 20 Februari 2012
WhatsApp
Facebook
Telegram
Print
Twitter
Artikel Populer
-
-
5 Februari 2020 Dekan, Kolom Pimpinan
-
18 Desember 2019 Dekan, Kolom Pimpinan
Inspiratif
Berita Utama
-
25 April 2024