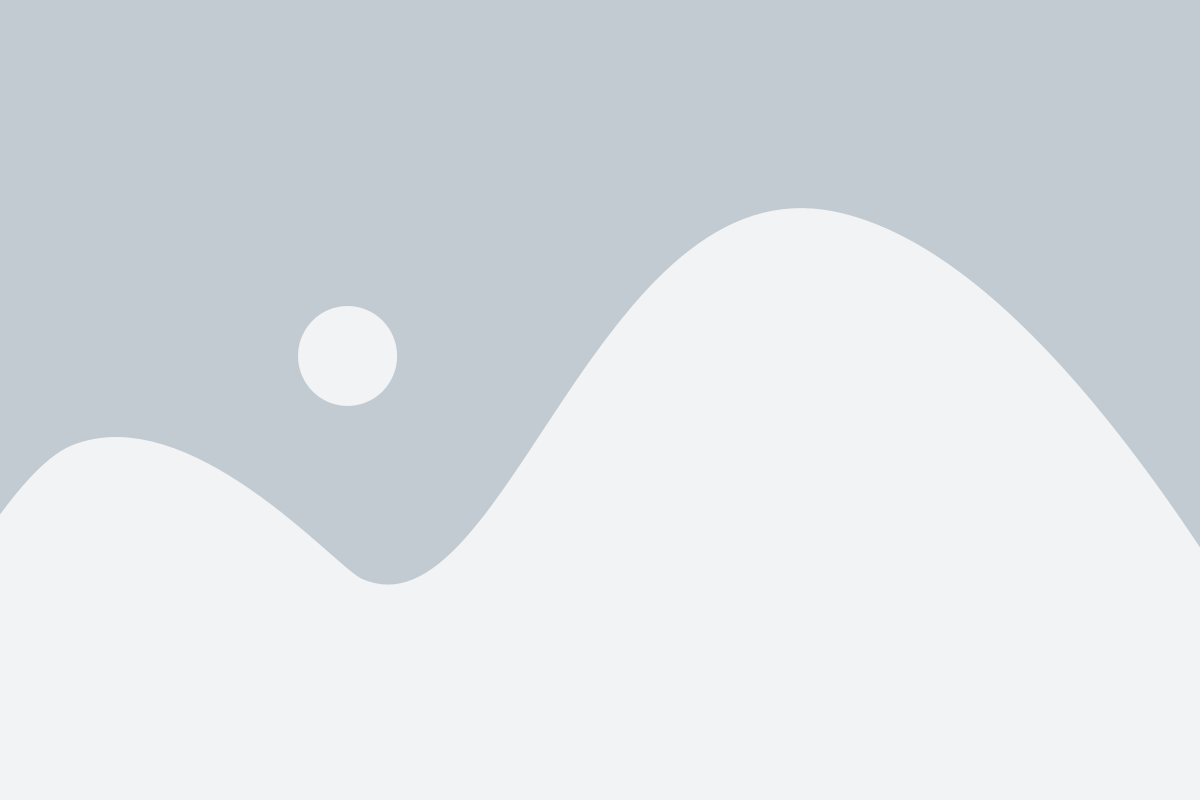Baru-baru ini ada berita bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengangap beberapa tayangan sinetron di televisi melecehkan agama. Perkaranya, dalam sinetron-sinetron itu ada tokoh haji yang perilakunya ditampilkan tidak mencerminkan akhlak kehajian, sembari menyombongkan diri, “Saya haji tiga kali!” Misalnya, dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji yang skenarionya ditulis oleh H Imam Tantowi.
Sialnya, sinetron jenis ini laris manis. Penonton menggemarinya sampai-sampai ada banyak sinetron sejenis bermunculan dengan tema yang hampir mirip: mencela ustaz sebagai sekadar fotocopy atau haji yang berperilaku lebih edan. Gejala apakah ini?
Ada rumus media yang kerap digunakan oleh produsen industri tontonan: apa yang banyak ditonton, itulah yang diinginkan pemirsa. Atas dasar prinsip ini, media harus melayaninya. Media tidak boleh melawan arus keinginan massa-pemirsa. Dengan begitu, bukan salah media jika tayangan “pelecehan‘ sejenis itu marak ditayangkan.
Semua itu menggambarkan keinginan dan kesadaran masyarakat tentang haji atau ustaz. Sisi lain, KPI atau MUI menginginkan “saringan‘ media. Letupan “keinginan‘ massa itu, bagaimanapun, tidak hadir sendirian; ia dipancing oleh tayangan artistik. Letupan “keinginan‘ massa hanyalah asap dari api yang dipercikkan media. Namun, tulisan ini tak hendak membicarakan fungsi media, tetapi lebih tertarik pada tesis pertama: apa yang banyak ditonton, itulah kesadaran massa.
Masyarakat Muak
Tokoh Haji Jamal dan Haji Muhidin digambarkan sebagai antagonis, namun fasih mengumbar kalimat suci agama. Ada juga tokoh ustaz yang menganggap dirinya “dirahmati Allah‘ sembari terus melakukan tipuan demi mengeruk keuntungan dari kebodohan umat. Semua itu dapat ditemukan dalam tayangan sinetron kita.
Ada apa di balik semua ini? Kemuakan dapat menjadi muasal dasar dari kecenderungan ini. Orang sudah muak dengan kepura-puraan yang diproduksi oleh pelakon media. Kepura-puraan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh para pemuka agama (haji atau ustaz), melainkan juga oleh semua pejabat publik. Lihat saja para pejabat negara yang dituduh korupsi: semua menampilkan diri tanpa rasa “malu‘. Semua berkilah benar dan berlindung pada asas “praduga tak bersalah‘.
Ketika media terus-menerus menayangkan situasi seperti ini, ada dua kemungkinan yang terjadi di benak masyarakat. Pertama, masyarakat akan menganggap kepura-puraan dan korupsi sebagai hal yang wajar dan lumrah, dan mungkin diam-diam akan melakukannya juga saat situasi memungkinkan. Kedua, masyarakat akan muak dan menolak. Jenis penolakannya bisa dalam bentuk bergabung dengan organisasi “negara dalam negara‘, atau dengan melakukan protes lain secara diam-diam.
Pada zaman kerajaan, ada ungkapan karikatural yang menyatakan, ‘Saat rakyat dipaksa menyembah Raja, rakyat akan bersujud sembari diam-diam mengeluarkan kentut‘. Rakyat bisa saja diam, namun ia terus melaksanakan protesnya dengan cara tak terduga. Salah satu caranya, bersepakat (tanpa ada komando) “melecehkan‘ pemuka agama.
Tentu, bukan saja pemuka agama yang melakukan kesalahan. Namun, hanya pada pemuka agama saja rakyat dapat secara bebas menunjukkan protes karikatural. Pemuka agama adalah aktor sosial yang sangat dekat dengan rakyat. “Pelecehan‘ merupakan ekspresi rasa sayang agar segera memperbaiki diri. Dibanding “pelecehan‘ terhadap pejabat negara, pelecehan terhadap “pemuka agama‘ tidak akan berbuah hukuman.
“Memiliki” dan “Menjadi”
Kritik karikatural melalui ramai-ramai menonton sinetron semacam itu adalah symptom dari masyarakat yang sakit. Ia seperti gejala ngilu pada persendian sebagai symptom awal bahwa asam urat di dalam darah di atas level normal (gout). Masyarakat yang sakit, bagi Erich Fromm, dibangun dari individu yang hidup dengan modus “memiliki” dan menolak untuk “menjadi”.
Ciri utama orientasi “memiliki” ialah kecenderungan memperlakukan setiap orang dan setiap hal menjadi miliknya. Memiliki berarti menguasai dan memperlakukan sesuatu sebagai obyek. Kata “milik” berkonsekuensi pada pembendaan, akhirnya muncul anggapan “segala sesuatu dibendakan” atau diperlakukan seperti benda.
Konsekuensi lainnya, orang yang berorientasi “memiliki” tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri karena tergantung pada simbol-simbol yang menjadi miliknya. Ketika mobilnya tergores, berdarahlah hatinya. Orang seperti ini dapat dianggap sebagai “terombang-ambing‘ pada apa yang menjadi miliknya.
Ketika “memiliki‘ menjadi ukuran kehebatan semua orang, masyarakat menjelma menjadi masyarakat serakah. Masyarakat serakah menganggap kegiatan memiliki, mempunyai dan mengambil untung sebagai hak suci bagi setiap individu. Pada masyarakat serakah sumber kekayaan tidak menjadi soal. Masyarakat seperti ini juga mendorong individu tidak menjadikan kepemilikan sebagai undangan untuk bertanggungjawab.
Symptom Kecil
Orientasi hidup “Memiliki” (To Have) berbeda dengan orientasi “Menjadi” (To Be). “Modus Menjadi menuntut agar kita membuang egosentrisitas kita dan sikap mementingkan diri sendiri,” kata Fromm. Orientasi “Menjadi‘ mengharuskan adanya kemauan memberi, membagi, dan berkorban.
Agamawan seharusnya mendorong perubahan dari modus “memiliki” menuju modus “menjadi”. Sebagaimana berhaji merupakan transformasi diri dari “memiliki” harta menuju pengorbanan demi “menjadi haji”. Sialnya, pada masyarakat serakah, modus menjadi ini diidap oleh banyak kalangan, termasuk agamawan.
Masyarakat serakah inilah yang melahirkan para penceramah agama yang menguantifikasikan jam ceramahnya dengan sejumlah uang honor dalam jumlah besar. Dengan seloroh mereka berkata, “Yang dilarang adalah menjual agama dengan harga murah‘. Pada sisi lain, pejabat menganggap jabatanya sebagai milik. Mereka lebih banyak menyatakan, “Saya memiliki jabatan X” daripada menyatakan, “Saya menjadi pejabat X”.
Haji juga demikian. Terutama ketika gelar haji harus diperoleh dengan uang yang tak sedikit, gelar “haji‘ menjadi sesuatu yang dimiliki melalui pembelian. Sering menunaikan ibadah haji menjadi prestise sosial, sementara karakter haji yang bagi Ali Syariati harus membangun “Rumah Kebaikan untuk Umat Manusia” terabaikan.
Semuanya menunjukkan orientasi “memiliki” atau masyarakat serakah. Sinetron itu hanya sebuah symptom kecil ketidakpercayaan rakyat pada “panggung‘ media. Sinetron itu bisa dilarang tayang kapan saja, tapi symptom kemuakan terus menyebar di benak masyarakat.
Bambang Q-Anees, Dosen Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung.
Sumber, Jurnal Nasional Jum’at, 10 May 2013