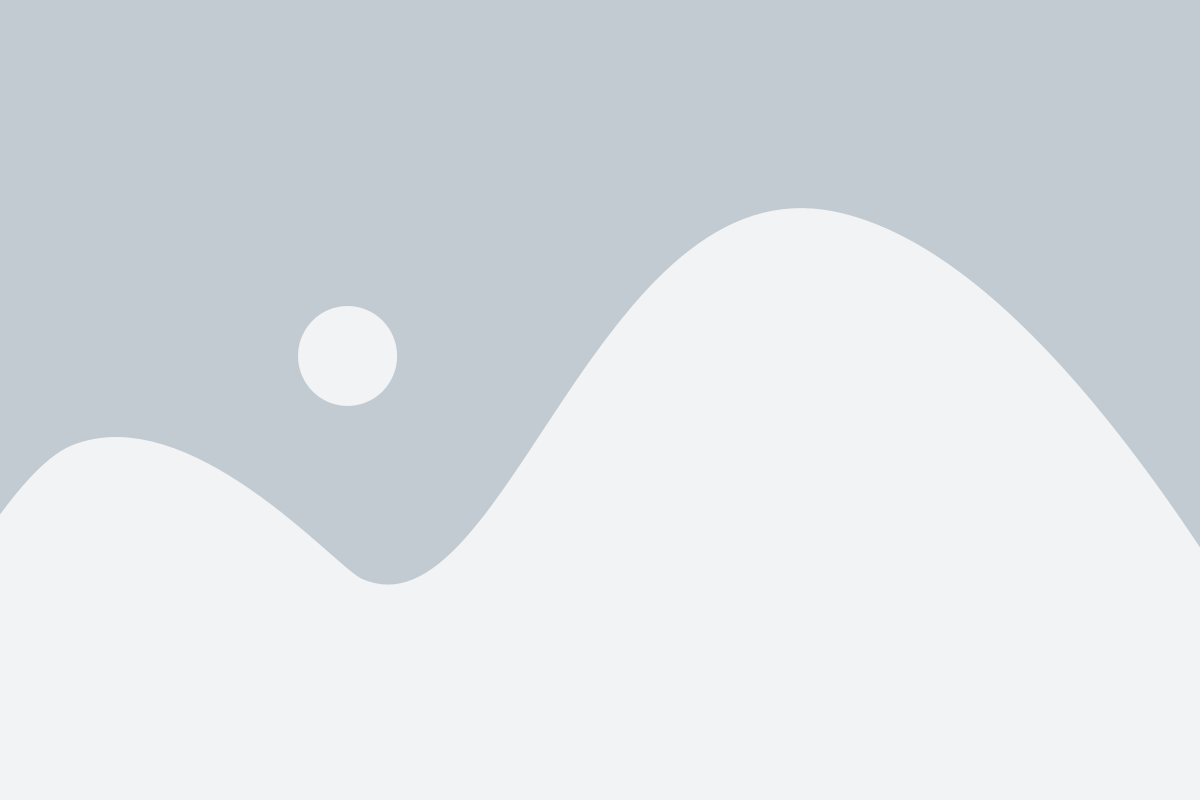Panggung politik Indonesia kembali diramaikan oleh kosa kata baru, “politik genderuwo”. Sebelumnya juga diramaikan oleh sejumlah kosa kata, seperti politik kebohongan, ekonomi kebodohan, politik sontoloyo, tampang Boyolali, dan sebagainya. “Politik genderuwo” ini dicetuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang notabene juga sebagai kandidat presiden Pilpres 2019, ketika ia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, untuk membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/18).
Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa “politik genderuwo” itu merujuk pada seluruh praktik politik sejumlah pihak yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti, menciptakan rasa kekhawatiran, dan menciptakan sikap pesimisme pada masyarakat.
Ragam Arti Genderuwo
Kata genderuwo itu sendiri dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) memiliki arti hantu yang konon serupa manusia yang tinggi besar dan berbulu lebat. Oleh karena itu, genderuwo menjadi subjek khayalan dalam dunia hantu yang kerjaannya menakut-nakuti manusia.
Pada masyarakat pedesaan tempo dulu, genderuwo sering kali dijadikan sebagai salah satu kata pamungkas orang tua ketika hendak memerintahkan anak-anaknya yang terus saja bermain di luar rumah menjelang malam, dengan ucapan “awas nanti ada genderuwo”.
Di samping itu, genderuwo juga menjadi salah satu judul dongeng orang tua kepada anak-anaknya agar tercipta sosok lain yang ditakuti oleh anak-anak, dan pada akhirnya mereka diharapkan akan turut (meminta perlindungan) kepada orang tua.
Lain lagi manakala digunakan di dunia sinetron atau film, genderuwo menjadi karakter antagonis yang memperagakan gangguan-gangguan mistis kepada manusia. Di pertengahan dan akhir cerita, biasanya sosok genderuwo tersebut harus berhadapan dengan tokoh agama yang taat (karakter protagonis) untuk mengusir atau bahkan memusnahkannya.
Pertanyaannya, apakah penggambaran genderuwo seperti di atas memiliki kesamaan dengan apa yang tengah dipraktikan di dunia politik seperti sekarang ini? Jawabanya, jelaslah ada kesamaan di balik tentunya juga ada perbedaan.
Persamaannya terletak pada definisi tentang genderuwo, yaitu sosok khayalan dunia hantu yang sangat menakutkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada bagaimana genderuwo diposisikan. Jika dalam tradisi mayarakat pedesaan tempo dulu, dongeng, dan dunia sinetron atau film, genderuwo diposisikan sebagai sarana manipulasi memori dan komoditi ekonomi, maka dalam politik aktual, genderuwo cenderung diposisikan sebagai sarana rekayasa kata-kata atau diksi dalam upaya merebut hati dan simpati para calon pemilih.
Senjata dan Do’a
Genderuwo dengan definisi dan ragam posisinya tersebut di atas memiliki keseragaman konotasi, yakni menunjukkan kenegatifan, karena mengandung keseraman dan ketakutan. Oleh karena itu, pesan yang dikonstruksinya pun cenderung selalu negatif, baik bagi sumber, saran yang digunakan, maupun bagi para penerima pesannya.
Padahal banyak disampaikan bahwa kata adalah senjata. Selain itu, disampaikan juga bahwa kata adalah do’a atau harapan. Dengan itu, kata sejatinya selalu melekat dengan makna-makna positif agar bisa menjadi senjata yang baik dan benar serta menjadi do’a yang positif bagi semua pihak terkait.
Istilah kata adalah senjata mengajarkan kita untuk menggunakan kata dengan efektif dan produktif. Senjata itu bisa digunakan untuk menyerang orang lain, bisa juga menyerang sang pemiliknya, seperti dalam istilah “senjata makan tuan”. Sementara itu, istilah kata adalah do’a mengajarkan kita untuk menggunakan kata secara baik dan benar.
Dalam istilah yang disebutkan terakhir, kata itu ibarat bibit, ketika mengucapkan sesuatu, berarti telah memberikan kehidupan pada kata-kata itu. Artinya, jika bibitnya buruk maka memberikan kehidupan buruk pada kata-kata. Sebaliknya, jika bibitnya baik maka dapat memberikan kehidupan yang baik pula pada kata-kata.
Oleh karena itu, orang bijak selalu berujar “hati-hati dengan kata-kata, karena perkataan sejatinya adalah do’a”. Makanya, jika suatu kata diucapkan diulang-ulang, kerap menjadi kenyataan. Seperti kata-kata bahwa “politik itu jahat” dengan diulang-ulang, maka politik itu selamanya akan terasa jahat, atau akan selalu disi oleh orang-orang jahat.
Kata yang Baik
Berdasarkan itu, baik atau buruknya kehidupan yang diberikan kepada politik sebagai kata sekaligus sebagai aktualita sebenarnya sangat tergantung pada pilihan kata lain yang diikutkannya. Memang sejauh ini persepsi masyarakat umum lebih banyak melihat bahwa politik itu kotor atau jahat.
Sepintas, hal demikian itu dapatlah dimaklumi, karena masyarakat umum cenderung belum bisa memisahkan antara cita dan realita politik. Atau juga belum mampu membedakan antara politik sebagai sarana nilai-nilai dengan sebagai ekspresi-ekspresi aktor yang mendayagunakan sarana tersebut.
Persepsi masyarakat itu seolah mendapatkan legitimasi ketika para aktor dan elit kekuasaan justru gemar melontarkan kata-kata buruk yang dialamatkan pada politik. Selain itu, para aktor dan elit kekuasaan malah lebih banyak memperagakan ekspresi-ekspresi politik yang mengingkari fitrah politik, yaitu politik sebagai sarana ekspresi perayaan kemanusiaan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan kebaikan untuk banyak orang.
Oleh karena itu, pada momentum Pemilu 2019 ini, belumlah terlambat, masih ada waktu kurang lebih lima bulan ke depan untuk sama-sama saling mengingatkan mengenai pentingnnya perbaikan persepsi dan harapan masyarakat umum tentang kehidupan politik.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama misalnya, para kontestan Pemilu 2019, baik kontestan Pilpres maupun kontestan Pileg, harus lebih banyak memperagakan etika dan nilai-nilai persatuan serta persaudaraan dalam setiap sikap dan perilaku politiknya. Ingat, perilaku dan sikap politik itu mencerminkan kedalaman dan keluasaan pengetahuan politik yang dimilikinya.
Dan kedua, seluruh aktor dan elit politik, terutama kedua pasangan kandidat presiden dan wakil presiden, harus mampu dan mau memilih kata-kata yang baik dalam setiap berkomunikasi publik dan berkampanye politik.
Melalui kedua langkah itu, setiap orang tidak lagi mudah terpengaruh untuk menjadi alergi dan picik dengan politik. Namun, mereka bisa menjadi lebih sukarela sekaligus sukaria dalam berpartisipasi politik, termasuk partisipasi bagi pemenuhan hak-hak politiknya. Wallau’alam bishawaab.
Asep Sahid Gatara, Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Sumber, Harian Umum Pikiran Rakyat, 12 November 2018