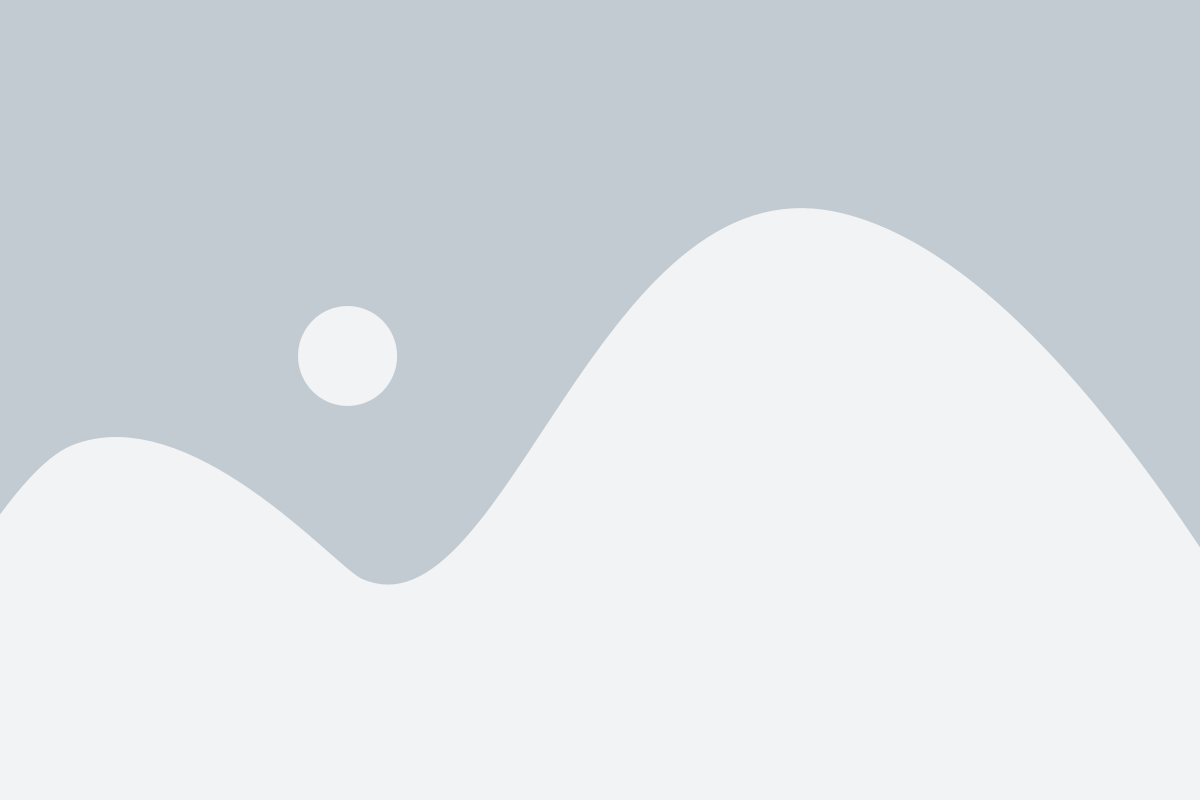(UINSGD.AC.ID)-Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia dari periode ke periode senantiasa berada pada pusaran politik. Entah itu politik praktis ataupun politik nilai. Namun demikian, menarik untuk disimak kemudian, apakah hal yang sama berlaku, terutama politik praktis, bagi NU periode hasil Muktamar ke -34 di Lampung, 22-24 Desember 2021. Muktamar yang mengantarkan KH Miftachul Akhyar terpilih kembali sebagai Rais Am PBNU periode 2021-2026 dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Tanfidziyah, menggantikan KH Said Aqil Siroj.
Secara retorik, penjelasan atau jawabannya sudah bisa publik peroleh ketika Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, telah berkomitmen akan menjaga NU agar jangan terlalu dekat dengan politik praktis, salah satunya soal Pemilu 2024 (detikcom, 27/12). Bahkan ia, sebagaimana banyak dikutip media massa, menegaskan tidak bakal ada calon presiden dan wakil presiden berasal dari PBNU. Kader nahdliyin diperbolehkan mengikuti kontestasi politik asalkan tidak duduk di jajaran PBNU.
Jawaban di atas, meskipun bersifat retorik, telah memberikan gambaran awal bahwa NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya tidak akan dibiarkan terjebak pada pusaran politik praktis. Namun demikian, publik tentu akan menunggu lagi apakah jawaban itu, secara praktis, adalah akan relevan. Terutama setelah melewati proses pengujian politik di lapangan, paling tidak untuk lima tahun ke depan.
Bagi NU, menjalankan komitmen tersebut sesungguhnya adalah pekerjaan yang tidaklah mudah karena pusaran politik praktis pernah begitu akrab. Pada Orde Lama misalnya, NU menjadi bagian dari Masyumi, lalu pada Pemilu 1955 memisahkan diri menjadi partai politik. Pada awal Orde Baru, NU pernah bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lantas menarik diri dan kembali ke khittah 1926. Ketika Reformasi 1998, para tokoh ormas ini mendirikan sejumlah partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan lain sebagainya.
Tetapi, bukan berarti NU, terutama secara jam’iyyah (organisasi, tidak bisa melepaskan dari politik praktis. Sejarah mencatat NU juga pernah berhasil menunjukkan kepiawaiannya menjauhi arena politik praktis dengan khittah 1926-nya. Selain itu, NU juga memiliki modal dasar berupa genetik politik substansialistik. Politik dalam pengertian yang sebenarnya.Yaitu, soal mengangkat dan merawat kemaslahatan umum atau kebaikan bersama.
Politik substansialistik itu berbeda dengan politik legalistik atau formalistik yang banyak diusung oleh partai politik berbasis agama. Mengutip Bahtiar Effendy (2000), politik formalistik cenderung menghasilkan tata kelola kebangsaan yang zero some game-ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan, dan semangat eksklusivitas keagamaan.
Dalam kenegaraan, politik substansialistik menghasilkan religious state bukan theocratic state (Munawir Sjadzali). Konsep bernegara yang kendatipun secara legal-formal tidak mendasarkan pada ajaran agama tertentu, namun memperhatikan kepentingan-kepentingan keagamaan masyarakat. Negara memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait hal-hal keagamaan.
Sedangkan dalam keagamaan, politik substansialistik menghasilkan moderasi dan toleransi. Praktik beragama yang berjangkarkan pemahaman keagamaan yang moderat serta dengan ekspresi yang mengakui dan melintas perbedaan.
Dengan demikian, politik substansialistik lebih fokus pada tujuan atau isi, sementara politik formalistik lebih tersibukkan pada prosedur dan bungkus atau cangkang dalam mencapai tujuan. Bahkan dalam kadar tertentu, bungkus tersebut acapkali berubah menjadi tujuan, seraya meminggirkan tujuan yang sesungguhnya.
Kemanusiaan
KH Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur misalnya, salah satu tokoh besar NU yang belakangan akan ‘dihidupkan lagi’ oleh Gus Yahya, menyatakan bahwa yang terpenting dari politik adalah kemanusiaan. Ini artinya, kemanusiaan merupakan tujuan dari setiap aktivitas politik.
Di sini politik kemanusiaan potensial bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi NU kini dan ke depan. Potensi yang kemudian harus didayagunakan, terutama melalui politik nilai, agar ia tidak hanya fungsional atau bermanfaat untuk lingkungan nasional namun juga untuk lingkungan internasional.
Di antara praktik terbaik dari pemikiran itu adalah peristiwa fenomenal saat NU melalui para tokohnya, termasuk KH Wahid Hasyim, pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18 Agustus 1945, mampu dan mau menerima dihapuskannya tujuh kata (“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) pada sila pertama Pancasila hasil dari sidang BPUPKI dengan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945.
Suatu penerimaan atas dasar adanya kepentingan yang lebih besar, yaitu ajeknya kemerdekaan Indonesia yang berkesatuan dan berkemaslahatan umum. Selain itu, kukuhnya kebangsaan Indonesia yang baru saja terbangun pasca proklamasi 17 Agustus 1945.
Praktik terbaik lainnya adalah penerimaan NU, di tengah derasnya penolakan, terhadap kebijakan Rezim Orde Baru perihal asas tunggal Pancasila. NU menerima asas tunggal tersebut dengan argumen bahwa Pancasila adalah falsafah bukan agama dan tidak akan menggantikan agama. Selain itu, asas-asasnya tidak sama sekali bertentangan dengan agama (Islam).
Kemudian, peristiwa kontroversial saat Gus Dur membuka komunikasi dengan Zionis Israel di tengah arus besar anti-Israel di Indonesia dan dunia. Anti karena Israel dinilai sebagai negara penjajah yang menurut konstitusi Indonesia harus dihapuskan dari muka bumi.
Gus Dur memilih melawan arus dengan pengorbanan menjadikannya tidak populer di mata publik agar penyelesaian konflik Israel-Palestina tergapai secara damai tanpa ada lagi pertumpahan darah atau korban nyawa manusia. Semua pihak yang berkonflik, ataupun pihak-pihak ikut serta terseret konflik, merasa menang dan tidak ada yang merasa dikalahkan.
Komitmen dan deretan praktik politik substansialistik di atas menjadikan NU senyatanya memiliki keluhuran pengetahuan dan kekayaan pengalaman dalam memerankan jam’iyyah-nya secara nasional dan internasional. Peran yang semata bukan untuk kekuasaan, namun demi berdiri tegaknya nilai-nilai kemanusiaan di mana pun serta kapan pun dengan cara-cara yang adil dan beradab. Wallahu’alam bi shawab.
Asep Sahid Gatara Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Wakil Ketua Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL)
Sumber, detikNews 4 Januari 2021: