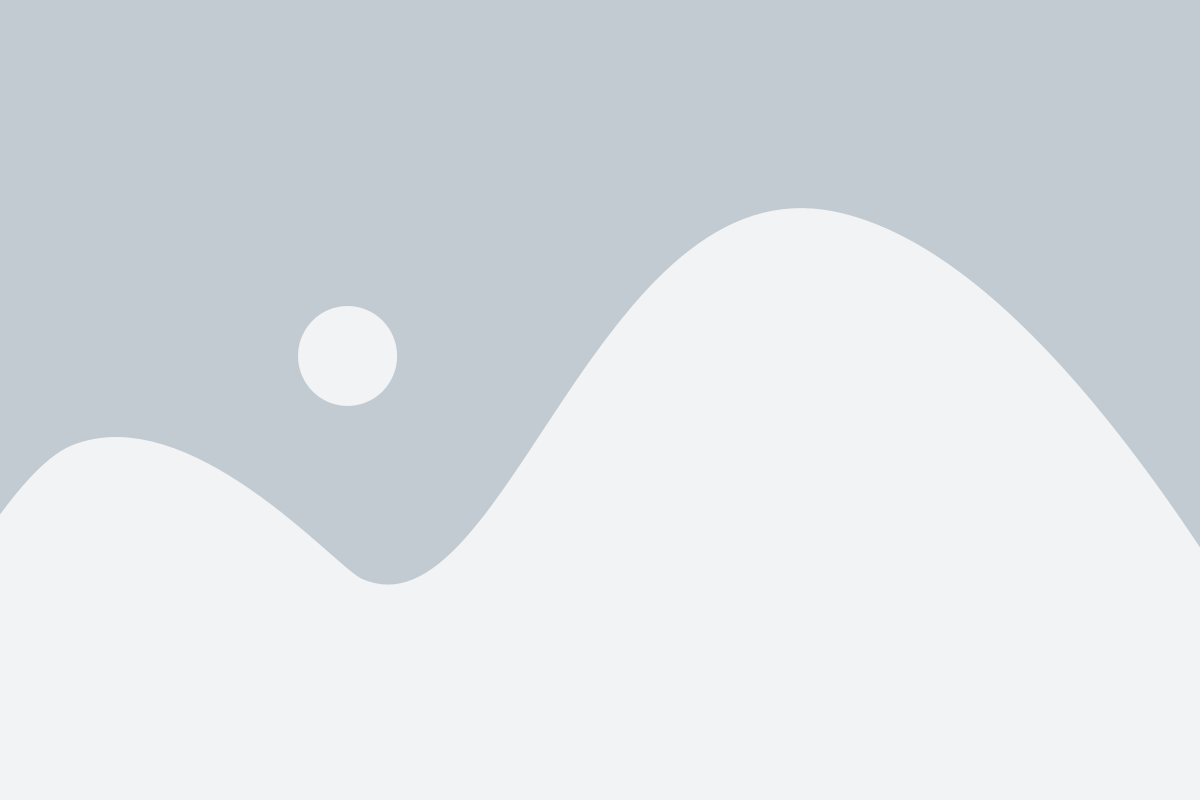(UINSGD.AC.ID) Keterbukaan Pak Presiden Joko Widodo atas berbagai kritik yang dilontarkan warga negara dinilai nyaris kontra-realitas dengan fakta di lapangan. Beberapa fakta menunjukkan sejumlah warga harus rela berurusan hukum karena kicauan di media sosial dianggap mengkritik Pemerintah dengan dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat, hingga Oktober 2020, sebanyak 10 peristiwa dan 14 orang diproses karena mengkritik Presiden Jokowi; 14 peristiwa dan 25 orang diproses dengan objek kritik Polri, dan 4 peristiwa dengan 4 orang diproses karena mengkritik Pemda.
UU ITE
Salah satu “kambing hitam” kontra-realitas tersebut yang muncul ke permukaan dan menjadi bahasan aktual adalah pasal “karet”, terutama dalam UU ITE. Padahal, beberapa pasal yang dinilai “karet” pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016.
Pada UU lama, sejumlah pasal “karet” menjadi sangat menakutkan. Tindak pidana delik fitnah dan pencemaran nama baik pada Pasal 27 UU ITE diancam pidana 6 tahun, sehingga tersangka dapat langsung ditahan. Setelah mendapat kritik publik dan banyak kasus yang viral, DPR merevisi UU ITE. Ancaman pidana Pasal 27 ayat (3) diturunkan menjadi 4 tahun, sehingga penegak hukum tidak lagi dapat langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kendati substansi pasalnya tetap “karet”, tetapi dapat mengurangi resiko tinggi bagi tersangka.
Namun, kerja bagus DPR ternyata belum tuntas karena pada UU ITE baru masih terdapat pasal “karet” yang juga beresiko tinggi. Pelanggaran pasal “hoax” serta menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA pada Pasal 28 masih tetap berkonsekuensi ancaman pidana 6 tahun. Pasal ini pula yang acapkali dijadikan dasar menjerat dan menahan tersangka yang kritis terhadap Pemerintahan.
Oleh karena itu, para cerdik pandai, termasuk Pak Jokowi memberikan prioritas agar revisi terhadap UU ITE segera “dituntaskan”. Selain memberikan substansi berkepastian hukum pada pasal “karet” juga memberikan space lebih luas bagi tumbuhnya demokrasi egaliter. Budaya kerelaan dan keiklasan untuk dikritik dan mengkritik dengan santun dan bertanggungjawab harus tumbuh dalam substansi pasal per pasal UU ITE revisi baru.
Pasal “Karet”
Kendati sejatinya nyaris tidak mungkin mengkikis pasal-pasal “karet” karena merupakan sunatullah bahwa kepastian dan kesempurnaan bukan milik manusia. Sehebat apapun DPR, Pemerintah, dan para pakar hukum, dapat dipastikan tidak akan bisa menjawab semua harapan publik. Persepsi dan imajinasi manusia sangat kaya dan teramat sulit untuk diterjemahkan dengan rangkaian kata, barisan kalimat, dan kolom-kolom paragraf.
Apalagi, eksistensi pasal “karet” merupakan fakta historis perjalanan panjang sejarah hukum yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karakteristiknya sudah merasuk pada nyaris semua peraturan perundang-undangan, sehingga dilematikanya terus mewarnai perdebatan di antara para pihak dan korban pun sudah bergelimpangan.
Secara prosedural, untuk menerjemahkan pasal “karet”, tidak selamanya harus serta merta merevisi pasal-pasal dalam UU. Selain memiliki penjelasan, setiap UU dimungkinkan, bahkan sebagian diperintahkan ada turunannya, seperti Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang lebih rendah, tetapi dapat lebih rinci menjelaskan substansi pasal per pasal. Namun, kadang itu pun tidak dapat menjadi solusi dan menjangkau kekayaan persepsi. Selalu saja tarfsir yang berbeda terjadi, sehingga karakteristik “karet” tidak dapat dihindarkan.
Oleh karena itu, merevisi pasal UU bukan satu-satunya solusi. Apalagi faktanya pasal “karet” nyaris ada pada setiap UU dan terkadang antara satu substansi UU terkait juga dengan UU lainnya. Seperti halnya substansi pasal “hoax” dan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA ternyata ada juga pada KUHP. Pelarangan penyebaran “virus hoax” terdapat juga pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
Keberadaan pasal “karet” seharusnya menjadi tantangan profesional bagi penegak hukum untuk mem-fakta-kannya melalui pase penyelidikan dan penyidikan. Makanya, profesionalitas penegak hukum merupakan persoalan yang juga harus mendapat perhatian dalam mencari solusi pasal “karet” karena profesionalitas menjadi sandaran bagi nasib warga dalam pembuktian ketisakbersalahan dan keadilan dalam penghukuman.
Hukum Komunikasi
Apalagi pendekatan hukum modern lebih integratif. Multidimensional khasanah keilmuan telah men-setting sebuah persoalan tidak hanya dapat diselesaikan dengan satu pendekatan, tetapi harus dengan multidisiplin. Karakteristik hukuman tidak lagi penyiksaan, tetapi pendidikan.
Penegakan hukum dapat saja di antaranya menggunakan pendekatan komunikasi. Dalam kajian hukum komunikasi, proses penegakan hukum merupakan proses komunikasi resiprokal mutualisme. Persidangan adalah setting media komunikasi terjadinya transaksi dan transformasi pesan. Ada hakim, ada penuntut dan pembela, ada penggugat dan tergugat, ada replik ada duplik, dan istilah lainnya yang menyurat proses komunikasi, sehingga putusan adalah kesepakatan dari fakta-fakta pesan yang disajikan para pihak.
Apalagi beberapa kasus tertentu, menyiratkan penyelesaian tidak harus berujung di meja hijau, tetapi melewati meja mediasi. Netralitas mediator terdepan dan win win solution menjadi putusan tertinggi agar semua happy. Hal itu dapat menjadi alternatif solusi menghadapi pasal “karet”. Terlebih substansi UU ITE dalam persinggungan erta hukum dan komunikasi, sehingga pasal sengketalah yang seharusnya diefektifkan, bukan memaksa menjeratkan pasal pidana untuk memenjarakan. ***
Mahi M. Hikmat, Dosen Fakultas Ada dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djatidan Penulis Buku Etika dan Hukum Pers.
Sumber, Pikiran Rakyat 23 September 2021.