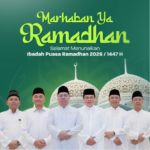UINSGD.AC.ID (Humas) — Zakat merupakan kegiatan yang menghubungkan dua kelompok masyarakat, yaitu kaya dan miskin. Secara mekanis, apabila terjadi transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, kekayaan agregat tidak akan berkurang, malah bertambah. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa zakat (atau apa pun nama transfer tersebut) memberikan sumbangsih dalam penurunan kemiskinan.
Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika zakat dipandang, dalam proporsi yang lebih besar, sebagai fenomena ekonomi. Namun demikian, dalam konteks akademik, sikap menahan diri dari penarikan kesimpulan “teologis” adalah pilihan terbaik. Tanpa bukti empirik yang berasal dari hasil penelitian di ranah ekonomi, pernyataan ini tetap merupakan proposisi asumtif.
Tanpa bermaksud menafikan produk interpretasi disiplin ilmu turats non-ekonomi, mengkaji zakat sebagai fenomena ekonomi dalam proporsi yang lebih besar dipandang semakin memperkuat (atau bahkan dianggap sebagai mukjizat dari) kesimpulan yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu turats tersebut.
Dampak sinergi-akademik ini akan memperkuat posisi dan fungsi semua lembaga pengkajian Islam, sesuai dengan objek kajiannya masing-masing. Fenomena filantropis, modal sosial berbasis iman, dan perilaku ekonomi masyarakat Muslim (baik individu maupun pranata) secara otomatis akan berubah menjadi laboratorium Ekonomi Islam, terutama dengan menjadikan zakat sebagai kajian utamanya.
Tulisan ini mengungkap gagasan tentang reformulasi zakat untuk kesejahteraan masyarakat dalam konteks negara-bangsa. Untuk konteks Indonesia, dengan melihat konsep kemiskinan yang diperluas, ditemukan peluang pendistribusian zakat pada sejumlah aspek yang memerlukan penanganan lebih serius.
Bersanding dengan pendidikan dan kesehatan, dana zakat yang dikeluarkan dapat mencerminkan kondisi daya beli masyarakat Muslim. Oleh karena itu, di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, ukuran zakat dapat dijadikan sebagai ukuran untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Dengan pendekatan teologis-normatif yang menyimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban individu dengan dampak sosial, tulisan ini mengarah pada pendekatan normatif-historis yang menyatakan bahwa penerima (mustahiq) zakat tidak hanya terbatas pada kelompok Muslim. Penerima zakat bisa saja non-Muslim, dan tujuan area distribusinya menggunakan konsep desentralisasi, tanpa menghilangkan kebolehan sentralisasinya.
 Dengan pendekatan filantropis, zakat dipandang sebagai tradisi masyarakat yang dapat menjadi perekat sosial, sebagaimana dikemukakan dalam pendekatan modal sosial. Pendekatan ilmu ekonomi memperkuat pembahasan reformulasi zakat untuk kesejahteraan bangsa ini. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.
Dengan pendekatan filantropis, zakat dipandang sebagai tradisi masyarakat yang dapat menjadi perekat sosial, sebagaimana dikemukakan dalam pendekatan modal sosial. Pendekatan ilmu ekonomi memperkuat pembahasan reformulasi zakat untuk kesejahteraan bangsa ini. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.
Untuk mengetahui tulisan utuhnya, dapat diunduh pada laman ini.
Prof. M. Anton Athoillah, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Sumber: Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014, hlm. 491-576