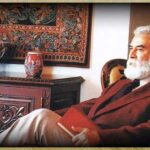“Ayu batur beresana syareate, boh menawa bakal nemu hakekate”
Luput dari amatan sains modern yang menyajikan fakta terindra sebagai hal yang harus dipercaya, realitas kehidupan manusia juga menyimpan entitas lain yang menuntut untuk diketahui. Realitas itu mungkin tersembunyi, tak bisa nampak menjelma sebagai fakta yang terindra, tapi senyatanya ia sering menjadi wilayah yang menyedot perhatian dan rasa ingin tahu manusia.
Dalam kajian antropologi agama, yang tersembunyi itu adalah “misterium tremendum” tapi pada saat yang sama ia juga adalah “misterium fascinosum”. Manusia bisa ngeri atau terperangkap dalam kubangan khawatir bahkan takut tapi ia kerap menggoda sebagai pesona yang memunculkan hasrat untuk diketahui.
Yang “tremendum” itu seumpama gelap, tidak jelas mana arah, tanpa wujud dan sering menjadi misteri. Tapi karena gelap dan misteri itu manusia diam-diam suka terbujuk karena magnet pesona yang ditimbulkannya.
Bahkan yang-tersembunyi itu sering nampak dalam wajah mistik, supra natural atau bahasa popnya adalah “dunia-lain”. Filsafat menyebutnya sebagai dimensi metafisika. Dunia tarekat menyebutnya sebagai hakikat. Sebutan-sebutan itu hanya ingin menunjukkan bahwa di sebalik dunia fisik ada juga dunia lain, dunia yang melampaui fisik atau dunia non-fisik.
Kursi yang dilihat adalah forma benda, ia memiliki bentuk dengan ciri dan definisi. Tapi kursi sebagai “kursi pada dirinya” (something it self) hanya bisa diketahui melalui abstraksi. Seumpama menyelam ke lautan yang dalam tanpa dasar itulah abstraksi. Yang berbentuk adalah fenomena (yang nampak) sedang yang tak berujud adalah noumena (benda pada dirinya sendiri).
Beragama secara umum adalah meyakini yang noumena itu. Kitab suci menegaskan percaya terhadap yang tak nampak (gaib) adalah bukti keimanan (الذين يؤمنون بالغيب). Malaikat, jin, syetan, hari kiamat adalah unsur-unsur dunia gaib. Apakah ia berwujud fisik? Pada masanya mungkin ia bisa diketahui dan menjadi realitas yang dialami. Tapi rumus agama menegaskan percayailah bahwa mereka ada. Tak perlu bertanya apa dan bagaimananya.
Mendekati yang-tersembunyi dan hasrat untuk mengetahuinya tak bisa dengan cara yang biasa. Sains modern yang menahbis logika ilmiah pasti kesulitan bahkan bisa gagal merumuskannya. Metode ilmiah adalah langkah pasti dari mulai proposisi logis-hypotetis-verifikasi. Tak ada asumsi mistis, supra natural atau sesuatu yang noumena di dalamnya. Dimengerti, jika sains modern menampik secara tegas seluruh yang-tersembunyi.
Dalam laku tarekat, yang-tersembunyi sebagai haikat jika ia ingin diketahui membutuhkan “sikap pasrah”. Melampaui pasrah dibutuhkan juga kepekaan indera manusia. Indera yang peka adalah yang terasah oleh tempaan latihan (riyadoh) dan doa (wirid) yang didawamkan. Dalam laku tarekat, yang tersembunyi sebagai hakikat juga ma’rifat hanya mungkin diketahui jika syariat dan tarekatnya tertib dilakukan. Sekalipun tidak ada jaminan menemukan hakekat, melaksanakan syareat dan tarekat adalah kemestian. Sesuatu yang imperatif untuk dilakukan. Maka berlakulah sebuah tuturan nadhom “ayu batur beresana syareate, boh menawa bakal nemu hakekate” (mari, kita membereskan laku syariat mudah-mudahan kita menemukan yang hakikat).
Ibadah-ibadah ritual wajib yang kita lakukan adalah laku syariat. Terhadap seluruh ibadah itu kepatuhan adalah kuncinya. Menemukan yang tersembunyi sebagai hakikat ibadah mustahil didapatkan jika laku syariat ibadah wajib tidak dilaksanakan.
Bahkan dalam laku tarekat, tak hanya sekadar kesanggulan melaksanakan ibadah yang wajib, patuh pada tuntunan, taat pada perintah Guru (mursyid) adalah jalan yang sangat menentukan untuk menemu hakikat ibadah.
Namun begitu, yang-tersembunyi sebagai hakikat atau makrifat tak selalu muncul dan hadir karena diusahakan, tapi ia kerap mengada karena inisiatif dan campur tangan Tuhan. Dalan istilah filsafat, Itulah “aleitheia” sebuah “ketersingkapan ada sebagaimana adanya”.
Ketekunan, kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah yang wajib disertai kepatuhan kepada tuntunan Guru mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk menemukan yang tersembunyi dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Allahu a’lam.[]
Dr. Radea Juli A. Hambali, M.Hum, dosen Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung.