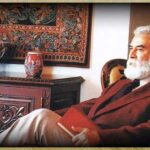(UINSGD.AC.ID) — Tradisi sufi menempatkan perempuan dalam posisi yang istimewa, bahkan menurut Ibnu Arabi, persaksian terhadap Tuhan dalam diri perempuan merupakan bentuk “persaksian” yang sempurna.
Di tepi lain, Rumi mengemukakan ikhwal serupa. Menurutnya, “perempuan adalah pantulan cahaya ilahi, bukan pelampiasan birahi. Tidak, konon dia bukan makhluk biasa, dia bahkan mencipta”.
Tampak dengan jelas, Ibnu Arabi juga Rumi meneguhkan ikhwal yang sama, bahwa kehadiran perempuan tidak bisa dianggap sepele. Karena ia “bukan makhluk biasa” maka kehadirannya tidak sekadar pelengkap laki-laki tapi juga menjadi titik epicentrum pengenalan manusia terhadap Tuhan.
Sekalipun perempuan disebut sebagai jalan pengenalan dan bentuk persaksian yang paling sempurna terhadap Tuhan, tradisi sufi mengakui juga bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam posisi setara. Jika Tuhan mencipta Adam tanpa Hawa, mungkin tak ada “rindu” dan “dendam”. Mungkin juga tidak dikenal “jalal” dan “jamal”. Mungkin juga tidak diketahui “marah” dan “rahmat”.
Sedemikian terhormatnya posisi perempuan dalam Islam demikian juga perkara kesetaraan. Lalu dari mana akar kekerasan berlangsung? Ada banyak jawaban yang bisa diberikan. Mungkin soal budaya. Barangkali soal persefsi juga anggapan tradisi.
Dalam tradisi pemikiran, muasal kekerasan bisa dilacak dari pemetaan “subjek-objek”. Terutama dalam tradisi Cartesian yang meletakkan subjek sebagai “pusat” kebenaran. Pusat yang “cukup diri”. Lalu lahirlah terma “biner-oposisi”: dua hal yang berlawanan tetapi yang satu diletakkan secara istimewa dan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Turunan biner-oposisi melahirkan “kuat-lemah”, “atas-bawah”, “kaya-miskin”, “maskulin-feminin” dan seterusnya.
Subjek adalah pusat sedang objek adalah wilayah asing yang keberadaannya tergantung persefsi subjek. Objek adalah “the other” atau “liyan” yang dalam prakteknya kerap menjadi korban persekusi bahkan stigma negatif.
Relasi subjek-objek sering tidak seimbang sebab pola relasi yang dipakai sebagaimana menurut Martin Buber adalah relasi “I-It”. Aku berkomunikasi denganmu tapi keberadaanmu tidak seimbang dengan keberadaanku. Di hadapanku kamu adalah benda asing. Demikian.
Sebaliknya, dalam Islam seperti yang diwakili tradisi sufi. Relasi yang berlangsung adalah “Subjek-subjek” yang dalam pola Buber berlangsung dalam “I-Thou”. Kamu dan aku berada dalam posisi yang sama. Pengenalan tentang aku terjadi karena ada kamu begitu juga sebaliknya.
Alhasil. Kekerasan terhadap perempuan bukan soal tradisi atau budaya belaka. Dalam prakteknya, ia seolah mendapat “pembenaran” dalam epistemologi pengetahuan. Menanggulangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan itu juga adalah perkara membereskan epsitemologi pengetahuan sebagai akarnya. Allahu a’lam[]
Dr. Radea Juli A. Hambali, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung