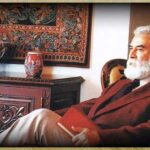(UINSGD.AC.ID) — Sampai saat ini kita baru punya satu-satunya norma hukum tertinggi sebagai pengatur kehidupan bernegara, yaitu Konstitusi, sebagai kerangka dasar operasi negara ini. Konstitusilah yang menentukan struktur pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, sistem hukum yang berlaku, dan lembaga negara.
Kita telah bersepakat bahwa hanya Konstitusi yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan urusan pemerintahan. Betul, ada klaim bahwa Kitab Suci (agama) dapat dijadikan alat pengatur, namun ia memiliki keterbatasan daya jangkau, tidak bisa lintas batas keyakinan karena tidak diproduk oleh hasil kesepakatan manusia. Ayat-ayatnya tidak dapat dieja untuk diberlakukan secara menyeluruh dengan daya jangkau luas dan lintas batas. Begitu halnya etika dan budaya tidak bisa diandalkan untuk menggantikan fungsi dan peran Konstitusi.
Karena hanya satu-satunya pengatur bernegara yang telah disepakati, Konstitusi harus dijaga ketahanannya agar tetap memiliki daya tahan yang kuat, kokoh, berfungsi dan memaksa. Pemerintah, individu, dan berbagai lembaga harus tunduk dan tidak bertentangan dengan “ayat-ayat Konstitusi”. Pemerintah, individu Masyarakat, pelaku sektor publik juga swasta tidak bisa melakukan atau membuat sesuatu yang bertentangan dengan “firman Konstitusi”.
Ketahanan konstitusi (constitutional resilience) menjadi semakin relevan di negara kita karena sejumlah tekanan dan ancaman yang bisa “merungkadkan” Konstitusi. Ketahanan Konstitusi harus kita perkuat agar ia menjadi alat yang tetap hidup dan efektif dalam mengatur berbagai unsur dan elemen negara ini.
Kepentingan Politik
Kita terus “berkoar” bahwa agar Konstitusi tidak “rungkad” ia harus berkarakter adaptif, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan politik. Kita meminta setengah maksa agar tersedia mekanisme untuk mengubah Konstitusi atau menyesuaikannya dengan kebutuhan baru. Namun, alih-alih menyesuaikannya malah kita tanpa sadar sekarang sedang bergotong royong “merungkadkannya” melalui perilaku yang oportunis dan gelora “syahwat politik” yang rendah kendali.
Syahwat politik boleh saja kita pelihara, karena ia kondisi alami dalam kehidupan politik, namun jangan sampai liar tak terkendali dan tidak mau beretanggung jawab. Syahwat politik pada dasarnya tidak mau tunduk pada apapun, termasuk pada Konstitusi. Bahkan, syahwat politik yang liar menghendaki agar tidak ada aturan karena akan menghalangi pelampiasan “hasrat kuasanya”. Kalau pun sebuah konstitusi tersedia, syahwat politik yang liar malah akan berusaha mengangkanginya agar bisa merengkuh “cinta kuasa”.
Agar konstitusi tidak rungkad, pemberdayaan Yudikatif merupakan salah satu rukunnya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sistem yudikatif yang kuat dan independen adalah penting untuk menegakkan Konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara. Yudikatif yang kuat akan dapat bertindak sebagai pengawas terhadap pelanggaran Konstitusi. Sebaliknya, Yudikatif yang lemah akan menyuburkan penyimpangan kekuasaan.
Rukun lain bagi kerungkadan Konstitusi adalah tidak terjadi proses keseimbangan kekuasaan, di mana Eksekutif mengangkangi Legislatif dan Yudikatif (atau sebaliknya), baik langsung maupun tidak, termasuk mengangkangi kekuatan civil society, yang berakibat tidak akan ada proses keseimbangan kekuasaan.
Polarisasi Politik
Selanjutnya, yang dapat merungkadkan Konstitusi adalah polarisasi politik yang parah. Saat ini kita menyaksikan dan merasakan polarisasi politik di Masyarakat telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai kelompok semakin jauh terpecah oleh perbedaan pandangan politik. Keparahan ini akan semakin “menggila” apabila nanti terjadi Pemilu yang kontroversial atau hasil pemilu yang dipertanyakan.
Polarisasi politik yang parah menghambat kemampuan lembaga-lembaga pemerintahan untuk bekerja sama, membangun kesepakatan, dan mengancam eksistensi Konstitusi akibat instabilitas politik. Polarisasi politik yang parah dipastikan akan merungkadkan Konstitusi dalam waktu yang sangat cepat. Dampak lanjutannya demokrasi dan stabilitas tatanan bernegara akan terancam, akan sering terjadi gangguan pada keseimbangan kekuasaan, mendegradasi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah, dan tentunya menciptakan konflik sosial berkelanjutan.
Sampai saat ini belum ada solusi yang jitu untuk mengurangi polarisasi politik di dunia, karena dunia hampir secara keseluruhan memang sedang dilanda “wabah ini”. Namun, dengan kombinasi antara proses politik yang jurdil, kebijakan inklusif, dan kepemimpinan yang moderat, dapat berkontribusi pada pengurangan polarisasi politik yang parah tersebut. Oleh sebab itu, perlu membangun konsepsi dan persepsi bersama, terutama di kalangan para aktor politik, untuk menghasilkan kepemimpinan politik yang mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan persatuan di masyarakat.
Ija Suntana, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung