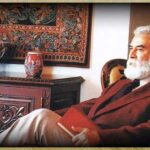(Obituari untuk seorang Guru)
Kabar yang datang adalah kematian. Seorang yang dihormati, guru, senior, teman juga sahabat harus “pulang” duluan. Ia dijemput taqdir yang niscaya. Menemui keabadian. Menjumpai fase “hidup” berikutnya dalam ukuran pengetahuan Tuhan.
Kematian itu batas, begitulah orang semacam Jaspers meyakininya. “Das umgreifende” yang melingkupi, peristiwa pasti yang ditemui. Suka atau tidak, ia bisa tiba pada waktunya. Pada saat gembira. Di kala lengah. Pada waktu tidur. Ketika sakit. Dan ketika manusia jumawa bahkan lupa seolah nyawa tak ada akhirnya.
Kematian itu memudarkan eksistensi sekaligus moment eksistensial. Istri atau suami yang menangis. Anak yang meratap. Kerabat yang tercekat atau kita yang terhenyak mendengar kabar kepergiannya. Istri atau suami yang ditinggalkan pantas meratap. Beberapa waktu lalu mungkin ia masih bersama kita menikmati hidangan di atas meja makan. Merayakan lebaran. Bersantap kupat dan opor ayam.
Istri, anak atau kerabatnya layak tercekat, bukankah sore tadi ia masih siuman? Dan kita memang terhenyak, ada beberapa ingatan bahkan kenangan yang menyapa kita dengan senyuman khas di mulutnya. Dengan guyon juga kelucuan yang menghangatkan suasana. Dengan caranya bicara yang membuat situasi menjadi cair penuh gelak dan tawa.
Lalu tanpa diduga, ia pergi untuk tak kembali. Sebuah sergapan yang menggetkan. Kejadian tragis yang membuat waktu seolah berhenti seketika. Itulah momen eksistensial. Momen yang meneguhkan kesadaran bahwa kematian adalah entitas pasti nan abadi yang dihadapi. Peristiwa “mengerikan” yang melunturkan anggapan manusia sebagai satu-satunya spesies yang paling istimewa.
Kematian. Tak ada ilmu dan kesaktian yang bisa mengalahkan. Tak ada ajian juga mantra yang bisa menunda bahkan menolak kedatangannya. Tak juga ada tempat yang aman buat bersembunyi dan mengindar darinya. Kita hanya sedang menunggu, ditemui mungkin juga diburu olehnya. Seumpama antri di balik pintu siapa giliran berikutnya. Tak bisa menghindar. Mustahil mengelak dari ajakan untuk datang menemuinya. “Fainnal mautalladzi taffiruna minhu fainnahu mulaaqiikum”, begitu penegasan kitab suci.
Kepada senior, guru juga sahabat yang pergi. Kepada siapapun yang menutup mata untuk selamanya. Terlebih buat sahabat juga kerabat yang baru saja “berangkat” menempuh perjalanan ke alam keabadian, Tuhan berkenan menerimanya. Tuhan sumringah menantinya. Seumpama tamu istimewa yang disambut dengan kehangatan dan pelukan. Ditempatkan di kursi kehormatan di samping-Nya.
Mereka yang sudah sempurna menjemput taqdirnya, berharap jiwa damailah yang menyertainya. Kematian bersama damai yang disertakan. Itulah “wurdevoller tod” yang ditegaskan Martin Heidegger. Kematian yang bermartabat. “Wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridla. Masuklah sebagai hamba-hambaku. Masuklah ke dalam syurgaku”.
Selamat jalan pa… ;
Allahu a’lam[]
24 Mei 2020.
Dr. Radea Juli A. Hambali, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung.