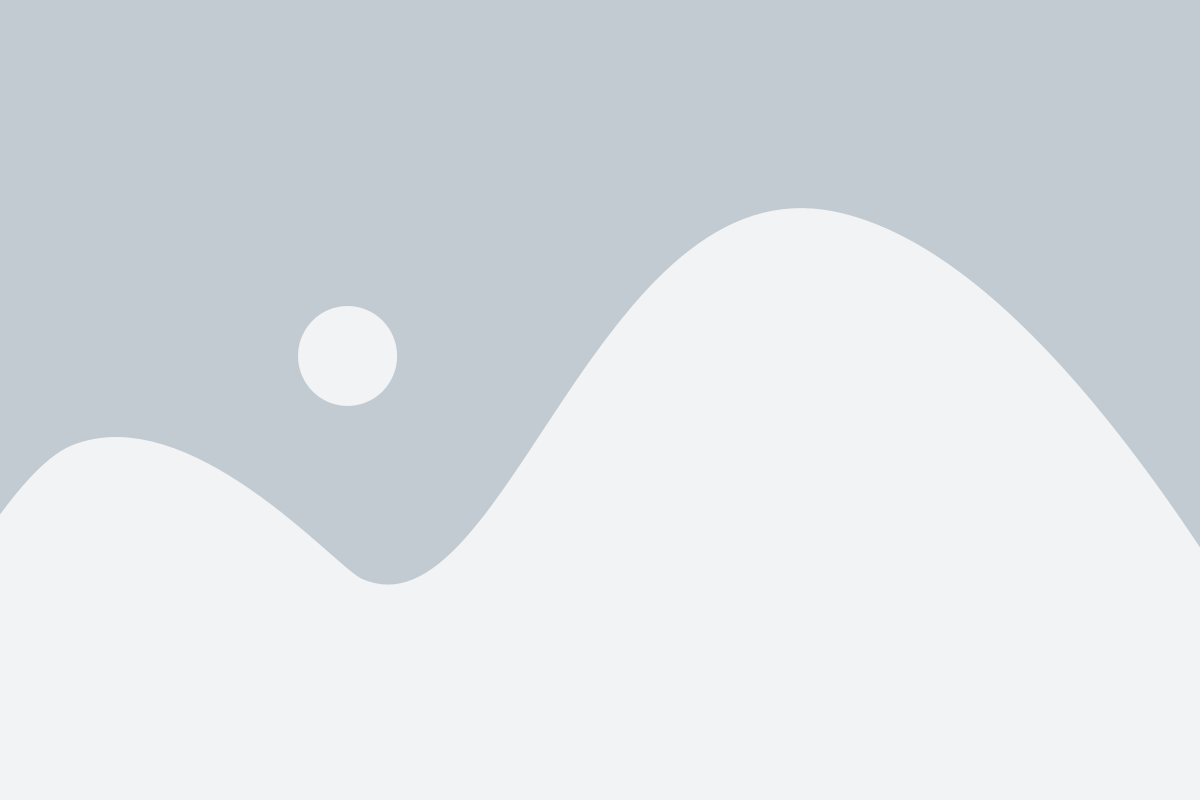Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 8 Januari 2013 adalah kabar gembira bagi sebagian besar masyarakat dan insan pendidikan, karena keberadannya dinilai menutup ruang bagi mereka yang tidak/ kurang mampu.
Dalam amar putusan, majelis hakim menilai keberadaan RSBI/SBI telah menimbulkan perlakuan diskriminatif di dunia pendidikan, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusi. Hanya anak-anak orang kaya yang bisa bersekolah di RSBI karena biaya yang sangat tinggi, jauh berbeda dengan sekolah regular. MK juga menyatakan keberadaan RSBI/SBI berpotensi menjauhkan dunia pendidikan dari jati diri bangsa. Hal ini didasarkan pada fakta “pengagungan” bahasa asing (Inggris).
Keberadaan RSBI/SBI bisa dibilang sebagai sumber kecemburuan sosial di antara anggota masyarakat. Adanya perbedaan pelayanan dan fasilitas yang mencolok antara RSBI/SBI dengan sekolah reguler semakin menajamkan pengastaan pendidikan. Alih-alih ingin membangun sekolah yang bisa bersaing di kancah internasional, yang terjadi justru keterpurukan. Dalam tataran praktis, RSBI/SBI justru jauh dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sebaliknya RSBI/SBI menjelma menjadi suber diskriminasi, kastanisasi, dan eksklusivitas.
Memang benar ada ketentuan 20% kuota bagi kalangan miskin untuk bersekolah di RSBI, namun faktanya mereka tidak mau memasukinya lantaran perbedaan mencolok antara kaya dan miskin menjadi beban psikologis.
Kapitalisasi
Kondisi suatu pendidikan yang telah dipetak-petak oleh faktor sosial dan ekonomi dinamakan kapitalisasi pendidikan. Yaitu suatu kondisi saat pendidikan sudah memasuki ranah komoditas yang menguntungkan secara terbuka dan diperjualbelikan layaknya barang dagangan di pasar. Padahal pendidikan adalah hak tiap warga negara tanpa mengenal kelas, baik kaya maupun miskin, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31, namun rupanya telah tergiring pada praktek jual beli pendidikan.
Dengan memakai logika, “Siapa yang berduit maka mereka akan mengenyam sekolah elit yang berkualitas dan mereka yang miskin akan terpuruk dalam sekolah yang mengenaskan,” pendidikan di Indonesia hanya akan melahirkan jurang pemisah antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin jika masih ada sekolah yang hanya bisa diakses oleh kaum elite.
Jelaslah bahwa akar dari semua ini adalah liberalisasi pendidikan. Ketika pendidikan diliberalkan maka beberapa gejala yang muncul adalah kebijakan dan hak dalam kepengurusan administrasi sekolah diberikan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara sekolah (oto,nom). Bahkan ada sekolah yang sudah dimasuki peran modal asing layaknya sebuah perusahaan seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka. Dalam peraturan itu tertera bahwa pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal dapat dimasuki oleh modal asing dengan batasan kepemilikan modal asing maksimal 49%.
Dengan dalih liberalisasi dan otonomi, pendidikan kian tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Pendidikan yang seharusnya menampilkan wajah “ramah” dan mampu mengayomi seluruh warga, justru berwajah “garang” yang membuat rahayat leutik semakin ketakutan. Takut karena untuk nyuprih elmu ke jenjang yang lebih tinggi dihadang oleh tembok tebal bernama rupiah. Kalu demikian, pendidikan menjadi minus kemanusiaan.
PR Baru
Tamatnya riwayat RSBI/SBI bakal menyisakan pekerjaan rumah (PR) baru bagi pemerintah. Pemerintah harus segera menata kembali kurikulum yang berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia agar berada pada satu sistem pendidikan nasional yang sama dan harus diikuti oleh standar yang sama alias kembali ke dalam kesatuan Sekolah Standar Nasional (SSN) sehingga akselerasi kualitas pendidikan dapat menyentuh seluruh kalangan siswa, dan tidak menciptakan diskriminasi baru.
Selain itu, PR baru bagi sekolah yang telah terlanjur dicap sebagai RSBI/SBI adalah mempertahankan nilaiinilai positif yang telah diterapkan, karena bagaimanapun, banyak hal-hal positif dari sekolah itu. Sebagai sekolah yang telah mengalami treatment, tentu harus menjadikan para siswanya tampil beda dengan menampilkan keunggulan-keunggulan seperti halnya ketika mereka berada dalam naungan RSBI/ SBI, bukan sebaliknya mereka menjadi terpuruk lantaran sistem yang disamakan dengan sekolah-sekolah lain.
Artinya, atmosfer keunggulan sekolah harus tetap tertanam dalam tubuh sekolah, karena untuk menjadi sekolah yang bisa bersaing di dunia internasional tentu tidak harus secara atributif formal dilabeli RSBI/SBI. Di zaman super modern seperti sekarang, peluang untuk go international sangat terbuka. Teknologi modern tentu bisa membantu sekolah-sekolah untuk berselancar di dunia internasional. Melalui surat elektrinik, facebook, twitter, teleconference, dan sebagainya sekolah dan para siswa dapat melibatkan diri dalam dunia internasional tanpa harus bersusah payah.
Untuk itu, tentu pemerintah, masyarakat, dan orang tua harus bertanggung jawab menjaga mutu, bukan menjaga kastanisasi, dan membuat para siswa yang berada di tingkat akhir RSBI/SBI tidak terpuruk karena hilangnya label “internasional” dari sekolah mereka.
Keputusan MK itu tepat, karena telah mengembalikan hakikat pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan nasional Indonesia. Tujuan itu mencita-citakan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin secara merata. Fenomena pendidikan yang menunjukkan aksi diskriminasi, kastanisasi, dan eksklusivitas adalah fenomena paradoks dengan hakikat pendidikan. Ini berarti hilangnya nilai kemanusiaan.
Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan STAI Alazhary Cianjur
Sumber, Galamedia 17 Januari 2013