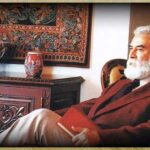UINSGD.AC.ID (Humas) — Rasa-rasanya, 20 atau 30 tahun terakhir Ramadhan, ruang publik Indonesia berubah wajah secara total. Spanduk ucapan selamat menjalankan shaum membentang di jalan-jalan dan di mal-mal. Televisi menayangkan ceramah dengan latar musik lembut, walaupun juga dipenuhi acara entertainment yang penuh gelak tawa. Dunia digital pun dipenuhi algoritma serupa.
Pada sisi lain, pasar-pasar sore mendadak penuh untuk para pemburu takzil, yang tidak hanya berasal dari mereka yang puasa. Fenomena ngabuburit seakan menjadi identitas sosio-religius semua kalangan. Sehingga, kondisi lapar pun seakan menjadi pengalaman kolosal “massal”. Orang-orang kaya merasa sudah menghayati keserakekuarangan sesaat, namun terkadang mereka yang berada kondisi “lapar” sesungguhnya sering tidak tersentuh “efek ibadah” kaum aghniya.
Namun sejarah tidak otomatis berubah hanya karena sebuah bangsa banyak yang melakukan puasa bersama-sama. Karena, rasanya, ada sesuatu yang paradoksal di sini: Indonesia adalah salah satu negeri Muslim terbesar di dunia. Ramadan dirayakan dengan gegap gempita. Tetapi dalam waktu yang sama, kita menyaksikan kriminalitas yang tak kunjung reda, polarisasi politik yang masih terasa keras di dunia digital, ujaran kebencian yang banal, dan religiusitas yang sering lebih simbolik daripada substantif. Kemiskinan dan kepapaan masih ditemukan di sana-sini, padahal gerakan zakat konsumtif dan produktif terus digemborkan dan digempitakan lewat media.
Di titik inilah puasa perlu dibaca bukan sekadar sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai persoalan sosio-historis. Nampaknya, ibadah ritual kita belum banyak berefek pada transformasi sosial.
—
Peta Batin yang Ditawarkan al-Ghazali
Dalam “Kitāb Asrār al-Ṣawm” dari Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Abu Hamid al-Ghazali menyusun tipologi yang tampak sederhana dan familiar, namun solid.
اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص.
Imam al-Ghazali mencoba memetakan tiga kualitas (derajat) puasa.
Tingkat pertama:
فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة.
Puasa orang umum, yakni puasanya orang menahan perut dan syahwat. Keshalehan yang dibangunnya adalah keshalehan normatif. Puasanya memenuhi syarat dan rukun secara “fiqhiyyah”. Tentu saja, ini adalah fondasi. Imam Murtadha al-Zabidin (salah satu pensyarah “Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn) dalam “Sirr al-Shaum” berpandangan bahwa puasa jenis ini baru memosisikan ritual keagamaan sebagai aturan, belum masuk pada aksis kesadaran, belum menjadi perilaku keagamaan yang historis
Tingkat kedua:
وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام.
Puasa orang khusus: menahan seluruh anggota tubuh dari dosa. Tingkatan pemaknaan puasa kedua ini adalah disiplin etis atau kesalehan sosial. Ia mewujud menjadi pengendalian diri kolektif, serta membentuk kultur publik yang lebih santun, lebih adik, dan lebih peduli (simpatik atau empatik).
Tingkat ketiga:
> وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية.
Puasa orang paling khusus: puasa hati dari ambisi rendah dan orientasi duniawi.
—-
Al-Ghazali tidak sekadar mengklasifikasikan ibadah. Ia sedang menyusun antropologi spiritual atau acuan normatif tentang manusia yang berpuasa, yakni a) manusia biologis, b) manusia etis, dan c) manusia transenden.
Kini, masalahnya bukan pada teks dan standardisasi itu. Masalahnya pada sejarah aktualitas kita—di tingkat mana posisi puasa kita berlabuh?
—
Ritualisme dan Budaya Simbolik
Jika memakai kerangka Fazlur Rahman, agama memiliki inti moral yang harus dibaca secara dinamis dalam konteks sejarah. Tetapi dalam banyak masyarakat Muslim modern, termasuk Indonesia, agama sering membeku menjadi ritualisme formal. Puasa dijalankan dengan disiplin waktu yang ketat, tetapi tidak selalu diikuti disiplin moral yang setara. Ada pemisahan antara kesalehan privat dan perilaku publik.
Di layar kaca atau layar digital lainnya, kita menyaksikan mereka yang taat berpuasa, tetapi terseret berbagai kasus negatif. Kita melihat tokoh yang rajin ceramah Ramadan, tetapi mudah memproduksi ujaran yang memecah belah, hate speech, bulliying, atau Fenomena ini bukan semata-mata skizoprenia individual. Ia adalah gejala budaya simbolik: agama dijalankan sebagai identitas kolektif, bukan sebagai etika transformasi.
Di sini puasa berhenti pada tingkat pertama—bahkan kadang hanya pada tampilan luarnya.
—
Puasa dan Krisis Etika Publik
Tingkat kedua dalam peta al-Ghazali—menahan lisan, mata, tangan—sesungguhnya sangat relevan bagi ruang publik Indonesia hari ini.
Bayangkan jika puasa benar-benar dipraktikkan sebagai disiplin lisan: tidak menyebarkan kabar bohong, tidak menghasut, tidak memperuncing perbedaan. Bayangkan jika puasa menjadi latihan menahan tangan dari transaksi gelap, menahan mata dari ketamakan proyek.
Dalam bahasa Mohammed Arkoun, agama seharusnya dibebaskan dari reduksi simbolik dan dikembalikan pada daya kritisnya terhadap struktur sosial. Puasa, jika dipahami pada tingkat kedua, bisa menjadi mekanisme pembentukan etika publik.
Tetapi etika publik tidak lahir dari seremoni. Ia lahir dari disiplin batin yang konsisten. Ramadhan memberi peluang itu. Persoalannya: apakah peluang itu diinstitusikan menjadi budaya?
—
Puasa Hati dan Pembongkaran Ego Kekuasaan
Tingkat ketiga adalah yang paling jarang dibicarakan dalam wacana publik: Puasa hati dari ambisi rendah dan pikiran duniawi yang berlebihan (tabdzîr). Di sinilah puasa bertemu politik dalam arti paling dalam: politik sebagai orientasi kekuasaan sosial, kultural, maupun struktuta. Ambisi melahirkan budaya, struktur, dan sistem yang berujung pada hegemoni dan kerakusan.
Misal, ambisi rendah—keinginan mempertahankan jabatan, hasrat dipuji, ketakutan kehilangan pengaruh—adalah motor banyak krisis sosial. Jika ambisi ini tidak dikendalikan, ia menjelma menjadi sistem: oligarki, kekuasaan koruptif, atau memodifikasi jargon-jargon agama untuk kepentingan politik pragmatis.
Ali Shariati pernah menegaskan bahwa tauhid bukan sekadar doktrin teologis, melainkan pembebasan manusia dari segala bentuk berhala—termasuk berhala diri. Dalam konteks ini, puasa hati adalah latihan menghancurkan berhala ego.
Tanpa pembongkaran ego, kesalehan mudah berubah menjadi legitimasi “kekuasaan.”
Indonesia tidak kekurangan simbol agama. Yang kita kekurangan adalah keberanian membiarkan agama mengoreksi diri kita sendiri dan menjadi enigma perubahan.
—
Puasa sebagai Praksis Profetik
Di sinilah kita bisa menyebut puasa sebagai praksis profetik. Puasa dalam dimensi profetik bukan sekadar spiritual; ia historis; ia etis; ia transformatif. Puasa membentuk manusia yang:
a) Mampu mengendalikan tubuhnya; b) Mampu mengendalikan tindakannya dalam ruang sosial; c) Mampu mengendalikan orientasi batinnya ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan.
Jika tiga lapis ini berjalan, puasa tidak berhenti di masjid atau meja makan. Ia masuk ke ruang kebijakan, ruang bisnis, ruang pendidikan, ruang politik.
Sejarah tidak berubah oleh simbol dan ritual yang artificial. Ia berubah oleh manusia yang pusat batinnya telah digeser.
—
Sejarah yang Tertahan
Mungkin problem kita bukan kekurangan ritual, tetapi kekurangan internalisasi. Ramadan datang setiap tahun. Tetapi transformasi sosial terasa seperti “janji yang tertunda.” Seolah-olah ada jarak antara ibadah dan sejarah—jarak yang tidak pernah kita upayakan untuk didekatkan. Al-Ghazali sudah memberi peta. Para pemikir modern telah mengingatkan dimensi moral dan historis agama. Yang tersisa adalah keberanian untuk menaikkan status puasa kita, satu tingkat.
Jika puasa kita berhenti pada tubuh, maka ia hanya mengubah ritme biologis;
Jika puasa kita berhenti pada perilaku, maka ia hanya membentuk kesantunan;
Namun, jika puasa kita menyentuh hati, ia berpotensi membentuk orientasi sejarah.
Saya sendiri sering merasa bahwa puasa saya berhenti di tingkat pertama. Kadang naik sedikit ke tingkat kedua. Tetapi tingkat ketiga—membiarkan ego benar-benar lapar—itu medan yang sunyi dan sulit.
Mungkin memang perubahan sejarah tidak dimulai dari kebijakan besar, tetapi dari keberanian kecil: menggeser pusat diri dan visi moral-spiritual yang terejawantahkan. Jika puasa hanya mengubah jam makan, ia akan tetap menjadi peristiwa musiman. Tetapi jika ia mengubah orientasi batin, ia bisa menjadi “energi sejarah”.
Dan di sanalah, mungkin, sejarah yang selama ini tertunda itu menemukan momentumnya. Mungkin, Ramadhan akan terus datang dan pergi; ia ramai di kalender dan dunia digital; namun sunyu dalam perubahan.
Dadan Rusmana, Wakil Rektor I UIN Sunan Gunung Djati Bandung.