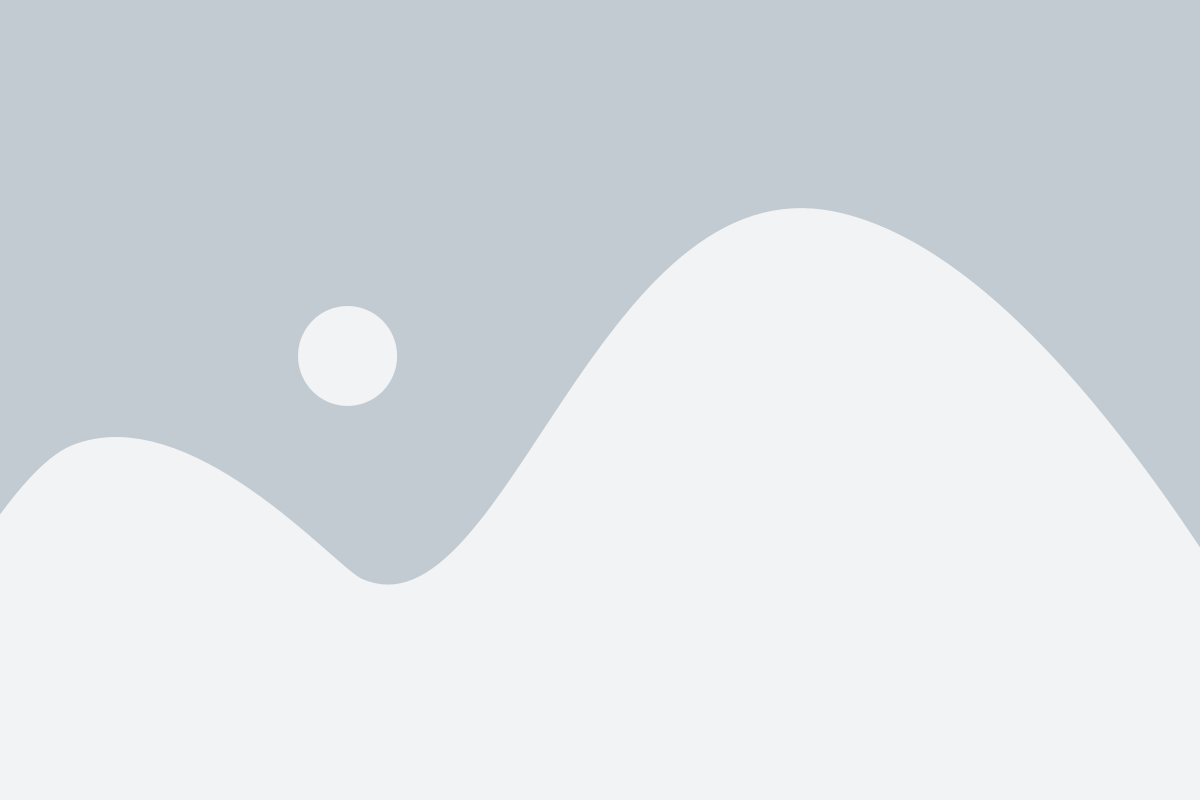A. Berawal dari Kegalauan Machicha
Selama ini tradisi fiqh Islam masih tetap menjadi doktrin dan acuan yang kuat bagi umat Islam. Hal itu didasarkan atas pemahaman dan keyakinan bahwa fiqh merupakan produk dan kesepakatan para faqih. Karena itulah, maka fiqh dijaga dan dipelihara. Dalam salah satu kaidah fiqh berbunyi: al-Muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhd bi al jadid al-ashlah—melestarikan tradisi lama yang baik dan mengembangkan inovasi yang lebih baik. Selain itu, pendapat para kiai, para ulama tetap menjadi rujukan di kalangan sebagian masyarakat Islam, sehingga kata-kata kiai sering mengalahkan tatanan sosial, bahkan regulasi. Sayangnya, tatanan yang sudah dibangun selama ini tidak serta merta diikuti dengan etika dan kesantunan. Acap kali perilaku sebagian orang dapat merusak tatanan dan tradisi fiqh yang semestinya dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih jika hal itu sudah merambah pada persoalan yang sakral seperti pernikahan.
Asumsi itu bukan tanpa alasan, mengingat dalam kehidupan kekeluargaan kita dewasa ini kecenderungan desakralisasi pernikahan itu sudah menjadi fenomena menarik. Desakralisasi pernikahan terjadi dengan memanfaatkan permissive-nya nikah siri– nikah secara diam-diam. Nikah siri pun akhirnya seringkali dilakukan dalam pernikahan poligini yang dilakukan kalangan tertentu, bahkan itu kemudian menjadi model yang dilakukan para pejabat untuk berpoligini secara diam-diam tanpa diketahui istri, keluarga, dan masyarakat. Dengan nikah siri itu seakan-akan tidak ada beban yang melekat, sehingga segalanya serba simplisit, termasuk mudah menceraikan, kapan saja, dimana saja, dan dengan cara apa saja, termasuk dengan pesan singkat (sms).
Padahal, sejatinya ada etika yang harus diperhatikan. Meskipun urusan nikah adalah domain privasi, tetapi jika itu terjadi kepada publik figur, apalagi jika ranah fiqh itu sudah menjadi tatanan kemasyarakatan dan kebangsaan, maka boleh jadi persoalannya menjadi lain. Hal itu bisa menjadi persoalan etika sosial dan norma hukum, bukan lagi etika pribadi. Sebab jika seseorang sudah menjadi publik figur maka harus siap menanggalkan egoisme privasinya masing-masing, sehingga jika hal itu dilanggar, maka hukumannya adalah hukum moral dan hukum sosial.
Lebih-lebih bagi kalangan pejabat yang sudah terikat dengan sumpah jabatan untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ironisnya, para wanita pun mau saja dinikahi secara diam-diam. Mereka terkadang terjebak oleh iming-iming, dan janji-janji gombal. Keluguan dan keawamannya dimanfa’atkan, akibatnya seringkali mereka harus menanggung risiko yang sangat berat. Untuk menyebut sebuah contoh, sebut saja kasus Bupati Cirebon (Dedi S), Bupati Garut (Aceng M. Fikri), dan kasus yang dialami panyanyi dangdut Aisyah alias Machica Mochtar (dinikahi secara siri oleh Drs. Moerdiono), yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, yang sarat dengan kontroversial dan menarik perhatian dari pelbagai kalangan dan berbagai level masyarakat.
Diskursus lahirnya Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 itu sendiri, berkenaan dengan permohonan penyanyi dangdut Aisyah (Machica) Mochtar dan anaknya M. Iqbal Ramadhan dalam uji materiil (judicial review) atas pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan dan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, telah mengundang komentar dan diskusi publik. Meskipun MK menolak uji materi atas Pasal 2 ayat (2), tetapi mengabulkan uji materi atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dipandangnya bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK itu telah mengubah jangkauan hubungan keperdataan anak. Anak yang lahir melalui perkawinan yang sah menurut agama dan negara dipersamakan dengan anak yang lahir tanpa melalui perkawinan yang sah menurut agama dan negara, bahkan yang melanggar nilai-nilai agama, norma-norma hukum dan tatanan sosial.
Hasil uji materi atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 itu secara lengkap berbunyi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Dengan lahirnya putusan itu, bukan saja Aisyah (Machica) Mochtar yang diuntungkan, karena anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang semula tidak diakui oleh keluarga besar Moerdiono, dari segi keperdataan mendapat kepastian hukum sebagai anak biologis dari Moerdiono. Tetapi dengan perluasan kandungan makna perlindungan anak itu, banyak pihak yang bisa memetik keuntungan. Meskipun dari segi maqasid, para hakim MK yang mengadili uji materi ini berdalih tidak bermaksud untuk melegalisasi perzinaan, tetapi disadari atau tidak, lambat laun, implikasinya bisa berdampak cukup luas.
Bagi kita, kalangan intelektual, tentunya perlu kearifan dalam mengapresiasi dan menakar putusan MK itu. Karena bagaimanapun MK adalah lembaga tinggi Negara, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pasca amandemen UUD 1945. Namun di sisi lain, janganlah karena putusan MK itu, kemudian memunculkan persoalan baru yang dapat mengusik ketertiban lahiriyah dan ketentraman batiniah umat Islam.
B. Putusan MK Pro Perlindungan Anak
Jika kita mengamati secara kronologis, uji materiil itu sesungguhnya berawal dari kegalauan Aisyah (Machica) Mochtar yang memperjuangkan nasib anaknya hasil “pernikahan siri” dengan Moerdiono, yang tidak kunjung mendapat pengakuan dari Moerdiono dan keluarga besarnya, karena tersandung oleh status pernikahannya yang tidak tercatat. Ini merupakan konsekuensi hukum dari bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”[1]
Dalam klausul permohonan uji materi, Aisyah (Machica) Mochtar menjelaskan, bahwa secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan pernikahan sepanjang hal itu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam kaitan itu, pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan norma agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini Pemohon berpandangan bahwa keabsahan pernikahannya tidak mungkin dapat diredusir oleh norma hukum buatan manusia, sehingga pernikahan yang sah menjadi tidak sah. Akibat hukumnya menjadi sangat luas. Bukan saja status pernikahanya tidak jelas, tetapi juga merembet pada status anak yang dilahirkannya menjadi tidak pasti.
Sementara keberadaan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbuyi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sejatinya merupakan ketentuan yang melekat—pasal ikutan terhadap pasal sebelumnya, yaitu Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur keharusan peristiwa pernikahan itu dicatat oleh pejabat yang berwenang, PPN dari Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian, maka anak yang lahir melalui “pernikahan siri-nikah agama-nikah dibawah tangan”, meskipun pernikahan itu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan drigama, yaitu telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) perihal keabsahan pernikahan, diperlakukan sama (bukan disamakan) dengan anak zina, yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dalam hal ini secara yuridis formal hak keperdataannya hanya dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya, sementara hak keperdataan yang berkaitan dengan ayah biologisnya, baik tentang nasab, wali nikah maupun tentang kewarisan tidak diakui.
Permohonan uji materi yang disampaikan Aisyah (Machica) Mochtar itu adalah dalam konteks mendapatkan keadilan pengakuan “nikah siri”, bukan dalam konteks hubungan di luar pernikahan. Pernikahan nikah siri yang dilakukannya itu telah mendapat penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 2008. Dalam konsiderannya dikatakan: … Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama KH. M. Yusuf Usman dan Risman. Mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.
Dengan memperhatikan pokok persoalan dan isi tuntutan yang disampaikan oleh pihak pemohon, serta mendengarkan kesaksian dari saksi ahli, maka pada tanggal 13 Pebruari 2012 Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan, dan pada 17 Pebruari 2012 Majelis Hakim membacakan amar putusan sebagai berikut:
Menolak permohonan uji materi pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, dengan pertimbangan hokum, bahwa pencatatan pernikahan penting untuk ketertiban. Pencatatan secara administrative yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hokum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.[2]
Menerima uji materi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan menyatakan: …….. “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hokum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: ““anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Pada prinsipnya, argumentasi yang dijadikan dasar diterimanya permohonan uji materi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah untuk melakukan pembelaan terhadap anak dan memberikan panisment kepada ayah biologisnya. Hal ini didasarkan kepada:
Anak yang lahir pada dasarnya suci. Karena itu eksistensi dan keberlangsungan anak harus dilindungi, jangan sampai terdiskriminasi oleh perbuatan a moral orang tuanya. Tidak adil jika sampai menerima stigma-label sebagai “anak jadah”—“anak haram”.
Dari segi sunatullah, setiap anak yang lahir dari rahim sang ibu, secara biologis tidak bisa terlepas dari peran pasangannya, yaitu seorang laki-laki. Karena itu hubungan keperdataannya tidak boleh terputus.
c. Pihak laki-laki, selaku ayah biologisnya harus mendapat panismen (wa’id—ancaman), sehingga tidak cuci tangan, lari dari tanggungjawab. Karena itu ia harus diikat (dihukum) dengan hubungan keperdataan.
C. Implikasi Putusan MK Bisa Melebar
Putusan MK itu tentunya memiliki konsekuensi yang sangat luas. Bukan saja berhasil menyelesaikan persoalan, yaitu dengan melindungi nasib anak yang status keperdataannya teraniaya, tetapi juga bisa mengundang persoalan baru. Tarik menarik penafsiran yang luas dan bisa menjangkau implikasi hukum di antara keberadaan lembaga pernikahan legal yang melahirkan anak spiritual dengan pergaulan tidak legal yang melahirkan anak biologis seba-gaimana terdapat pada pasal 43 ayat (1) hasil uji materi perlu dipagari agar tidak merambah dan melebar kemana-mana.
Persoalannya, janganlah dengan alasan untuk melindungi dan mengakui anak suci yang lahir justru dibuka “pintu” kebebasan yang tanpa batas, termasuk perbuatan bejad orang tuanya. Alih-alih kemudian memunculkan persoalan baru. Seakan-akan lepas dari “sarang macan” kemudian masuk ke “sarang buaya”. Dengan “diubahnya” pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 itu, maka semangat keagamaan yang melekat pada pasal 2 ayat (1) dan disebut-sebut sebagai pasal yang Islami, seakan-akan “dinafikan”. Padahal keberadaan pasal itu sebenarnya melekat dan merupakan “ikutan” atas pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Selama ini pasal tersebut sudah dipandang tepat dengan kultur bangsa yang agamis, yang menempatkan pernikahan sebagai pintu untuk menisbatkan anak yang ideal kepada ibu-bapaknya, sehingga posisi dan pengakuan anak bukan hanya “anak biologis, tetapi juga anak spiritual”. Anak biologis yang sehat dan anak spiritual yang shaleh yang lahir melalui gerbang pernikahan resmi sesuai dengan agama inilah kelak menjadi pintu masuk membangun keluarga sakinah.
Jika dengan alasan untuk melindungi anak itu sampai harus “bongkar pasang” pasal sensitif, yaitu pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, tampaknya terlalu mahal. Karena pasal ini sesungguhnya merupakan pasal penguat atas pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang secara materiil memberikan forsi kemajemukan, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam pernikahannya harus disesuaikan dengan norma agama sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab fiqh. Begitu pula bagi warga Negara non Muslim harus disesuaikan dengan norma agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, rumusan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak lagi memiliki benang merah dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Padahal substansi dan nilai-nilai yang terdapat pada pasal-pasal itu semestinya sinergi, saling mengisi dan menguatkan.
Seandainya alasan dan pertimbangan utama lahirnya putusan MK itu demi melindungi anak (hifdz al-Nafs) supaya mendapatkan kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan, bagi pelaku yang terlanjur kebablasan, dan menghasilkan anak dalam kandungan, yang merupakan argumentasi andalan hakim MK, yaitu dalam rangka melindungi anak, sebenarnya bisa terbantahkan, karena bagi pelaku hubungan di luar perkawinan seperti perzinaan, perselingkuhan, samen leven (kumpul kebo) yang bertanggungjawab dan berniat baik, ada ruang untuk memberi perlindungan bagi anak yang dikandung ibunya, yaitu: melalui pasal 53 ayat (1) KHI, yang membolehkan kawin hamil: “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.
Meskipun dari segi maqashid tidak dimaksudkan untuk melegitimasi hubungan perkawinan yang tidak sah, tetapi dengan mengakui hubungan biologis ayahnya, sekalipun secara “malu-malu”, maka mafhum mukhalafahnya bisa dipahami ada celah untuk mengakui hubungan di luar perkawinan yang sah. Dampaknya, akan memunculkan pula berbagai persoalan baru:
Perluasan penafsiran itu mengandung arti memberi kelonggaran, sekaligus membuka pintu untuk melakukan pelanggaran dan perbuatan dosa. Padahal sekecil apapun, jalan kemaksiatan dan perbuatan dosa itu harus ditutup (syadz al-dzari’ah). Apapun alasannya, termasuk dengan dalih untuk melindungi anak, tidak mesti memunculkan persoalan baru, yakni membuka jalan (fath al-dzri’ah) untuk melanggar norma agama, nilai-nilai hukum dan tatanan sosial.
Anak yang dimaksud dengan hubungan di luar perkawinan itu tafsirannya bisa diperluas: Pertama, bisa anak yang lahir melalui nikah siri (karena hanya memenuhi tuntutan pasal 2 ayat (1) dan tidak memenuhi tuntutan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, bisa dimaknai dengan anak hasil nikah siri dan anak yang lahir dari hasil kumpul kebo dan perzinaan (tidak memenuhi tuntutan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974). Dari sudut pandang maqashid al-syari’ah hal itu berbenturan dengan semangat hifdz al-Nafs, hifdz al-Nasl dan hifdz al-Din. Karena menjaga dan melindungi jiwa dan keturunan itu harus juga memperhatikan agama.
Bisa jadi, jika suatu saat “alumni Saritem” (kini Darul Taubah), mantan Pekerja Seks Komersial (PSK), atau mantan pasangan kumpul kebo yang melahirkan anak berbondong-bondong mencari bapak biologisnya.
Orang-orang yang tidak mau terikat oleh hukum itu semakin merasa terlindungi untuk melakukan praktik pergaulan dan seks bebas. Memang semua itu kembali kepada moral dan kesadaran hukum serta tanggungjawab masing-masing. Tetapi alangkah baiknya jika setiap saluran, setiap ventilasi, bahkan setiap ruang dan kesempatan itu secara sinergi bersama-sama menutupnya, tanpa sedikit-pun memberikan celah dan peluang.
Jika secara terminology anak di luar perkawinan yang lahir itu termasuk anak hasil perkosaan, maka penisbatan dengan ayah biologisnya itu justru akan menjadi beban berat bagi anak dan ibunya. Karena ayah biologisnya “unwanted”. Di sini alasan perlindungan terhadap anak menjadi abu-abu. Relasi keperdataan dengan ayah biologisnya pun menjadi parsial, sehingga akan mendatangkan persoalan baru dalam internal rumah tangga.
D. Umat Islam Menunggu Kearifan
Awal munculnya permohonan uji materi itu adalah dalam konteks perlunya pengakuan yuridis pernikahan siri yang dilakukan Aisyah (Machica) Mochtar dengan Drs. Moerdiono, dan bukan dalam konteks hubungan di luar perkawinan. Karena itu, semestinya perubahan ayat itu hanya ditujukan bagi anak yang lahir melalui pernikahan sah yang tidak dicatat sebagaimana dialami pemohon, Aisyah (Machica) Mochtar dengan Moerdiono, sehingga bunyi pasal itu tetap sebagai pasal empati, pasal yang mendukung kemuliaan dan keabsahan pernikahan legal sesuai dengan norma agama dan segala konsekuensi keperdataannya yang melekat. Sebab, jika hasil uji materiil itu sampai merubah bunyi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menempatkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi mempunyai hubungan darah dan perdata dengan laki-laki biologis sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya, maka posisi pasal itu menjadi pasal yang kontroversial, yang bertentangan dengan semangat ajaran agama yang menempatkan anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab, hubungan darah, dan hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya.
Suka atau tidak suka, secara konstitusional putusan MK yang dinilai banyak pihak sebagai putusan yang teramat berani itu telah keluar. Lembaga tinggi yang paling kompeten dalam menguji peraturan perundang-undangan itu sudah mengetuk palu, mengeluarkan putusan yang menguntungkan pihak pemohon, meskipun sangat menghenyakan dan menyesakan perasaan hukum umat Islam. Sebagai warga negara yang baik, tentunya dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, seberat dan sepahit apapun harus tetap elegan, menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai putusan hakim.
Namun demikian, dalam meredam problematika hukum yang kemungkinan muncul sebagai implikasi dari putusan MK itu perlu adanya kekuatan ekstra cerdas yang lebih arif, agar penafsiran dan dampak putusannya tidak melebar ke mana-mana. Dengan begitu, putusan itu bisa aman, dihargai dan dihormati, tetapi dalam hal yang sama lembaga pernikahan yang sakral tidak terasa dilecehkan dan umat Islam tidak merasa dicederai.
Karena itu diperlukan langkah-langkah hukum yang lebih bijak. Semua kekuatan umat Islam, baik melalui MUI maupun ormas-ormas Islam sebagai garda umat perlu mengambil inisiatif untuk memberikan dorongan kepada pihak yang berwenang guna merespon dan mencegah kemungkinan terjadinya penafsiran yang lebih luas yang dapat membingungkan umat. Misalnya dengan membuat rekomendasi melalui pendekatan politik hukum untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang merevisi Peraturan Pemerintah sebelumnya guna memberikan penjelasan berkaitan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu. Dalam konteks ini pula diperlukan pemikiran progresif guna mengawal dan mengamankan putusan lembaga tinggi Negara di satu sisi, dan memagari dampak lain yang lebih luas:
Sejatinya putusan itu dipahami bersifat lex generalis, sehingga diperlukan adanya ketentuan yang bersifat lex spesialis, semisal peraturan pemerintah yang memperjelas Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksud di situ hanya menjustifikasi pernikahan yang tidak dicatat, tetapi secara hukum, dari sudut pandang fiqh sah, karena memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana awal munculnya putusan MK ini, yaitu mencari pengakuan atas “nikah siri”.
Jika status anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya dipersamakan, maka hak-hak keperdataannya tidak mesti sama dengan hak keperdataan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah. Dengan kata lain, hubungan keperdataan dalam perubahan ayat itu semestinya tidak mencakup hubungan keperdataan dalam hal nasab, wali nikah dan waris.
Diperlukan tafsir hukum progresif para praktisi hukum, termasuk para hakim dalam mengapresiasi dan menafsirkan terminology “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, yaitu dengan melakukan takhsis bagi “nikah siri”, yang memenuhi Pasal 2 ayat (1), tetapi tidak memenuhi tuntutan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, penafsiran yang melebar yang mengakui anak hubungan di luar perkawinan bisa dihindarkan.
Perlu adanya regulasi untuk melakukan upaya preventif yang ketat—pencegahan, agar hubungan di luar perkawinan yang sah itu bisa dicegah, paling tidak dapat diminimalisir, sehingga tidak berakibat lahirnya anak di luar perkawinan yang sah. Di samping itu, diperlukan pula panisment, sanksi hukum yang berat bagi pelaku perzinaan, pelacuran, dan hubugan seksual di luar perkawinan.
E. Penutup
Mengakhiri tulisan ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:
Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 itu dipandang terlalu berani dan bisa menyesatkan. Karena telah mengesampingkan nilai-nilai agama yang semestinya dijunjung tinggi, dan telah memberi ruang untuk menyamaratakan antara perilaku orang yang memiliki komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sunnah Rasul (pernikahan) dengan perilaku orang bebas yang tidak menginginkan terikat dengan nilai-nilai agama yang sakral.
Pengakuan keperdataan atas posisi anak, dengan dalih “anak biologis”, jangkauannya bisa melebar, bisa mencakup nikah siri, perzinaan, perselingkuhan, samen leven (kumpul kebo) memiliki hubungan keperdataan bukan saja dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah biologis dan keluarganya.
Secara konstitusional, putusan MK yang dinilai banyak pihak sebagai putusan yang teramat berani itu telah keluar. Lembaga tinggi yang berkompeten dalam menguji peraturan perundang-undangan itu sudah mengeluarkan putusan yang menguntungkan pihak pemohon, meskipun sangat menghenyakan dan menyesakan perasaan hukum umat Islam. Sebagai warga negara yang baik, tentunya dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, harus tetap elegan, menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai putusan hakim.
Perlu adanya peraturan pemerintah yang memperjelas bahwa putusan MK itu bersifat lex generalis, sehingga memerlukan ketentuan yang bersifat lex spesialis, yang hanya menjustifikasi perkawinan tidak dicatat. Karena sesuai konteksnya, permohonan uji materi itu adalah dalam rangka mencari keadilan, yaitu mencari pengakuan atas “nikah siri”.
Para intelektual, para pakar dan praktisi hukum, termasuk para hakim dalam mengapresiasi dan menafsirkan terminology “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, ditantang untuk melakukan takhsis, bahwa yang dimaksud dengan klausul “di luar perkawinan” itu sesuai dengan konteksnya, yaitu “nikah siri”, yaitu perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.
Secara implisit MK mengakui fenomena perilaku menyimpang yang dilakukan segelintir masyarakat. Karena itu, pemerintah harus lebih kuat dalam melakukan kontrol, sehingga bisa mencegah perbuatan yang dapat melanggar hukum dan norma kesusilaan. Setidaknya dapat meminimalisir perbuatan-perbuatan menyimpang itu.
Wallahu’alam.
Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si., Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung
[1] Lihat pula Pasal 5 ayat (1) Buku I tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. ……………………..
[2] Asrorun Ni’am Sholeh, “Memperjelas kedudukan Anak di Luar Perkawinan” dalam Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan (Jakarta: MUI, 2012) hlm. 251.