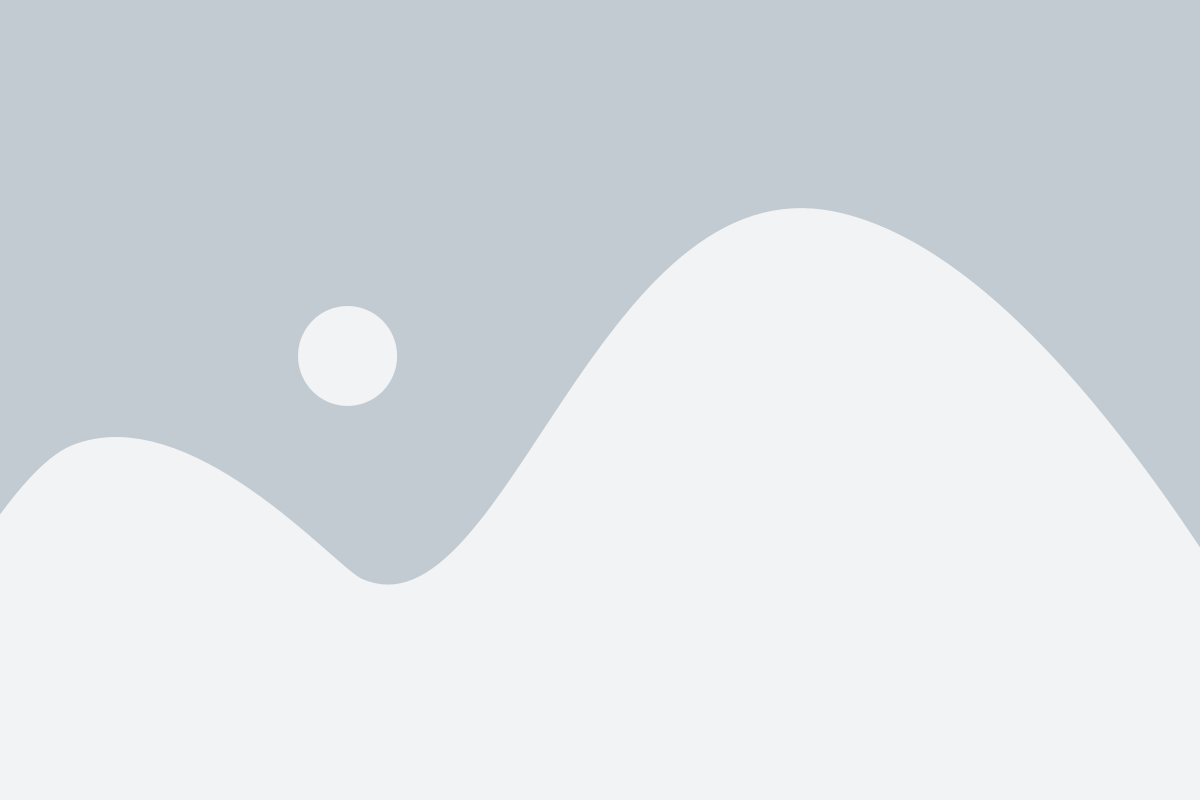Dalam sebuah dialog, Ernest Renan, seorang filosof Perancis abad ke-19, terdesak oleh Muhammad Abduh mengenai keunggulan ajaran Islam dibanding ajaran Kristen. Akan tetapi, ketika Renan beralih ke masalah umat dengan mengatakan, “Mana di antara umat Islam itu yang merupakan gambaran dari Islam yang hebat tadi,” maka Muhammad Abduh tunduk dengan sedih, tanpa dapat menyangkal kenyataan bahwa kaum Muslim memang masih terbelakang.
Dialog tersebut terjadi pada akhir abad ke- 19M. Saat itu Dunia Islam berada dalam kondisi sangat terbelakang dibandingkan kondisi Barat secara keseluruhan, bahkan hampir seluruh negeri Muslim merupakan negeri jajahan Barat. Padahal, dalam babakan sejarah Islam masa awal hingga abad ke-13 M, Dunia Islam justru berada dalam puncak kejayaan.
Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada umat manusia, melalui Muhammad, Rasulullah Saw. Sebagai agama yang datang dari Zat Yang Mahabenar, Islam memiliki ajaran-ajaran yang luhur dan mulia. Ajaran-ajaran tersebut termuat di dalam Al-Quran al-Karim yang menjadi pedoman hidup kaum Muslim sejak saat diturunkan hingga Hari Kiamat.
Sebagai Kitab Suci, Al-Quran al-Karim mengajarkan nilai-nilai ideal yang harus diamalkan oleh kaum Muslim. Murtadha Muthahhari menyebut ajaran “Islam ideal” yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut sebagai “Islam Cita”, sedangkan Nurcholish Madjid menyebutnya “Islam Doktrin”. Sementara itu, Islam seperti yang diamalkan oleh kaum Muslim disebut Muthahhari sebagai “Islam Fakta”, dan disebut Nurcholish Madjid dengan “Islam Peradaban”.
Sebagai himpunan ajaran, Islam memiliki nilai yang sangat baik, unggul, dan mulia: mendorong manusia untuk berakhlak mulia, bekerja keras, jujur, adil, amanah, mencintai ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kemanusiaan, memuliakan kaum perempuan, serta menentang kemunkaran, kezaliman, tiran, kemaksiatan, dan segenap bentuk kejahatan lainnya.
Sedemikian luhur, mulia, dan unggulnya ajaran Islam, sampai-sampai Ernest Renan, seperti dikemukakan di atas, tidak sanggup menentang kebenarannya. Akan tetapi, ketika ajaran-ajaran yang unggul dan mulia tersebut diterapkan pada tataran kehidupan sosial oleh para pemeluknya, terdapat jarak yang sangat jauh, sehingga pemikir modernis Muslim sekaliber Muhammad Abduh pun tidak sanggup menunjukkan bukti keunggulannya melalui suatu komunitas yang representatif bagi ajaran Islam.
Sirah-Nabawiah
Di dalam usaha mentransformasikan Islam Ideal ke ranah “Islam Faktual”, atau “Islam Doktrin” menjadi “Islam Peradaban”, sesungguhnya kaum Muslim adalah umat yang sangat beruntung. Sebab, ketika mereka diharuskan mengamalkan ajaran Islam, mereka tidak dibiarkan berjalan dan meraba-raba sendiri sesuai dengan keinginan mereka, tetapi Allah Yang Maha Penyayang telah mengirimkan kepada mereka contoh atau model dari kalangan sesama manusianya. Al-Quran menyebut manusia model ini dengan Uswah Hasanah (Teladan yang Baik), dan itu adalah Muhammad, Rasulullah Saw.
Karena merupakan contoh atau teladan dalam ranah pengamalan, maka Rasulullah Saw adalah orang pertama yang mengamalkan Al-Quran, dan praktik pengamalan Al-Quran inilah yang diajarkannya kepada para sahabatnya. Dengan demikian, Rasulullah Saw adalah “Al-Quran dalam wujudnya yang nyata”. Inilah yang menyebabkan Ibunda Aisyah Ra, mengatakan, ketika ditanya Anas bin Malik tentang akhlak Rasulullah Saw, “Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.”
Mengenai keteladanan Rasulullah Saw tersebut, Al-Quran menegaskan, Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. (Qs al-Ahzab [33]: 21)
Karena sadar akan fungsinya sebagai teladan, maka Rasulullah Saw hidup menyatu dengan para sahabatnya, dekat dan akrab dengan mereka. Sebab, hanya dengan kedekatan seperti itulah seorang teladan dapat dicontoh oleh orang-orang yang harus meneladaninya. Sedemikian dekatnya hubungan Rasulullah Saw dengan para sahabatnya, sampai-sampai orang yang sehari-harinya tidak mengenal mereka, sulit membedakan mana Rasulullah Saw dan mana pula sahabatnya. Itulah yang dialami oleh salah seorang pangeran dari Persia, ketika dia bermaksud menemui Rasulullah Saw.
Karena belum pernah bertemu, pangeran dari Persia itu bertanya kepada salah seorang penduduk Madinah yang ditemuinya, “Di mana saya bisa menemui Muhammad?”
“Di dalam masjid, dia sedang berada bersama para sahabatnya”, jawab orang itu.
Sang pangeran Persia segera menuju Masjid Nabi, dan ketika dia masuk, dilihatnya sejumlah orang yang sedang duduk dan membentuk lingkaran. Lutut mereka bertemu satu sama lain. Karena pakaian mereka rata-rata tidak berbeda, maka sulit bagi sang pangeran untuk mengenali Rasulullah Saw. Dia baru mengetahuinya ketika seseorang memperkenalkan dia dengan Rasulullah Saw.
Karenanya, merupakan suatu anugerah tersendiri bagi para sahabat ketika mereka ditakdirkan menjadi orang-orang yang hidup bersama Rasulullah Saw. Cara peneladanan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dengan menyatu dengan para sahabatnya seperti itu, menyebabkan para sahabat dapat melihat dari dekat sosok teladannya, dapat bertanya dan melihat gerak-geriknya, bentuk tubuhnya, cara berjalan dan berbicaranya, keadaan rumahtangganya, cara beribadahnya. Dengan kalimat pendek, “totalitas kehidupan sehari-hari Rasulullah Saw”. Hasilnya, para sahabat pun menjadi mudah meneladani Rasulullah Saw dalam hal-hal yang detil. Dengan kondisi seperti itu, barangkali tingkat presisi para sahabat dalam mencontoh Rasulullah Saw bisa mencapai sembilan puluh persen. Inilah yang menyebabkan Ibn Taimiyah mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah Saw generasi pertama adalah duplikat terbaik Rasulullah Saw. Melalui model peneladanan seperti itu, terbentuklah suatu komunitas yang, oleh Rasulullah Saw sendiri, disebut dengan “sebaik-baik kurun (generasi) adalah kurunku (bersama para sahabat)”.
Jika kemudian ada yang bertanya kepada para sahabat tentang Rasulullah Saw, baik mengenai bentuk tubuhnya, cara beribadah, maupun kehidupan sehari-harinya, maka para sahabat dapat menyebutkannya dengan baik. Dimulai dari seseorang yang bertanya tentang sosok Rasulullah Saw kepada salah seorang sahabat. Sahabat tersebut menjawab, “Rasulullah Saw, orangnya tidak tinggi dan tidak pendek, tetapi sedang.” Yang lain segera menyambung, “Beliau tidak kurus dan tidak gemuk.”
Sahabat yang lain menambahi, “Benar, tidak tinggi dan tidak pendek, tetapi kepala beliau sedikit lebih besar dibanding kepala orang biasa.” Dari ihwal kepala, pembicaraan berlanjut ke alis dan mata. “Alis beliau tebal dan hitam, sedangkan matanya hitamnya hitam sekali dan putihnya putih sekali.” Sahabat yang lain menyambung, “Tatapan beliau bersinar dan berwibawa, sehingga jika seseorang beradu pandang dengan beliau, pasti menundukkan wajahnya.”
“Memandang wajah beliau,” kata sahabat yang lain, “bagaikan memandang bulan purnama.”
Begitulah, dari masalah fisik, kemudian berlanjut pada perikehidupan sehari-hari Rasulullah Saw: akhlaknya, rumahtangganya, sikapnya terhadap istri-istrinya, kedekatannya dengan kaum miskin dan anak yatim, caranya memimpin peperangan dan mengatur strateginya, toleransinya kepada orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan, dan seterusnya.
Jika kemudian riwayat-riwayat tersebut dirangkaikan satu sama lain, maka terbentuklah suatu biografi yang sangat detil, yang tidak hanya mengemukakan tentang riwayat hidup dan perjuangan beliau, tetapi juga hal-hal kecil dan detil, misalnya bentuk gigi dan jumlah uban, cara tersenyum dan berjalan, cara duduk dan makan, dan lain-lain, yang sulit ditemukan pada biografi tokoh-tokoh besar lainnya. Itulah yang kemudian disebut dengan Sirah Nabawiyah.
Melakukan dan membuat sesuatu dengan ada modelnya, memang jauh lebih mudah ketimbang tanpa model. Demikian pula halnya dengan mentransformasi “Islam Ideal” menjadi “Islam Realita”, atau “Islam Doktrin” menjadi “Islam Peradaban”. Karena itu, ketika para sahabat Rasulullah Saw berusaha melakukan transformasi dengan teladan nyata diri beliau, maka Islam Realita yang mereka hadirkan nyaris mendekati tingkat idealnya, bahkan dalam beberapa hal lebih mirip legenda ketimbang fakta. Lalu, ketika Sang Uswah Hasanah telah tiada, dan jarak zaman semakin jauh, hasil transformasi itu pun mengalami kemerosotan demi kemerosotan. Sampai-sampai, Muhammad Abduh pun tidak sanggup mengemukakan adanya suatu komunitas yang representatif bagi ajaran Islam yang mulia dan sempurna itu.
Sebenarnya, kemerosotan seperti itu tidak harus terjadi jika fungsi keteladan Rasulullah Saw berjalan berkelanjutan, dalam arti terdapat tokoh-tokoh yang dapat dijadikan panutan dan teladan oleh kaum Muslim. Hal seperti itu sebenarnya sudah ditegaskan oleh Rasulullah Saw, ketika Nabi yang mulia ini mengatakan, “Ulama adalah pewaris para Nabi,” dan para ulama pun berusaha keras untuk merealisasikan hal itu.
Sampai masa tabi’in generasi ketiga, kaum Muslim masih memiliki tokoh-tokoh panutan, baik dalam ilmu maupun akhlak, seperti Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Ghazali, sampai dengan Ibn Taimiyah. Tetapi, pada masa-masa selanjutnya, satu per satu para ulama tersebut dipanggil menghadap Allah Swt, tanpa ada lagi yang melanjutkannya. Rasululah Saw bersabda, “Ilmu dicabut bukan dengan cara mencabutnya ke langit, tetapi dengan wafatnya para ulama.” Walhasil, generasi berikutnya pun hidup nyaris tanpa uswah dan tanpa ilmu, karena para ulama telah meninggalkan mereka. Kondisi inilah yang kemudian kita kenal dengan “krisis keteladanan”.
Dalam kondisi seperti itu, usaha mentransformasikan “Islam Ideal” ke tataran “Islam Realita”, atau “Islam Doktrin” menjadi “Islam Peradaban”, sungguh merupakan usaha yang teramat sulit, lebih-lebih lagi ketika pandangan hidup sekular-materialistik sudah mengepung di kiri-kanan kita. Maka, di sinilah pentingnya Sirah Nabawiyah. Dari buku Sirah Nabawiyah ini kita dapat menghadirkan kembali keteladanan Rasulullah Saw, sekalipun tidak lagi dalam bentuk nyatanya. Karena itu, bagi setiap keluarga Muslim, Sirah Nabawiyah haruslah menjadi buku wajib kedua sesudah Al-Quran al-Karim.
Mempelajari Sirah Nabawiyah berarti mempelajari perikehidupan Rasulullah Saw, dan itu mencakup semua aspek kehidupan beliau, baik pada sisi hablun minallâh maupun sisi hablun minan-nâs. Sayangnya, kaum Muslim kurang memberi perhatian yang seimbang terhadap kedua ranah tersebut. Sepertinya, bagi kaum Muslim saat ini, hablun minallâh itu lebih penting ketimbang hablun minannâs. Bahkan, dalam bidang yang satu ini, hablun minallâh (kesalehan ritual) kita temui adanya sekelompok Muslim yang demikian ketat dan penuh semangat ingin meneladani Rasulullah Saw secara tepat.
Sedemikian ketatnya cara beribadah mereka, sampai-sampai semuanya harus seperti yang diamalkan Rasulullah Saw. Sedikit tambahan saja, mereka akan menolak secara keras, dan menyebutnya sebagai bid’ah. Yang sangat disesalkan adalah bahwa usaha mereka untuk meneladani Rasulullah Saw berhenti pada aspek-aspek ibadah ritual (hablun minallâh), sedangkan aspek-aspek sosialnya (hablun minan-nâs) sangat terabaikan. Rasanya, belum pernah kita dengar adanya seseorang yang mengatakan bahwa dalam kehidupan sosial, sebagaimana bidang ritual, kita harus sepenuhnya mencontoh Rasulullah Saw. Di sini, mereka seakan-akan meyakini bahwa inti ajaran Islam yang paling utama adalah aspek-aspek ritual, sedangkan aspek sosial berada pada urutan entah keberapa.
Buku yang ditulis oleh Ajid Thohir, yang kini ada di tangan pembaca, tidak saja membicarakan Sirah Nabawiyah dalam substansinya, tetapi juga mengemukakan cara memahami Sirah Nabawiyah melalui pendekatan ilmu sosial-humaniora. Dengan usahanya ini, Doktor yang mengambil spesialisasi Sejarah Peradaban Islam ini, mengajak kita untuk melakukan reinterpretasi Sirah Nabawiyah seperti yang dirintis oleh pemikir besar Islam dari Iran, Ali Syari’ati. Saya yakin buku ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi usaha kita dalam menghadirkan keteladanan Rasulullah Saw di era global yang penuh tantang dan peluang ini. []
Prof. Dr. Afif Muhammad, MA, Guru Besar Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung dan Ketua Prodi S3 Religious Studies Pascasarjana.
Tulisan ini merupakan Kata Pengantar dalam buku Sirah Nabawiyah, karya Dr. Ajid Thohir.