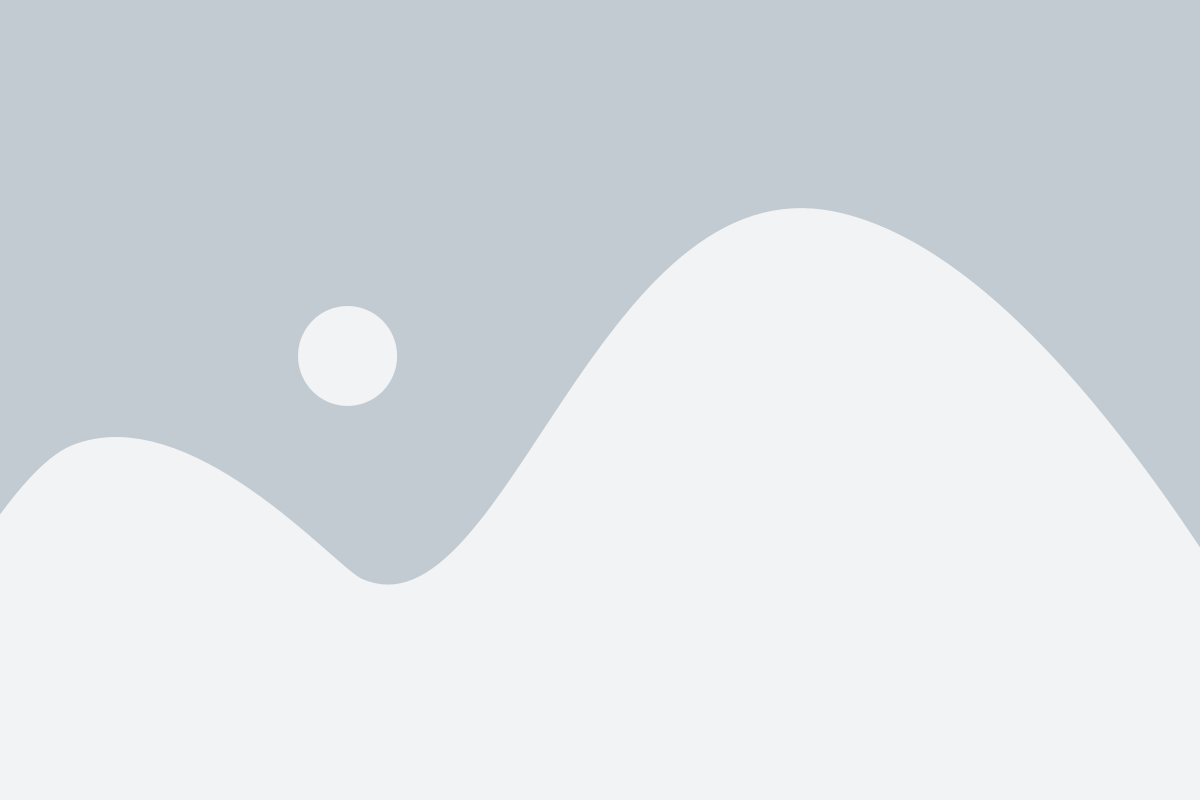Ritual atau ibadat, merupakan essensi setiap agama. Dalam Islam, ritual, berarti pengabdian diri kepada Allah SWT. Dalam arti luas, ritual Islam mencakup seluruh kegiatan manusia, termasuk kegiatan duniawi sehari-hari jika dilakukan dengan sikap batin dan niat penghamban kepada-Nya. Inilah yang dimaksud dalam Firman Allah bahwa manusia dan jin tidaklah diciptakan, kecuali untuk beritual kepada-Nya (Q.S.51:56).
Berdasarkan referensi ayat itu, maka tugas pokok manusia dan jin pada hakekatnya adalah untuk mengabdi kepada-Nya. Bagi manusia, tugas untuk mengabdi kepada Tuhan tidak lantas merubah fungsinya sebagai makhluk sosial di dunia ini yang di dalamnya selalu terjadi interaksi sosial sesama manusia. Untuk itu, orientasi hidup akhirat dan hubungan interaksi sosial dengan manusia sekitarnya, senantiasa tetap berada dalam kerangka ritual. Dari sini, berarti pola keseimbangan antara ritual dengan ibadah sosial, menjadi sebuah keharusan.
Namun dalam peradaban modern sekarang ini, nampak fenomena ketidakseimbangan manusia dalam mengaktualisasikan peran ‘abid (kehambaan) dengan fungsi sosialnya di dunia. Antara urusan duniawi dengan ritual sering terjadi kepincangan, sehingga tidak sedikit orang harus diingatkan agar dalam pelaksanaan urusan dunia tidak lupa akhirat. Yang umum terjadi sekarang ialah penunaian tugas keduniaan tidak seimbang dengan kewajiban untuk keakhiratan.
Padahal, antara keduanya mesti dalam rumusan yang seimbang. Referensi populer yang terkait persoalan ini adalah: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan bekerjalah seakan engkau akan mati esok hari”.
Referensi itu akan lebih applicable bila difahami dalam kerangka “tawazun” (keseimbangan) antara aktivitas duniawi dan ukhrawi. Ritual yang dilakukan secara mahdhah, dalam arti bersifat vertikal antara manusia dengan Tuhannya, seperti dalam bentuk shalat, puasa, dan sebagainya, harus berdampak horizontal bagi kehidupan manusia, yaitu pada dimensi ibadah sosialnya.
Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan berita tentang seorang yang berpredikat “kiyai”, “ustadz”, atau “pastur” yang notabene tidak pernah tinggal shalat atau aktif ke gereja, tetapi tiba-tiba diberitakan terlibat korupsi.
Kita juga menemukan tentang orang-orang yang hidup dan dibesarkan dalam kultur santri, tetapi ketika terjun ke dunia politik, ternyata memakai cara-cara yang tidak mengenal fatsoen. Sikap saling menggunting dalam lipatan, saling memfitnah, dan perilaku saling menjatuhkan, menjadi beigut akrab menghiasi tindak kesehariannya. Mereka berlindung dalam jargon reformasi, atau bermanis bibir dengan bahasa demokrasi atau apapun namanya, yang sesungguhnya banyak menyulap “ambisi” menjadi seperti “kesalehan”. Begitu juga mereka yang menduduki jabatan tertentu, walaupun telah dilantik dan disumpah secara kesantri-santrian, tetapi setelah semuanya berlalu, mereka banyak yang melanggar sumpah jabatan yang “sakral” itu.
Pada tingkat itu –sadar atau tidak– perilaku keagamaan mereka telah masuk dalam kategori “kesalehan formalistik” atau kesalehan simbolik. Kesalehan formalistik adalah kesalehan yang tercipta hanya karena tuntutan formal. Sekedar contoh, misalnya seseorang memakai jilbab hanya karena bekerja pada instansi yang mengharuskannya berjilbab; seseorang mentaati rambu-rambu lalu lintas, hanya karena takut pada polisi; atau seseorang yang selalu bermanis bibir dan seolah bekerja dengan baik, hanya karena takut atau bahkan berharap pujian dari atasannya. Jika sudah seperti ini, maka pemahaman agama dan aktivitas keagamaannya, telah menyentuh tindakan yang dalam bahasa agama dikenai penilaian “zhalim”.
Kesalehan formalistik dan kezhaliman itu, menjadi terbukti dengan fenomena betapa alam “reformasi” sekarang ini menjadi seperti liar dan bebas nilai. Akibatnya, kita melihat betapa agama –yang akhir-akhir ini dinilai tengah mencapai perkembangan yang menakjubkan– ternyata tidak mengubah akhlak sosial yang dewasa ini justru semakin memburuk.
Di satu sisi, betapa orang berduyun-duyun pergi ke mesjid-mesjid, mushala-mushala atau tempat-tempat ibadah lainnya, tapi pada sisi lain terjadi dekadensi moral, yakni dengan fenomena semakin kukuhnya budaya sogok, kolusi, korupsi, uang pelicin, dan pemerasan, yang semakin menyeruak ke permukaan akhir-akhir ini. Persoalannya, tidak adakah pengaruh ritual pada etika sosial?
Penyebab hal itu bisa dideteksi melalui fenomena kehidupan manusia yang terus dihadapkan pada situasi persaingan kepentingan, sedang kebutuhan hidup semakin mendesak. Yang terjadi kemudian, eksistensi manusia banyak yang diabdikan pada tujuan dan pamrih ekonomi. Hidup ini menjadi semacam untuk “perut” an-sich. Titik sentral kehidupan berorientasi hanya pada produksi dan konsumsi. Mereka hidup dalam apa yang disebut oleh Max Weber sebagai “semangat kapitalisme modern”.
Dalam kehidupan modern ini ada indikasi bahwa dalam struktur masyarakat tengah bersemayam “Darwinisme Sosial”, yang berarti bahwa masyarakat harus serba unggul untuk bisa bertarung memperjuangkan hidupnya. Mereka yang malas, kurang berkualitas dan kurang ambisius, akan tersisih dengan sendirinya. Hal ini dianggap wajar, sejalan dengan hukum yang diteorikan Darwin (Ali Maksum, 1995).
Dalam arus kehidupan Darwinis yang berpusat pada pamrih ekonomi serta hedonisme keduniaan tersebut, nasib agama mendapat ujian berat, akibat gempuran ilmu pengetahuan, teknologi dan kepentingan ekonomi. Orientasi ekonomi dan keduniaan semakin kokoh menjadi “berhala baru”. Rasioanlisme, empirisme, positivisme dan pragmatisme mendapat tempat terhormat –yang semuanya cenderung mengangkat dunia fana sebagai majikannya– sementara agamanya tercampakkan.
Disitulah berkembang budaya keinderawian (sense of culture), yang orientasinya sangat sekularistik dan kebendaan. Inilah sumber krisis makna hidup dan idealisme moral di masyarakat. Yang terjadi kemudian adalah kemajuan budaya dan peradaban masyarakat modern terlepas dari kendali agama “mainstream” (Ali Maksum, 1995).
Dahulu, tidak sedikit orang meminta resep hidup bahagia, adalah dengan datang ke kiyai atau ustadz-ustadz; Dahulu, orang mencari perlindungan keselamatan adalah dengan sering mengunjungi mesjid atau mushala; dan dahulu, banyak orang mengadukan nasibnya dengan meminta nasihat kepada hamba Allah yang saleh dan dimuliakan-Nya. Tetapi kini semuanya telah berubah. Mereka meminta resep hidup bahagia kepada ahli-ahli ekonomi; mereka mencari perlindungan keselamatan ke bank-bank; dan mereka mempertaruhkan nasibnya kepada lembaga-lembaga asuransi.
Dari fenomena-fenomena seperti dijelaskan di atas, hemat penulis perlu rumusan keseimbangan antara ritual dengan etika sosial. Pentingnya rumusan keseimbangan ini, karena mempunyai signifikansi untuk mengantisipasi kecenderungan terjadinya pen-distorsi-an agama, berkembangnya kesalehan formalistik, dan terjadinya dekadensi moral serta anomali nilai. Dalam perspektif ini, maka ritual yang kita lakukan perlu diformat ulang agar teraplikasi secara kaffah dalam realitas sosial.
Tesis yang bisa diajukan adalah: Pertama, dengan memformat rituali Islam sebagai “Ethical Religion”. Yakni, dalam arus sekularisasi dan modernisasi ini manusia tidak mencampakkan agamanya begitu saja. Tetapi justeru agama selalu dijadikan cermin untuk menghadap, aplikasi dalam bersikap, serta menjadi pegangan, pengendali, dan frame of reference (kerangka acuan) yang selalu memberikan sentuhan nilai, baik yang berdimensi sosial, politik, ekonomi maupun intelektual. Format ini mengacu pada Firman Allah: “Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus…” (Q.S.30:43).
Kedua, memformat ritual Islam sebagai “Spiritual Religion”. Artinya, ketika manusia sibuk dengan aktivitas keduniaan, namun kebutuhan spiritualnya tidak diabaikan. Dengan demikian manusia akan selalu berjalan pada jalur eksistensi sebagai makhluk yang harus beritual kepada-Nya, dan sekaligus tetap peduli kebutuhan duniawi sebagai makhluk sosial. Dalil yang sejalan dengan tesis ini adalah: “Carilah apa-apa yang menjadi bagianmu untuk kehidupan akhirat, tetapi jangan kamu lupa dengan bagianmu di dunia ini” (Q.S. 28:77).
Ketiga, memformat ritual sebagai “kesatuan dari universalitas”, terutama dalam upaya pembentukan wihdatul aqidah (kesatuan aqidah), wihdatul kalimah (kesatuan kalimat), dan wihdatul ummah (kesatuan ummat). Ritual yang dilakukan oleh setiap individu muslim harus mempunyai dampak bagi terbinanya kesadaran akan kesatuan aqidah di antara sesama kaum muslimin. Ritual yang dilakukan juga harus menumbuhkan kesamaan kalimat, yakni kalimat “Allah” yang terefleksi baik secara tekstual maupun kontekstual. Selain itu, ritual yang akan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka sesama muslim sebagai satu ummat.
Keempat, memformat ritual Islam sebagai “Individual and Social Action”. Pada format ini, yang menjadi orientasi ritual, disamping pembentukan “kesalehan individual” juga terbentuknya “kesalehan sosial” dan “kesalehan struktural” yang terbebas dari “kesalehan-kesalehan formalitik”. Bentuk intensifikasi keimanan dan ritualnya selain berorientasi “ke dalam” (inward oriented) juga intensifikasi “ke luar” (outward oriented).
Intensifikasi keagamaan selain bersifat pribadi (aspek esoterisnya), juga mampu menjelmakan dalam komitmen yang tinggi, tidak hanya mentransformasi dalam kehidupan individual, tetapi juga sekaligus kehidupan komunal (aspek eksoterisnya). Dalil yang mengarah ke sini adalah: “Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agamamu secara kaffah (keseluruhan)” (Q.S.2:208).
Seruan Allah itu mengisyaratkan bahwa kekaffahan agama pada setiap muslim tidak berarti hanya pada dimensi vertikal saja tetapi juga pada dimensi horizontalnya. Orang hidup memang harus mengintensifkan ibadah secara individual kepada Tuhan, tetapi jangan lupa pada tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial yang dituntut harus selalu concern pada realitas sosial di sekelilingnya.
Untuk itu, sudah selayaknya kita mengoreksi kembali visi keagamaan kita agar pemahaman dan aktualisasi ritual kita –seperti yang terumuskan dalam format-format ritual di atas– dapat terimplementasi dalam bentuk etika sosial.[]
Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag., Pgs Rektor UIN SGD Bandung.