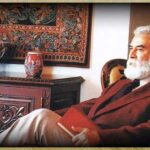Ramadhan di Indonesia tidak pernah benar-benar sama dari masa ke masa
—-
UINSGD.AC.ID (Humas) — Di pedesaan wilayah Cimahi Selatan, tempat aku lahir dan menjalani kehidupan anak-anak dan remaja tahun 1970–1980-an, Ramadhan hadir dalam bentuk yang nyaris tanpa dekorasi. Tidak banyak spanduk si jalanan atau di warung-warung. Tidak ada lampu “hias” tematik, hatta di mesjid sekalipun. Yang ada hanya suara bedug atau pengeras suara masjid yang kadang serak karena energi aki “battery” nyaris habis. Malamnya, shalat tarawih dilaksanakan dalam temaram lampu cempor atau petromak (minyak tanah) yang sesekali harus dipompa agar terang kembali.
Pada waktunya, terkadang jelang sahur ada suara kentongan sahur, atau anak-anak yang berlarian membawa obor di penghujung Ramadhan menjelang takbiran. Saat itu, puasa terasa lebih sebagai disiplin kolektif daripada perayaan atau seremoni. Warung-warung buka untuk menjajakan panganan untuk sahur dan buka, sedangkan warung nasi umumnya buka jelang malam.
Orang-orang menahan diri bukan karena kamera atau unggahan media sosial, tetapi karena malu pada tetangga. Solidaritas lahir dari kedekatan fisik (kekerabatan; geneologis), atau kerekatan sebagai tetangga. Jika satu keluarga kekurangan, kabar itu cepat menyebar. Ramadhan menjadi ruang sosial yang mempersempit jarak.
Karenanya, dalam tradisi fikih, puasa memang memiliki dimensi sosial. Yusuf al-Qaradawi dalam “Fiqh al-Shiyâm” menekankan bahwa tujuan puasa adalah taqwa yang berimplikasi sosial—membangun empati dan keadilan. Dalam konteks masyarakat desa, “maqashid” (tujuan) puasa itu terasa konkret: lapar bukan metafora, tetapi pengalaman yang juga dirasakan sebagian tetangga sepanjang tahun.
Namun, kini suasana Indonesia berubah cukup cepat, bahkan “radikal”. Urbanisasi menggeser pola relasi. Kota tumbuh di berbagai penjuru wilayah. Pusat perbelanjaan (mall atau supermarket” menjadi ruang publik baru, yang rame-rame menawarkan discount dan “iming-iming” lainnya. Dan Ramadhan perlahan memasuki etalase formal serta menjadi bagian dari komoditas sosio-ekonomi.
Spanduk diskon menyambut bulan suci bahkan sebelum hilal terlihat. Paket “bukber” dirancang lebih awal daripada program sedekah dan zakat fitrah. Di layar televisi, Ramadhan menjadi musim rating tinggi, terlebih bagian alunan adzan Maghrib yang dinanti oleh segenap yang berpuasa.
Apakah ini berarti maknanya hilang? Tidak sesederhana itu. Karena Sejarah dan ritual selalu bergerak dalam dialektika dan kompleks. Pada satu sisi, komersialisasi memang berpotensi mengebiri makna. Lapar siang hari dibalas pesta malam hari. Kesederhanaan diganti kompetisi kuliner. Puasa berubah menjadi pola konsumsi musiman yang menggerakkan roda ekonomi yang signifikan.
Pada sisi lain, modernitas juga membuka peluang baru: kajian daring menjangkau ribuan orang, melalui media sosial, baik GWA komunitas, Thread, X, instagram, dll. Begitu pula, penggalangan zakat menjadi lebih sistematis, dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar fisik, tetapi lewat layar digital yang terpersolalisasi.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah Ramadhan berubah, tetapi: bagaimana kita membaca perubahan itu?
Dalam “Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn,” khususnya Kitab “Asrar al-Shawm”, Abu Hamid al-Ghazali mengingatkan bahwa inti puasa adalah pengendalian diri dan pembersihan hati. Prinsip ini lintas zaman. Ia tidak bergantung pada kentongan atau notifikasi. Yang berubah adalah konteksnya.
Dulu, tantangan puasa mungkin lebih pada kebutuhan fisik. Hari kerja berat. Sawah luas. Matahari terik. Sesekali godaan datang dari televisi, game watch, atau hiburan rakyat di pekarangan atau lapangan. Ketiadaan fisik di mesjid dan madrasah seringkali jadi “gunjingan” jemaah, teman, atau tetangga
Kini, tantangannya lebih subtil: distraksi digital, budaya instan, dan eksposur berlebihan. Kita tidak lagi diuji hanya oleh lapar dan haus, tetapi oleh perhatian yang terpecah karena “godaan” digital pada layar gadget. Sebentar saja membaca al-Qur’an digital di HP, maka beberapa status muncul dalam notifikasi yang memecah kekhusyuan qirâ’ah atau tiláwah. Begitu pula, kala melakukan shalat, getaran hp di saku atau layar yang hidup karena ada yang nelepon, maka kekhusyuan pun memudar.

Ilustrasi Ramadan / Foto: Getty Images/iStockphoto/TanyaSid
—-
Jika melihat lebih jauh, Ramadhan di Indonesia juga pernah menjadi momentum kebangkitan sosial-politik. Di berbagai periode sejarah, bulan ini melahirkan solidaritas umat, gerakan sosial, bahkan konsolidasi perlawanan moral terhadap ketidakadilan. Dalam kerangka ini, puasa bukan sekadar ibadah privat, tetapi latihan kolektif membangun etos, yakni etos disiplin, etos kesabaran, serta etos keberpihakan pada yang lemah.
Ibn al-Qayyim dalam “Zâd al-Ma‘âd fi Hadyi Khayr al-‘Ibâd” menekankan bahwa praktik Nabi selalu terhubung dengan pembentukan karakter dan komunitas. Puasa bukan ritual terisolasi; ia membentuk manusia yang siap berkontribusi pada masyarakat.
Jika ditarik ke konteks Indonesia hari ini, pertanyaannya menjadi lebih tajam: apakah Ramadhan masih membentuk karakter kolektif, atau hanya menjadi jeda konsumsi yang terjadwal?
Ada pula dimensi kesehatan yang sering terabaikan dalam sejarah budaya kita. Tradisi berbuka dengan yang manis dan sederhana pada masa lalu—kurma atau air gula—berangkat dari prinsip moderasi. Dalam Al-Qanun fi al-Tibb, Ibn Sina berbicara tentang keseimbangan sebagai fondasi kesehatan.
Kini, berbuka sering berubah menjadi pesta “kuliner” berlebih. Panganan dikumpulan melalui tradisi “berburu takjil”. Tubuh yang siang hari dilatih menahan, malam hari justru dipaksa menerima limpahan makanan dan minuman. Di sini terlihat bagaimana perubahan budaya turut menggeser praktik spiritual.
Maka menyambut Ramadhan hari ini memerlukan kesadaran historis. Kita tidak bisa sekadar bernostalgia pada kesederhanaan masa lalu, karena konteks telah berubah. Tetapi kita juga tidak boleh menyerah pada arus komersialisasi.
Persiapan Ramadhan di era modern mungkin berarti memilih secara sadar, yakni mengatur konsumsi di tengah kelimpahan, menjaga fokus di tengah distraksi, serta membangun empati di tengah anonimnya kota.
Ramadhan selalu bergerak bersama sejarah kita.
Ia tidak pernah statis. Yang menentukan bukan apakah zaman berubah, melainkan apakah kesadaran kita ikut tumbuh. Puasa adalah momentum tumbuh jiwa spiritual dan intelektual.
Jika dulu kentongan sahur membangunkan tubuh, mungkin kini yang harus dibangunkan adalah “notifikasi jiwa kesadaran”. Namun itu tidak pernah otomatis.
Dadan Rusmana, Wakil Rektor I UIN Sunan Gunung Djati Bandung.