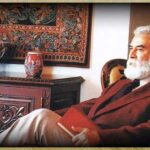Desember 1995. Di hari ketika Emmanuel Levinas hendak dikuburkan, Jacques Derrida menyampaikan ceramah yang menggetarkan. Sebuah paparan yang disampaikan dengan ekspresi ketakutan tentang fakta yang berada di luar kendali dirinya. Fakta tentang “perpisahan” yang tidak satu pun makhluk yang bisa menahannya: kematian.
“Sudah sejak lama, bahkan lama sekali, aku merasa takut untuk mengatakan ‘selamat tinggal’ kepada Levinas. Aku tahu suaraku akan gemetar saat mengatakannya, apalagi saat mengatakannya dengan suara yang keras, tepat di sini, di hadapan Levinas, begitu dekat dengannya….”
Ini pernyataan yang tidak biasa. Ini bukan semata-mata ekspresi ketakutan karena harus berpisah dengan Levinas. Melampaui itu, ketakutan yang mendera Derrida adalah ketakutan yang mengguncang kebahasaan. Saat bahasa menjadi limbung. Hubungan penanda-petanda yang retak dan tidak stabil.
Derida disergap sejenis ketakutan untuk berucap “selamat tinggal” kepada Levinas. Jasadnya yang kaku dan membisu tak lagi merespons. Ia sudah tidak ada lagi. Tidak hidup lagi.
Ucapan “selamat tinggal” menjadi tidak ada maknanya. Ia seperti membentur ruang hampa. Kepada siapa Derrida berucap “selamat tinggal” jika pada kenyataannya Levinas sudah dimakamkan? Normalnya, ucapan “selamat tinggal” hanya ditujukan kepada orang yang masih berwujud. Ia hidup di hadapan kita. Ia berdiri dengan respons yang terbaca melalui gerak tubuh, mata atau sungging senyumnya. Bagi Derrida, kematian bukan hanya sebuah “peristiwa biologis”, tetapi juga sebuah “peristiwa lingusitik”.
Hari ini, ketika sampai ke telinga saya tentang kabar kematian seorang teman bahkan Guru, kabar kematian ini mengurai makna yang jauh berbeda. Bukan lagi sebuah retakan kebahasaan, tetapi juga sebuah momen hilangnya jangkar refleksi atas keber-ada-an.
Sungguh saya bersedih. Dan kesedihan ini semakin bertumpuk setelah beberapa waktu lalu juga kehilangan seorang teman juga Guru yang patut untuk dijadikan teladan. Kematian yang memisahkan. Tapi bisakah kita menunda bahkan melawan?
Al-Samarqandi seorang penyair Sufi pernah berkata: “Akulah kematian yg akan memisahkan segala yg dicintai. Akulah kematian yg memisahkan lelaki dan perempuan, suami dan istri. Akulah Kematian yg memisahkan anak-anak perempuan dari ibunya. Akulah kematian yg memisahkan anak laki-laki dari bapaknya. Akulah kematian yg memisahkan saudara dari saudaranya. Akulah kematian yg menundukkan kekuatan anak-anak Adam. Akulah kematian yg menghuni kubur. Tidak satupun makhluk yg mampu bertahan utk tidak merasakanku”.
Buya. Yang pergi adalah magnet yang memancarkan uswah penuh pesona. Ia menunjukkan laku spiritual yang matang yang tidak sekadar berbingkai luasnya ilmu tapi juga mengalir melalui bukti yang bisa dikenali secara jelas dalam laku dan polah sehari-hari. Sikap yang tidak dibuat-buat seperti kebanyakan politisi. Sikap tulus yang menghargai dan “memanusiaakan” siapapun yang berbicara dengannya.
Buya. Pernah suatu waktu saya tawasulan dengannya. Ia bahkan menyampaikan paparan tentang jalan spiritual. Tentang laku manusia dalam meniti perjalanan menuju ilahi. Tentang keharusan menjaga akhlak dan budi pekerti. Sosok yang teduh juga teduh. Sosok ‘alim yang menginspirasi. Tuturnya, “jujur kepada orang lain lebih gampang daripada jujur kepada diri sendiri”.
”Mautul ‘alim mautul ‘alam, matinya seorang ‘alim adalah matinya alam,” begitu kata Gus Mus. Sekaligus juga berarti matinya seseorang yang berilmu adalah padamnya cahaya ilmu. Gelap. Kata-kata Gus Mus, adalah juga isyarat untuk tak berlama-lama membiarkan kegelapan menguasai hidup kita. Bangkit, jaga nyala yang masih hidup. Mari nyalakan pelita berikutnya!
Allahu a’lam[]
Tabik!
Dr. Radea Juli A. Hambali, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung.