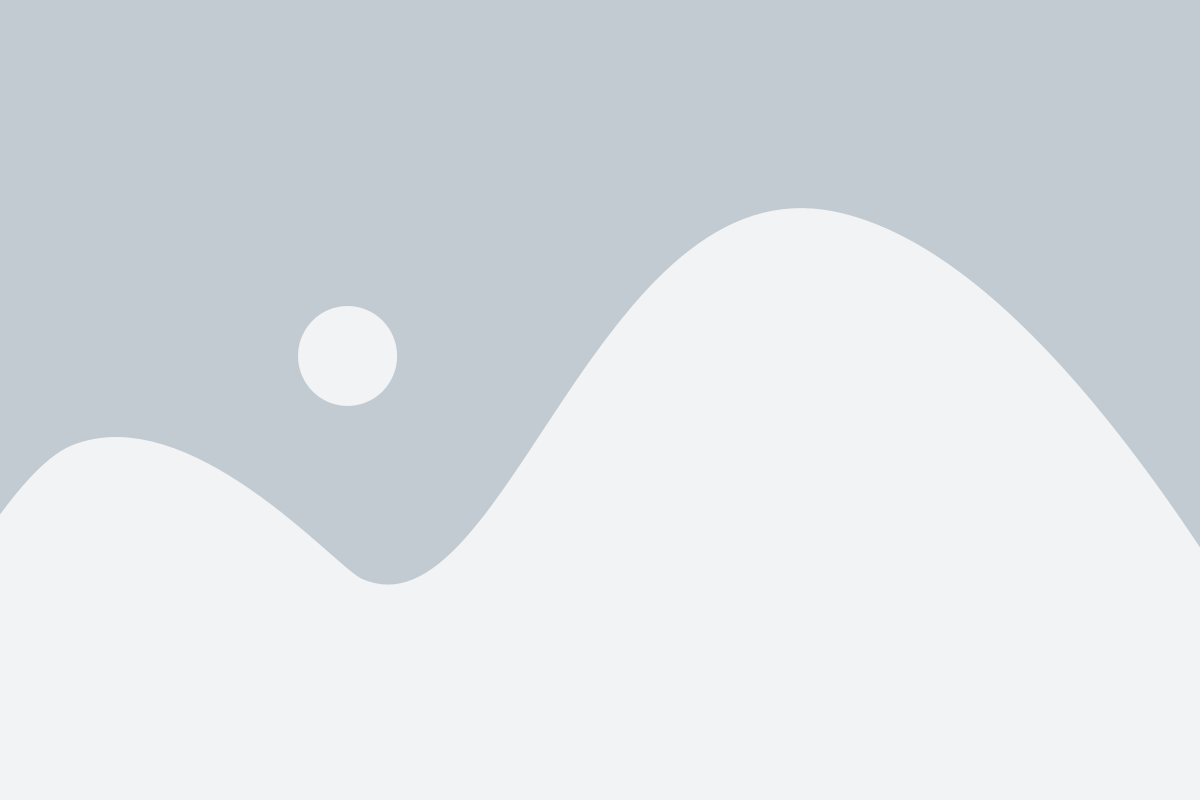Agama dan Keberagamaan
Tulisan ini berangkat dari tiga dimensi utama dalam beragama, yaitu doktrin, penyikapan (pemahaman), dan pelaksanaan terhadap doktrin itu. Dari ketiga dimensi ini, maka dalam studi keagamaan seringkali dibedakan antara ‘agama’ (religion) dengan ‘keberagamaan‘ (religiosity). Dalam kajian-kajian sosiologis, misalnya, kita sering menemukan dua istilah ini. Agama berkaitan dengan doktrin sedangkan keberagamaan berkaitan dengan penyikapan terhadap doktrin itu. Doktrin tiada lain adalah keyakinan, sedangkan penyikapan mengandung arti pemahaman dan pemaknaan terhadap doktrin. Oleh karena itu, agama sebagai doktrin kebenarannya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, sementara keberagamaan sebagai penyikapan atas doktrin itu kebenarannya bernilai relatif, termasuk “kebenaran” hasil pemahamannya itu menjadi bernilai relatif pula, karena setiap orang yang meyakini doktrin itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Setiap penyikapan terikat oleh sosio-kultural; dan setiap lingkungan sosio-kultural tertentu ini sangat mempengaruhi terhadap pemahaman seseorang tentang agamanya.
Demikian pula, jika mengikuti pandangan para penstudi agama-agama pada umumnya, memang membedakan dua istilah itu. Religion biasa dialih bahasakan menjadi “agama” yaitu himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku, yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Sedangkan religiosity, istilah ini lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang diyakininya.[1] Dalam kehidupan para penganut agama, antara doktrin dan penghayatannya tidak bisa dipisahkan. Keduanya menunjukkan dinamika kehidupan dalam beragama. Pada sisi lain, pengungkapan keyakinan agama seseorang atau sekelompok orang, akan berhadapan dengan berbagai keyakinan agama yang beragam. Oleh karena itu, beberapa pandangan, teori, dan berbagai pengalaman telah muncul berkaitan dengan, bagaimana keyakinan seseorang atau sekelompok orang bisa hidup berdampingan secara aman, damai, dan rukun dengan berbagai keyakinan lain yang berbeda.
Oleh karena itu, dalam konteks keberagamaan itulah akan muncul keragaman pandangan dan faham keagamaan. Tingkat keragaman dalam beragama ini sangat memungkinkan terjadi sekalipun dalam kepenganutan agama yang sama. Joachim Wach menyatakan bahwa keberagaman pemahaman ini mewujud dalam tiga bentuk, yaitu thought (pemikiran) berupa sistem kepercayaan; practice (praktek-praktek keagamaan) berupa pengabdian dan upacara keagamaan; dan followships (kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga keagamaan).[2] Tinggi rendahnya kualitas beragama sebagai “perwujudan” kebenaran agama yang diyakininya itu, terletak pada manusianya, karena memang hanya manusia yang menganut agama. Taufik Abdullah menguatkan pandangan ini dengan menekankan, bahwa memahami agama tiada lain adalah memahami kebenaran agama dari realitas empiris, yang berarti apa-apa yang diyakini dan diperbuat oleh manusia dalam kesehariannya sebagai manusia beragama.[3]
Penyikapan dan pandangan yang bermacam ragam itu secara intuitif ditangkap oleh Scheilermacher, bahwa keragaman itu sebenarnya semakin menunjukkan adanya kesatuan di antara (para penganut) agama-agama. Ia mengatakan, bahwa “semakin pesat kemajuan dalam beragama, akan semakin nampak bahwa dunia keagamaan adalah satu kesatuan yang tak terbagi”. Max Muller, seorang perintis “Science of Religion” (Religionswissenschaft), juga mengatakan bahwa : “hanya ada satu agama universal dan abadi yang melingkupi, mendasari dan melampaui semua agama-agama yang di situ mereka termasuk atau dapat dimasukkan”.[4] Ungkapan semacam ini hanyalah untuk menunjukkan bahwa agama dan keberagamaan itu merupakan “sesuatu yang diyakini dan dipahami manusia”. Suatu keyakinan tidaklah berarti apa-apa manakala tidak diekspresikan dalam tindakan beragama oleh manusia, atau bisa dikatakan sebagai penerapan konkrit nilai-nilai yang dimiliki manusia.[5]
Sementara, Smith mencoba “mempersoalkan” agama berdasarkan apa yang diyakini dan diperbuat manusia, karena kebenaran itu muncul berdasarkan yang dipahami oleh manusia. Keberagamaan seseorang, bagaimanapun akan dipengaruhi oleh struktur sosial, politik dan kultural setempat dimana agama itu hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, kenapa “perwujudan” Islam di Indonesia bisa dibedakan dengan Islam di Arab Saudi, Pakistan atau Mesir? Juga, kenapa Hindu di India berbeda dengan Hindu di Bali? Oleh karena itu, setiap agama tidak dapat dipisahkan dari cirinya yang “kompromistis” atau “akomodatif”. Sifat akomodatif terletak pada penghampiran manusia terhadap agamanya yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kultur dan politis dimana ia hidup. Sebaliknya, sebagai sistem keyakinan, agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan suatu masyarakat dan menjadi pendorong tindakan-tindakan anggota masyarakat supaya tetap berjalan sesuai dengan niali-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya.[6]
Tulisan ini mencoba menganalisis perbedaan keyakinan dan keragaman dalam beragama adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari. Tetapi persoalannya adalah, bagaimana keragaman itu bisa tetap berjalan dalam konteks kerukunan sebagaimana secara essensial diinginkan oleh semua agama?
Pluralisme Beragama dan Keragaman Budaya
Secara fenomenologis, istilah ‘pluralisme beragama’ (religious pluralism) menunjukkan pada fakta, bahwa sejarah agama-agama menampilkan suatu pluralitas tradisi dan berbagai varian masing-masing tradisi. Sedangkan, secara filosofis istilah ‘pluralisme beragama’ menunjukkan pada suatu teori partikular tentang hubungan antara berbagai tradisi itu. Teori itu berkaitan dengan hubungan antar berbagai agama besar dunia yang menampakkan berbagai konsepsi, persepsi, dan respon tentang ultim yang satu, realitas ketuhanan yang penuh dengan misteri. Teori hubungan antar agama itu, paling tidak didekati melalui dua bentuk utama, eksklusivisme dan inklusivisme.[7] Sebaliknya, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Demikian juga, pluralisme tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (negative good), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme. Tetapi, pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”. Bahkan, pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.[8]
Makna pluralisme seperti itu, terungkap dalam Kitab Suci Alquran (S.2:251) : “Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur; namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam”. Suatu penegasan, bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia.[9] Dengan demikian, pluralisme bisa muncul pada masyarakat dimanapun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin cerdas dan tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sektarianisme. Pluralisme harus dimaknai sebagai konsekuensi logis dari Keadilan Ilahi – bahwa keyakinan seseorang tidak dapat diklaim benar dan salah tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan komunikasi, dan klaim-klaim kebenaran yang dibawa dengan kendaraan ekonomi-politik dan kemudian direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, tidak akan diterima oleh seluruh komunitas manusia manapun.
Pada situsi dewasa ini, diperlukan kesadaran akan sipat dan hakekat “pluralistik” dan “lintas budaya”. Disebut pluralistik, karena tidak ada lagi satu budaya, ideologi, maupun agama yang dapat mengklaim sebagai satu-satunya sistem yang unik dan bahkan terbaik dalam pengertian absolut. Di sebut lintas budaya, karena komunitas manusia tidak lagi hidup dalam sekat-sekat, sehingga setiap persoalan manusia saat ini yang tidak dilihat dalam parameter kemajemukan budaya adalah persoalan yang secara metodologis salah letak.[10]
Berdasarkan fakta empiris-historis, keragaman beragama (pluralitas) tidak mungkin bisa dihindari. Inilah yang diingatkan oleh Nurcholish Madjid, bahwa sistem nilai plural adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) yang tidak mungkin berubah, di ubah, di lawan, dan diingkari. Barangsiapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan.[11] Demikian juga pandangan H.M. Rasjidi yang mengakui bahwa dalam kenyataan sejarah masyarakat adalah multi-complex yang mengandung religious pluralism, bermacam-macam agama. Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui adanya religious pluralism dalam masyarakat Indonesia.[12] Boleh dikatakan bahwa memahami pluraritas agama dan budaya merupakan bagian dari cara memahami agama secara kontekstual. Memahami agama, pada dasarnya memahami juga kebudayaan masyarakat secara menyeluruh. Dan, jika agama dipahami secara integral dengan kondisi sosial kulturalnya, pada saat itu pula akan tampak dengan sendirinya mana aspek budaya yang selaras dengan misi agama dan mana yang tidak.
Dengan kenyataan bahwa keberagamaan masyarakat Indonesia adalah pluralistis dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, maka masalah ini diakui dalam konstitusi dan telah ditegaskan adanya jaminan untuk masing-masing pemeluk agama dalam melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, kekayaan keragaman ini bila dikelola dengan baik dan posistif, maka akan menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia. Namun bisa juga menjadi bencana yang mengandung potensi konflik. Sebagai kenyataan sosial, pluralitas agama ini tak jarang menjadi problem, dimana agama di satu sisi dianggap sebagai hak pribadi yang otonom, namun di sisi lain hak ini memiliki implikasi sosial yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya (claim of truth) harus diwartakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam konteks ini, agama seringkali menjadi potensi konflik dalam kehidupan masyarakat.
Bukan saja hanya keragaman dalam beragama yang berpeluang memunculkan konflik, tetapi juga bisa terjadi karena keragaman etnis dan budaya. Perbedaan budaya menjadi sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. Misalnya, ada yang mengangguk-nganggukan kepala atau bilang ‘uh’, tepuk tangan ataupun mengedipkan mata ketika mengungkapkan perhatiannya ketika diajak bicara atau mendengarkan pidato. Dikalangan psikolog, perbedaan budaya menunjukkan perbedaan intelegensia masyarakat. Masyarakat sunda bercirikan ramah, masyarakat Bali lemah gemulai, dan lain-lain. Jika masyarakat atau seseorang memiliki kemampuan menguasai hal itu maka merupakan ciri dari tingkat intelegensianya. Sementara, manipulasi dan rekayasa kata dan angka menjadi penting dalam masyarakat Barat, maka keahlian dalam memiliki kemampuan ini menunjukkan kepada kemampuan intelegensinya.[13] Di sinilah perlunya membangun kesadaran bersama akan penghormatan terhadap keragaman identitas sosial termasuk indetitas dan ekspresi keberagamaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang budaya yang beragam itu supaya tidak terjadi fragmentasi kelompok, ketersinggungan, kesalahfahaman, dan konflik-konflik horizontal.
Dalam menyikapi keragaman budaya itu, sedikitnya ada tiga sudut pandang yang berbeda dan bahkan bisa memunculkan konflik, yaitu : 1) pandangan primordialis, dimana identitas asal sangat kental, baik itu agama, suku, adat, dll; 2) pandangan instrumentalis, dimana keragaman budaya dan identitas dijadikan alat untuk mencapai tujuan, baik materil maupun nonmateril. Pandangan ini sering digunakan oleh para politisi. Misalnya ketika meneriakkan Islam, adalah dengan maksud semua umat Islam membackupnya untuk kepentingan politiknya; dan 3) konstruktivis, yaitu keragaman budaya dan identitas dibentuk sebagai jaringan pergaulan sosial. [14] Bagi mereka, persamaan adalah anugrah sedangkan perbedaan adalah barkah. Tampaknya, yang ketiga ini terbuka ruang wacana untuk multikulturalisme dan menerima pluralitas beragama dalam membangun toleransi, egaliterian, persamaan, dan lain-lain yang bersikap inklusif. Wacana ini sudah sering dibicarakan di lingkungan akademisi, praktisi budaya, dan agamawan.
Truth Claim dan Dialog Keagamaan
Sejalan dengan pluralitas dalam beragama itu, maka yang menjadi problem paling besar dalam kehidupan beragama dewasa ini adalah “bagaimana teologi dari suatu agama (truth claim) mendefinisikan diri di tengah agama-agama lain. Semakin berkembangnya pemahaman mengenai pluralisme agama, berkembang pula suatu paham teologia religionum, yaitu suatu faham yang menekankan pentingnya dewasa ini untuk berteologi dalam konteks agama-agama, [15] tetapi pada saat yang bersamaan masih tetap terpelihara keyakinan dan kebenaran agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-tawar, apalagi berganti. Agama bukan sebagai (seperti) rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Jika seseorang memeluk keyakinan, maka keyakinan itu tidak dapat pisah darinya, ia involved dengan keyakinan agamanya.[16] Demikian pula, pemahaman pluralistis tidak sertamerta diiringi dengan keharusan pertemuan dalam masalah-masalah teologis, atau pertemuan dalam hal keimanan, namun hanya untuk memberi tempat dan pengakuan terhadap keberadaan agama-agama lain. Pandangan pluralismenya tidak sampai masuk pada perbincangan tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama lain. Ia sama sekali tidak menyinggung tentang hal itu. Sebaliknya, ia juga tidak memandang kesalahan-kesalahan ajaran teologis dari agama lain.
Berbagai pandangan dan teori dalam mempelajari dan memahami keragaman dalam beragama itu banyak ditemukan. Setidaknya, tiga pendekatan yang sering digunakan : pendekatan teologis, politis, dan sosial kultural. Untuk pendekatan kedua dan ketiga, biasanya dikelompokkan pada pendekatan teoritis.[17] Pendekatan teologis tiada lain adalah mengkaji hubungan antar agama berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing. Bagaimana doktrin-doktrin agama “menyikapi” dan “berbicara” tentang agamanya dan agama orang lain. Sedangkan pendekatan teoritis melalui analisis politis dilihat dalam konteks “kerukunan” dengan maksud untuk melihat, bagaimana masing-masing (penganut) agama memelihara ketertiban, kerukunan dan stabilitas suatu masyarakat yang multi agama. Sedangkan pendekatan kultur atau budaya adalah untuk melihat dan memahami karakteristik suatu ma-syarakat yang lebih menitikberatkan pada aspek tradisi yang berkembang dan mapan, dimana agama dihormati sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang dimiliki oleh setiap manusia atau masyarakat. Tradisi “rukun”, menjadi simbol dan sekaligus sebagai karakteristik sebuah masyarakat yang telah berjalan sejak lama dan turun temurun. Konsep “kerukunan hidup antarumat beragama”, misalnya, bisa dianalisis melalui pendekatan politis maupun kultural. Konsep itu, lebih menitik beratkan pada muatan politis dan kulturalnya ketimbang teologis, karena agama begitu nyata terlibat dalam dunia manusia yang tidak lepas dari kecenderungan politis dan kulturalnya.
Melalui kajian teologis, kita bisa memahami teks-teks masing-masing agama berkenaan dengan penyikapan agamanya dengan agama orang lain. Oleh karena itu, buku-buku yang di tulis oleh para ulama dan cendekiawan agama berkenaan dengan penyikapan agama masing-masing itu, sangat membantu kita dalam memahami doktrin-doktrin agama berkenaan dengan hubungan antar agama. Apakah aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan, dari pandangan politis, kita bisa melihat dari ideologi sebuah masyarakat atau negara yang dimilikinya. Ideologi ini sangat mempengaruhi terhadap hubungan masing-masing agama. Pada sebuah negara yang bertipe “demokratis” (umumnya di Barat), misalnya, maka hubungan antar agama akan bersipat demokratis pula, tetapi lebih memiliki kecenderungan bahwa agama itu hanya milik individu dan bersipat internal. Sebaliknya, pada sebuah masyarakat yang tidak atau semi demokratis (umumnya di Timur), cenderung sosok agama bersipat eksklusif, masing-masing umat beragama ingin menampakkan dan menonjolkan agamanya sebagai satu-satunya sumber semua aspek kehidupan manusia, tetapi sulit diwujudkan dalam praktek-praktek berbangsa dan bernegara, karena berbenturan dengan agama-agama lain dan tradisi atau budaya lainnya yang telah berkembang cukup lama.
Demikian juga, banyak teori yang telah diajukan oleh para agamawan (juga cendekiawan) di Indonesia berkaitan dengan toleransi beragama, tetapi bila disederhanakan meliputi dua hal, yaitu : pertama, dari sisi ‘konsep kerukunan’, yakni pemaparan teologis masing-masing agama; dan kedua, pada aspek ‘dialog’ antar cendekiawan yang diwujudkan dalam bentuk hubungan antar lembaga formal. Tetapi, hubungan antar lembaga formal ini baru bersipat seremonial, belum pada tataran konsepsional. Munculnya “orde reformasi”, menampakkan kelemahan pada konsep kerukunan umat beragama yang sudah di buat dan dipublikasikan. Ternyata, konsep itu bisa berjalan lebih bersipat pendekatan “keamanan” dibandingkan “kesadaran”. Maka, secara praktis, dialog keagamaan harus berangkat dari kesadaran beragama. Sebab, kesadaran beragama lahir dari pengetahuan dan pengalaman beragama.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap agama memiliki kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif oleh setiap pemeluk agama. Ia tidak lagi utuh dan absolut. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknai dan dibahasakan. Sebab keperbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang yang diambil peyakin – dari konsepsi ideal turun ke bentuk-bentuk normatif yang bersipat kultural. Dan ini yang biasanya di gugat oleh berbagai gerakan keagamaan (harakah) pada umumnya. Sebab mereka mengklaim telah memahami, memiliki, dan bahkan menjalankan secara murni dan konsekuen nilai-nilai suci itu. Keyakinan tersebut menjadi legitimasi dari semua perilaku pemaksaan konsep-konsep gerakannya kepada manusia lain yang berbeda keyakinan dan pemahaman dengan mereka. Armahedi Mahzar menyebutkan bahwa absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstrimise, dan agresivisme adalah “penyakit” yang biasanya menghinggapi aktifis gerakan keagaman. Absolutisme adalah kesombongan intelektual; ekslusivisme adalah kesombongan sosial; fanatisme adalah kesombongan emosional; ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap; dan agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik. Tiga penyakit pertama adalah wakil resmi kesombongan (‘ujub). Dua penyakit terakhir adalah wakil resmi sipat berlebih-lebihan.[18]
Dalam konteks kehidupan beragama yang pluralistis sebagaimana tersebut di atas, maka untuk memelihara keragaman keyakinan beragama dalam konteks kerukunan, diperlukan suasana saling pengertian dan saling menghormati di antara berbagai penganut agama. Salah satu cara untuk sampai pada suasana “rukun”, saling pengertian dan menghormati itu adalah melalui upaya memahami doktrin yang berkaitan dengan prinsip-prinsip beragama dengan keyakinan agama yang berbeda. Masing-masing agama, khususnya Islam memiliki prinsip-prinsip dasar ini. Di samping toleransi dalam beragama ini merujuk pada norma-norma masing-masing agama, juga, bisa berasal dari pengalaman-pengalaman pribadi manusia beragama, baik pengalaman langsung maupun pengalaman atas dasar memahami fenomena beragama. Untuk itu, bagi umat beragama diperlukan :
1. Keyakinan yang kuat yang didasarkan atas pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang agamanya. Di sini, agama (doktrin) memberikan rambu-rambu yang jelas dan tegas, bagaimana bergaul secara komunikatif, toleran, dan saling menghormati diantara para pemeluk agama;
2. Minimal memiliki pengetahuan standar tentang ajaran (doktrin) agama orang lain yang berbeda dengan kita dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Cara ini dimaksudkan untuk menghindari ketersinggungan, kesalahfahaman dan penilaian yang salah tentang (doktrin) agama mereka.
3. Memahami karakteristik budaya, tradisi, dan kesukuan yang beragam sebagai kunci utama dalam memasuki pergaulan sosial.
4. Kontinyuitas dialog antar pemuka dan tokoh agama lebih intens. Cara ini dilakukan mengingat di mata sebagian besar umat beragama, bahwa kredibilitas ketokohan agama tetap tinggi dan terpelihara untuk membimbing dan menyelesaikan persoalan-persoalan internal dan eksternal kehidupan beragama.
5. Peran pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik formal maupun nonformal dalam menanamkan nilai-nilai kerukunan, toleransi, solidaritas, dan saling menghormati antar kepenganutan yang berbeda sangatlah besar. Oleh karena itu, pengetahuan tentang “rukun” bukan hanya berasal dari kultur lokal saja, tetapi jauh lebih penting adalah dari doktrin agama yang mengajarkan dan memberi kesadaran kemanusiaannya.
Lima langkah di atas bukanlah jaminan mutlak yang serta merta kerukunan antar umat beragama bisa langsung tercapai. Sebab, masalah keyakinan adalah masalah “pribadional”. Kita memang sulit melepaskan kerangka (frame) subyektivitas ketika keyakinan pribadi berhadapan dengan keyakinan lain yang berbeda. Sekalipun ada yang berpendapat bahwa kerangkan subyektif adalah cermin eksistensi yang alamiah. Lagi pula, setiap manusia mustahil menempatkan dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain dalam hatinya. Dengan begitu, kita tidak harus memaksakan inklusivisme “gaya kita” pada orang lain, yang menurut kita eksklusif. Sebab, bila hal ini terjadi, pemahaman kita pun sebenarnya masih terkungkung pada jeratjerat eksklusivisme, tetapi dengan menggunakan nama inklusivisme.
Dari sisi lain, yang nampak ke permukaan adalah, bahwa terjadinya konflik antar agama muncul bisa sebagai akibat kesenjangan ekonomi (kesejahteraan), perbedaan kepentingan politik, ataupun perbedaan etnis. Akhirnya konsep kebenaran dan kebaikan yang berakar dari ideologi politik atau wahyu Tuhan sering menjadi alasan pembenar penindasan kemanusia-an. Hal ini pun bisa terjadi ketika kepentingan pembagunan dan eko-nomi atas nama kepentingan umum sering menjadi pembenar tindak kekerasan. Ditambah pula dengan klaim kebenaran (truth claim) dan watak misioner dari setiap agama, peluang terjadinya benturan dan kesalah pengertian antar penganut agama pun terbuka lebar, sehingga menyebabkan re-taknya hubungan antar umat ber-agama. Untuk hubungan eksternal agama-agama, maka penting dilakukan dialog antar agama. Sedangkan untuk internal agama, diperlukan reinterpretasi pesan-pesan agama yang lebih menyentuh kemanusiaan yang universali. Dalam hal ini, peran para tokoh agama lebih dikedepankan.[19]
Oleh karena itu, dialog kerukunan dalam beragama’, atau kepenganutan agama dalam konteks pluralisme keyakinan agama menjadi sangat penting untuk dipahami, diluruskan, dan ditindaklanjuti dalam aktifitas kehidupan beragama, sehingga secara esensial dapat diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh para penganut agama ketika bersinggungan dan berhadapan dengan para penganut yang berbeda keyakinan. Dialog menjadi salah satu media penting bagi terwujudnya keharmonisan antaragama, karena berpijak dari nilai akademis (intelektual), pengalaman dan kesadaran dalam beragama.
Peran Pendidikan Agama (Islam)
Sejalan dengan perkembangan kehidupan beragama dan poin ke-5 (lima) langkah-langkah kerukunan di atas itu, karena persoalan pluralitas beragama di Indonesia menjadi tantangan, maka harus direspon oleh semua elemen bangsa ini, termasuk didalamnya dunia pendidikan (Islam). Sebagai sebuah proses, maka pendidikan sangat berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Berdasarkan konsep pendidikan ini, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau “enculturation”, suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu masyarakat tertentu dengan keragaman budaya dan keyakinan. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka praktek pendidikan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebab praktek pendidikan harus mendasarkan pada teori-teori pendidikan dan giliran berikutnya teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Maka tidaklah heran kalau pendidikan bisa dipandang sebagai simbol peradaban, bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut.[20]
Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong atau penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa Pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun proses-proses pembedayaanya. Maka maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana Pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut. Kemajuan, peradaban yang dicapai umat manusia dewasa ini, sudah tentu tidak terlepas dari peran-peran pendidikannya. Diraihnya kemajuan ilmu dan teknologi yang dicapai bangsa-bangsa diberbagai belahan bumi ini, telah merupakan akses produk suatu pendidikan, sekalipun diketahui bahwa kemajuan yang dicapai dunia pendidikan selalu dibawah kemajuan yang dicapai dunia industri yang memakai produk lembaga pendidikan.[21]
Pendidikan agama Islam, misalnya, tidak dapat dipahami sebatas ‘pengajaran agama’, juga, parameter keberhasilan pendidikan agama tidak cukup diukur hanya dari segi seberapa jauh anak menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang ajaran agama atau ritus-ritus keagamaan semata. Lebih-lebih penilaian yang diberikan melalui ‘angka-angka’ yang didasarkan pada seberapa siswa didik menguasai materi sesuai dengan buku ajar. Justru penekanan yang lebih penting adalah seberapa dalam tertanamnya nilai-nilai keagamaan tersebut dalam jiwa dan seberapa dalam pula nilai-nilai tersebut terwujud dalam tingkah laku dan budi pekerti siswa didik sehari-hari. Wujud nyata nilai-nilai tersebut dalam tingkah laku dan budi pekerti sehari-hari akan melahirkan budi luhur (akhlakul karimah). Karena itu pendidikan agama adalah pendidikan untuk pertumbuhan total seorang manusia. Seyyed Hossein Nasr, menegaskan bahwa pendidikan agama (Islam) musti berkepedulian dengan seluruh manusia untuk dididik. Tujuannya bukan hanya melatih pikiran, melainkan juga melatih seluruh wujud pribadi. Itulah yang menyebabkan mengapa pendidikan agama (Islam) bukan hanya menyampaikan pengetahuan (al-Ta’lim), tetapi juga melatih seluruh diri siswa (al-Tarbiyah). Fungsi guru bukan sekedar seorang muallim, penyampai pengetahuan, tetapi juga seorang murabbi, pelatih jiwa dan kepribadian.[22]
Upaya membangun pendidikan Islam berwawasan global yang ditandai dengan keragaman budaya dan agama itu memang bukan persoalan mudah, karena pada waktu bersamaan pendidikan Islam harus memiliki kewajiban untuk melestarikan, menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dan dipihak lain berusaha untuk menanamkan karakter budaya nasional Indonesia dan budaya global. Tetapi, upaya untuk membangun pendidikan Islam yang berwawasan global dan keragaman agama itu dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana dan strategis. Misalnya saja, bangsa Jepang tetap merupakan satu contoh bangsa yang mengglobal dengan tanpa kehilangan karakternya sebagai suatu bangsa yang maju dengan tetap kental dengan nilai-nilai religius. Dengan contoh bangsa Jepang, maka pembinaan dan pembentukan nilai-nilai Islam tetap relevan, bahkan tetap dibutuhkan dan harus dilakukan sebagai “kapital spiritual” untuk masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global menuju masyarakat madani Indonesia. Dari pandangan ini, tergambar bahwa peran pendidikan sangatlah sentral dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa “system sosial, politik, dan ekonomi bangsa selalu menjadi penentu dalam penetapan dan pengembangan peran pendidikan.[23]
Perbedaan budaya, agama, aspirasi poltik, kepentingan, visi, dan misi, keyakinan dan tradisi merupakan sebuah konduksi dalam hubungan Interpersonal yang kadang-kadang juga menjadi perbedaan perilaku dalam memahami sesuatu. Maka dapat dikatakan berbagai kekisruan etnis yang merebak dibanyak tempat di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, bagian dari krisis multi dimensi yang dihadapi Negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 pada masa akhirnya rezim orde baru merupakan akibat dari rendahnya kesadaran dan wawasan multikulturalisme.[24] Program pendidikan bagaimanakah yang relevan dengan kehidupan masyarakat dan bangsa dengan corak masyarakat majemuk ini dengan berbagai etnis, suku bangsa dan agama yang ada didalamnya. Sebab masing-masing etnis, suku bangsa dan agama tadimembawa kultur sendiri-sendiri dan keagamaan ini tentu menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia adalah masyarakat multicultural. Oleh karenanya, pengakuan akan keragaman etnis, suku dan budaya penting ditumbuhkan pada peserta didik, karena para pendiri bangsa ini sesungguhnya telah menempatkan ideology multicultural sebagai dasar kehidupan bernegara dan berkebangsaan yaitu “Bhineka Tunggal Ika”. Dalam ideology multicultural perbedaan dalam kesederajatan tentu diakui dan diagungkan, baik secara individual atau kelompok maupun secara kebudayaan. Sayangnya, penghargaan terhadap perbedaan dalam kesederajatan ini nyaris tidak pernah ditumbuhkembangkan terutama selama lebih dari 32 Tahun masa pemerintahan Orde Baru. Selama kurun waktu itu, konsep pendidikan selalu seragam dan selalu merupakan upaya atau berkarakteristik penyeragaman budaya.
Atas dasar itulah, dalam konteks pluralitas beragama dan keragaman budaya bangsa Indonesia itu, maka mengembangkan sikap pluralisme pada peserta didik adalah mutlak segera “dilakukan” oleh seluruh pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikanya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kolompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eklusifisme kelompok agama dan budaya yang sempit. Sehingga sikap-sikap pluralisme itu akan dapat ditumbuhkembangkan dalam diri generasi muda kita melalui dimensi-dimensi pendidikan agama, sehingga mereka tahu dan sadar atas kemanusiaanya. Oleh karena itulah, Islam mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan untuk mengatur hubungan antar manusia ini. Prinsip-prinsip itu antara lain :
Pertama, Islam pada essensinya memandang manusia dan kemanusian secara sangat positif dan optimis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama, keturunan Adam dan Hawa. Tetapi kemudian manusia menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum atau berbangsa-bangsa lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan ini mendorong manusiauntuk saling kenal-mengenal dan membutuhkan apresiasi dan repek satu sama lain. Dalam pandangan Islam, perbedaan itu, bukanlah warna kulit dan bangsa, tetapi hanyalah tergantung pada tingkat ketaqwaan masing-masing.[25] Inilah yang menjadi dasar perspektif Islam tentang “kesatuan umat manusia” (Universal humanity), yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya solidaritas antar manusia (ukhuwah insaniyah). [26]
Kedua, dalam perspektif Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). Dengan fitrahnya setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan dan memahami dkebenaran, yang pada gilirannya akan membuatnya mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran tersebut. Kemampuan dan kecenderungan inilah disebut sebagai sikap “hanif”.[27] Atas dasar prinsip ini, Islam menegaskan prinsipnya bahwa setiap manusia adalah homo religius. Di dalam Al-qur’an, manusia hanif itu diidentifikasikan dengan nabi Ibrahim yang dalam pencarian kebenaran yang pada akhirnya menemukan Tuhan sejati.[28] Ibrahim dipandang sebagai tiga panutan agama, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, sehingga dikalangan para penstudiagama-agama dikenal sebagai “agama Ibrahim” (Abrahamic Religions).[29]
—————————–
Daftar Rujukan
Komarudin Hidayat : “Agama Untuk Kemanusiaan”, dalam Andito (ed), Atas Nama Agama, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998
Joachim Wach, the Comparative Study of Religions, Diedit dan diberi pengantar oleh Joseph M. Kitagawa, Columbia University Press, New York, 1958; Edisi Indonesia diterbitkan oleh Rajawali, Jakarta, 1984.
Taufik Abdullah & Rusli Karim, ed, Metodologi Penelitian Agama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990
Ahmad Norma Permata (ed), Metodologi Studi Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
F.J. Moreno, Agama Dan Akal Fikiran, terjemahan, Rajawali, Jakarta, 1985
Roland Robertson, Sosiologi Agama, terjemahan, Tonis, Bandung, 1985
Mircea Eliade, (ed), Encyclopaedia of Religion, vol.12, MacMillan Publishing Company, 1987
Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Paramadina, Jakarta, 2001
Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, Jakarta, 1995
M. Rasjidi, Al-Djami’ah, Nomor Khusus, Mei 1968 Tahun ke VIII
Muhaemin el-Ma’hady, “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (sebuah kajian awal)”, dalam www.komunitasdemokrasi.or.id; 3 Nopember 2008
Budhy Munawar Rachman : “Resolusi Konflik Agama Dan Masalah Klaim kebenaran”, salah satu kumpulan tulisan yang terdapat dalam buku berjudul : Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana Mult-kultural Dalam Media, Sandra Kartika dan M. Mahendra (editor), Lembaga Studi Pers & Pembangunan, Jakarta, 1999
Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama, Pustaka Setia, Bandung, 2005
_______________, Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama, Pustaka Setia Bandung, 2004
_______________,(ed), Otonomi Pendidikan, Lembaga Penelitian UIN SGD Bandung, 2008; Sumber diambil dari tulisan Hujair Sanaky, “Paradigma Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi Antara Mitos dan Realitas”, www.sanaky.com; September 2006.
Armahedi Mahzar dalam pengantar untuk terjemahan R. Garaudy, Islam Fundamentalis dan Fundamen-talis lainnya, Pustaka, Bandung, 1993
Abdul Halim F, “Pendidikan :Simbol Peradaban”; Sumber : http://www.penulislepas.com; 16 april 2008
http://qastalany.wordpress.com/2007/09/22/paradigma-pendidikan-islam/ – _ftn3.
Syamsul Ma’arif, “Islam dan Pendidikan Pluralisme, Menampilkan Wajah Islam Toleran melalui Kurikulum PAI berbasis Kemajemukan”, Makalah yang disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam, Lembang Bandung, 26-30 Nopember 2006
Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Adicita, Yogyakarta, 2001
Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam, Paramadina, Jakarta, 1999
[1] Komarudin Hidayat : “Agama Untuk Kemanusiaan”, dalam Andito (ed), Atas Nama Agama, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hal. 41 dan 42
[2] Lihat, Joachim Wach, the Comparative Study of Religions, Diedit dan diberi pengantar oleh Joseph M. Kitagawa, Columbia University Press, New York, 1958, hal. 55. Edisi Indonesia diterbitkan oleh Rajawali, Jakarta, 1984.
[3] Taufik Abdullah & Rusli Karim, ed, Metodologi Penelitian Agama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990, hal. xiii
[4] Lihat; Fredrich Heiler : “Studi Agama Sebagai Persiapan Kerja Sama Antaragama”, dalam Ahmad Norma Permata (ed), Metodologi Studi Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 232
[5] F.J. Moreno, Agama Dan Akal Fikiran, terjemahan, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 122
[6] Roland Robertson, Sosiologi Agama, terjemahan, Tonis, Bandung, 1985, hal. vi
[7] Lihat Mircea Eliade, (ed), Encyclopaedia of Religion, vol.12, MacMillan Publishing Company, 1987, hal.331
[8] Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Paramadina, Jakarta, 2001, hal. 31
[9] Ibid.
[10] Ramundo Pannikar, “Dialog Yang Dialogis”, dalam Ahmad Norma Permata (ed), Op.Cit, hal. 199
[11] Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, Jakarta, 1995
[12] M. Rasjidi, Al-Djami’ah, Nomor Khusus, Mei 1968 Tahun ke VIII, hlm.35
[13] Lihat, Muhaemin el-Ma’hady, “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (sebuah kajian awal)”, dalam www.komunitasdemokrasi.or.id; 3 Nopember 2008
[14] Ibid
[15] Lihat; Budhy Munawar Rachman : “Resolusi Konflik Agama Dan Masalah Klaim kebenaran”, salah satu kumpulan tulisan yang terdapat dalam buku berjudul : Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana Mult-kultural Dalam Media, Sandra Kartika dan M. Mahendra (editor), Lembaga Studi Pers & Pembangunan, Jakarta, 1999, hal. 129-130
[16] M.Rasyidi, Loc.Cit
[17] Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hal. 22-23
[18] Armahedi Mahzar dalam pengantar untuk terjemahan R. Garaudy, Islam Fundamentalis dan Fundamen-talis lainnya, Pustaka, Bandung, 1993, hal.ix
[19] Adeng Muchtar Ghazali, Op.Cit, hal. 25
[20] Abdul Halim F, “Pendidikan :Simbol Peradaban”; Sumber : http://www.penulislepas.com; 16 april 2008
[22] Syamsul Ma’arif, “Islam dan Pendidikan Pluralisme, Menampilkan Wajah Islam Toleran melalui Kurikulum PAI berbasis Kemajemukan”, Makalah yang disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam, Lembang Bandung, 26-30 Nopember 2006
[23] Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Adicita, Yogyakarta, 2001, hlm.6.
[24] Adeng Muchtar Ghazali (ed), Otonomi Pendidikan, Lembaga Penelitian UIN SGD Bandung, 2008, hal. 1-7, diambil dari tulisan Hujair Sanaky, “Paradigma Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi Antara Mitos dan Realitas”, www.sanaky.com; September 2006.
[25] Lihat, Q.S.49:13
[26] Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam, Paramadina, Jakarta, 1999, hal. 32
[27] Lihat, Q.S.30:30
[28] Azyumardi, Op.Cit, hal. 33
[29] Penjelasan luas tentang Agama Ibrahim ini, bisa di lihat dalam buku, Adeng Muchtar Ghazali, Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama, Pustaka Setia Bandung, 2004, hal. 69-90