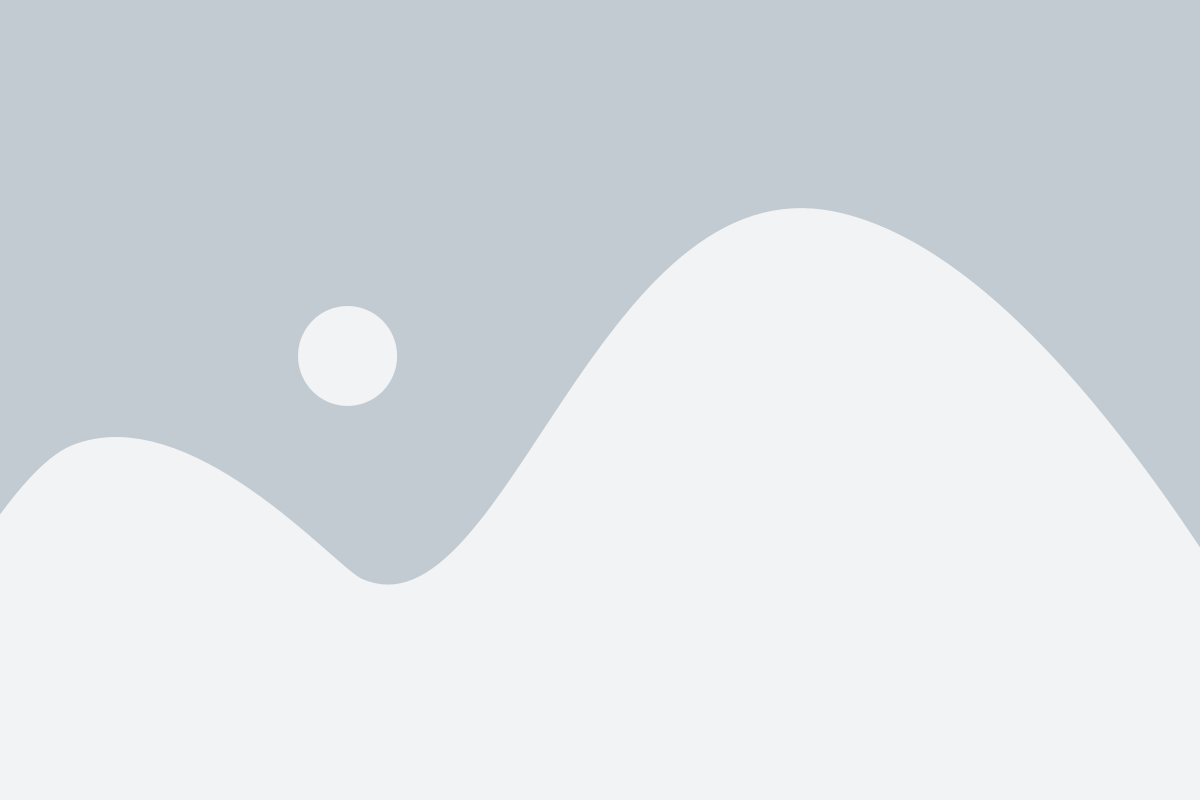Arogansi antar lembaga dan kelompok tengah dipentaskan dengan vulgar di media massa. Kepongahan individu ditampilkan tanpa rasa malu di media sosial. Santun, rendah hati dan peduli sesama mulai menjadi perilaku langka.
Kini tak ada bedanya antara intelektual dan pejabat publik yang berpendidikan tinggi dengan selebriti. Berbicara seenak perut, tanpa kesantunan. Ruang publik telah dipenuhi oleh sampah kata-kata dari kebun binatang. Akibatnya meluaslah kegersangan sosial.
Apa pangkal sebab utamanya? Perlu riset mendalam untuk menjawabnya. Namun dapat diajukan beberapa hipotesa sederhana tentang variabel penyebab mengapa hal ini terjadi. Pertama, lemahnya peran keluarga. Ayah dan ibu karena kesibukannya masing-masing, lebih banyak menyerahkan pendidikannya kepada orang tua ideologis (televisi). Rumah hanya tempat untuk makan dan tidur saja, kurang kehangatan dan kasih sayang, penyemaian nilai-nilai mulia dan keteladanan. Ayah dan ibu hanya menjadi orangtua biologis.
Kedua, secara sosial terjadi krisis keteladanan. Di masyarakat, para elit politik lebih senang rebutan kekuasaan, menonjolkan pencitraan dan menyampaikan statemen penuh sangkaan. Masih lekat dalam ingatan, sebutan “rakyat tak jelas” dari salah satu menteri pemerintahan Jokowi-JK. Paling hangat, saling tuding tentang mafia anggaran antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta.
Ketiga, media massa baik elektronik maupun cetak bahkan media sosial dengan sangat terbuka setiap harinya menyajikan tentang ketidakadilan. Rasanya sudah sangat eneg dan mual menontonnya. Jika begal dibakar hidup-hidup, berbanding terbalik dengan begal uang rakyat. Bilapun telah ditangkap, masih bisa mengajukan keringanan hukum, bersolek dengan gagah dan cantiknya di pengadilan. Masih dapat tersenyum di hadapan wartawan, menolak untuk diperiksa bahkan bisa bebas karena menyuap para pengadil. Mencabik-cabik rasa keadilan dan itu menjadi endapan kebencian dan kesumat yang melahirkan pembangkangan.
Keempat, sekolah sebagai tempat disemai dan dipupuknya sikap rendah hati, santun dan peduli agar tumbuh subur, mulai kehilangan perannya. Sekolah lebih mirip “pabrikan prestasi dengan parameter intelligence quotient (IQ)” semata, dibandingkan budi pekerti. Kurikulum 2013 yang diharapkan menjawab kekeringan moralitas malah harus layu sebelum berkembang. Semoga saja ada ikhtiar serius dari pemerintah untuk segera menerapkannya dengan merata. Tentu saja, sekolahnya harus siap, sementara faktanya, ketimpangan fasilitas dan kualitas guru menjadi problem utamanya.
Kelima, masyarakat Indonesia sebagian besarnya tengah sakit, mengalami alienasi. Tingkat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan masih mengkhawatirkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 melansir, indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia sebesar 68,28. Angka ini menegaskan masih banyak yang kurang bahagia. Ketidakpastian dan mahalnya kebutuhan hidup menjadikan setiap orang tak peduli. Jangan aneh, sangat jarang pengendara di jalan raya yang mau berhenti memberi kesempatan kepada penyeberang jalan. Semuanya buru-buru, mengejar waktu, sementara untuk keselamatan orang lain, tak peduli. Fakta nyata tentang arogansi yang tumbuh subur setiap hari.
Manusia menjadi mesin dari industri. Berangkat pagi, pulang malam, namun tetap saja masih miskin. Perguruan tinggi hanya memproduksi sarjana dengan minim kompetensi. Menjadi sarjana bahkan doktor sekalipun belum tentu mendapatkan pekerjaan layak. Dihinggapi alienasi, manusia jauh dari eksistensi diri.
Keenam, agama diajarkan dengan formal jauh dari esensi. Ustad banyak yang mirip selebriti, memasang tarif tertentu untuk setiap ceramah yang disampaikannya. Sementara ulama, ustad, kiai dan guru ngaji yang ihlas semakin kehilangan murid (santri), karena telah digantikan oleh guru yang ada di televisi, internet dan perangkat multimedia yang dengan mudah dan murah dapat dibeli. “Muslim tanpa mesjid” begitu almarhum Kuntowijoyo menggambarkan model belajar generasi muda Muslim saat ini. Akibatnya, hanya pengetahuan yang tersampaikan, tanpa akhlaq, iman dan ihsan.
Ketujuh, hidup di era postmodern dengan identitas budaya yang semakin kabur. Anak muda bahkan remaja, telah menjadi bagian dari komunitas global, kepribadiannya dibentuk oleh teknologi digital. Bayangkan saja, usia dua bahkan satu tahun saja sudah akrab dengan telepon genggam atau bahkan smartphone. Remaja seperti ini disebut Dan Pankraz dengan istilah Gen-C. C yang berarti connected (terhubung), digital creative, curiosity (ingin tahu), customize (menyesuaikan) cyber, dan chameleon (bunglon). Terkoneksi dalam kebudayaan global, hidup bersama di desa buana (global village).
Identitas dan ekspresi diri terlihat dari pola konsumsi. Konsumsi yang digambarkan Peter York dalam bukunya yang berjudul “Style Wars” menunjukkan makna, status, walau terkesan banyak gaya, citra dan pilihan. Semuanya permainan simbolik dengan makna yang boleh jadi dangkal. Seperti sebagian selebritis yang bersalinrupa, memakai hijab ketika bulan ramadlan, namun setelah selesai bulan suci tersebut, kembali mengumbar aurat.
Kegersangan Sosial
Kegersangan sosial ditandai oleh kurang hangatnya interaksi, rendahnya sensitivitas dan kesantunan kepada sesama. Tidak ada ikatan yang menguatkan antar warga masyarakat. Jika dibiarkan, lingkungan sosialnya akan rusak. Ketidaknyamanan, ketidakamanan dan ketidaktertiban bahkan konflik hanya menunggu waktu saja untuk terjadi.
Lingkungan sosial sehat didukung oleh sistem pranata sosial, dimana di dalamnya ada nilai dan norma, pola prilaku serta sistem hubungan sosial yang berkualitas. Kegersangan sosial hanya mungkin disejukkan dengan menata kembali norma dan nilai sosial yang rusak. Nilai agama dan tradisi harus dikuatkan serta dikembangkan dalam kerangka sikap saling menghargai satu sama lain. Semuanya harus menahan diri, kuatkan keyakinan namun pada saat bersamaan klaim kebenaran agama jangan menjadikan kita melecehkan keyakinan agama lain, karena itu akan menjadikan keberagamaan sebagai faktor penyebab konflik.
Sementara dalam pola prilaku sosial, ruang publik yang terbuka dan menyenangkan harus diperbanyak, sehingga tercipta proses interaksi sosial yang hangat. Boleh jadi di ruang publik seperti taman lah, awalnya warga masyarakat tidak saling mengenal, kemudian akrab dan menguatkan persaudaraan. Warga yang sibuk dan stress selama hari kerja, direlaksasikan dengan taman bermain dan area publik yang menyenangkan. Jangan biarkan warga menikmati hiburan di tempat-tempat yang minim interaksi sosial.
Lingkungan sosial sehat juga ditandai dengan penggunaan bahasa dalam interaksi sosial yang santun. Bahasa itu simbol, mencerminkan pengetahuan, sikap dan kebudayaan. Kedamaian, sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain hanya mungkin tercipta, apabila bahasa santun dipergunakan. Berbeda pendapat itu harus, agar ada ruang wacana untuk meninjau persoalan dari ragam perspektif. Namun tentu sampaikanlah perbedaan pandangan itu dengan bijak. Wallâhu’alam.[]
Iu Rusliana, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, aktif di Mien R Uno Foundation Jakarta.
Sumber, Pikiran Rakyat 13 Maret 2015.