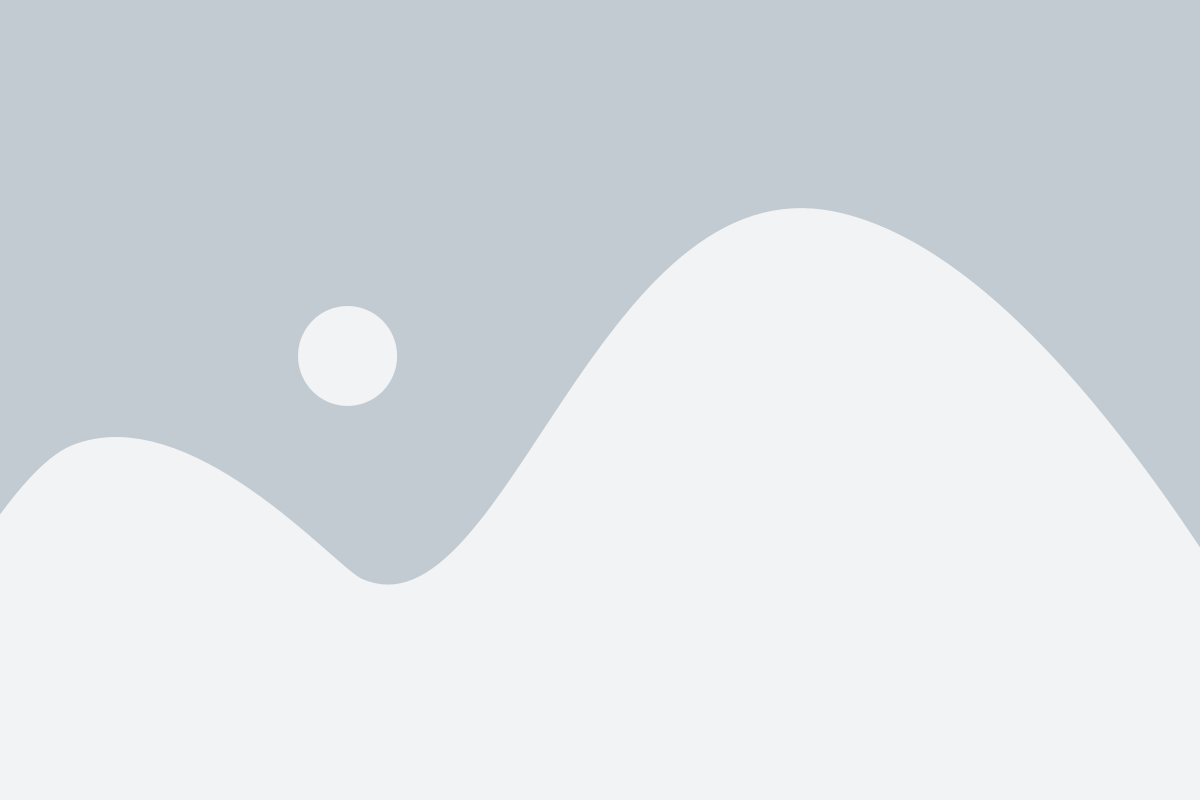Hijrah itu dalam sosiologi disebut transformasi, perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Transformasi kaitannya dengan sikap mental yang kemudian ditautkan dengan dinamika sosiokultural. Demikian juga hijrah interaksi maknanya bukan sekadar mental, melainkan juga pergerakan fisikgeografis. Dalam konteks kenabian, migrasi dari Mekah ke Madinah.
Peristiwa itulah yang kemudian dijadikan titik pijak perhitungan kalender Islam. Haikal mencatat hijrah nabi sebagai `pembuka pintu baru dalam kehidupan politik’.
Fazrul Rahman, Guru Besar Pemikiran Islam di Universitas Chicago, menyebutnya sebagai marks of the beginning of Islamic calendar and the founding of Islamic community (1984).
Dalam catatan Nurcholis Madjid (1993), peristiwa hijrah di samping bersifat metafisis sebagai perintah Tuhan juga merupakan lambang peristiwa kesejarahan karena dampaknya yang demikian besar dan dahsyat pada perubahan sejarah seluruh umat manusia. Kalau sebuah buku yang membahas tokoh-tokoh umat manusia sepanjang sejarah menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai yang terbesar dan paling berpengaruh daripada sekalian tokoh, bukti dan alasan penilaian dan pilihan itu antara lain didasarkan kepada dampak kehadiran nabi dan agama Islam, yang momentum kemenangannya terjadi karena peristiwa hijrah. Hijrah menjadi turning point (titik balik) untuk membentuk masyarakat yang berperadaban. Upacara hijrah Hijrah sebagai awal tahun baru Islam diperingati dengan serangkaian upacara. Tentu maksud utamanya tidak lain sebagai media menginjeksikan ingatan-ingatan tentang nilai kejuangan. Tentang sebuah epos dalam fragmen sejarah kenabian yang telah mencapai puncak-puncak keadaban itu.
Ingatan masa silam itu penting terus diulang walaupun teks narasinya sering didengar, minimal agar tidak lekas lupa akan sebuah peristiwa.
Secara ontologis, majunya sebuah bangsa mensyaratkan daya ingat yang kuat terhadap `masa silamnya’. Kemudian masa silam itu pada gilirannya menjadi energi yang terus menggerakkan elan vitalnya hari ini dan masa depan. Kata Bung Karno, `jasmerah’ (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah).
Eliade pernah mencatat, `Orang akan menyusun kembali waktu yang menakjubkan masa lalu itu untuk menyusun waktu yang tidak kalah menakjubkan untuk masa depan’. Peradaban Barat selalu mengklaim sebagai ahli waris peradaban Yunani; Rumania mengidentifikasi sebagai titisan Romawi; atau dalam ukuran yang lebih personal lagi mengapa raja-raja dan para penguasa merasa wajib merangkai silsilah mereka kembali kepada zaman Majapahit atau Mataram. Yang selalu disuntikkan para elite Yahudi untuk merawat daya hidupnya ialah masa teologi pada masa lampau; sejarah bahwa mereka ialah umat terpilih yang diberi tugas suci melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Adanya jalinan yang erat antara orang-orang Yahudi dan Israel yang sangat mistis-auratis dan historis realistis.
Itu juga yang menjadi alasan utama setiap kitab a suci begitu bersemangat s mengungkap cerita silam sambil dibubuhi di ujung ayatnya sebuah ungkapan, `Sungguh dalam fragmen-fragmen sejarah itu terdapat pelajaran bagi mereka yang menggunakan nalarnya’.
Menghidupkan memori hijrah ialah menghidupkan narasi spirit masa lampau.
Tentang bentangan perjalanan menegangkan Muhammad SAW yang ditemani seorang kawannya di tengah padang pasir menempuh jarak ratusan kilometer dari tanah kelahiran yang dicintainya, Mekah, menuju tempat asing sebuah kampung Yastrib yang kelak beralih nama menjadi Madinah.
Masa lampau yang mencatat buah dari hijrah itu; menampilkan Islam dalam wajah yang utuh. Islam yang bukan sekadar gerakan kultural, melainkan juga sekaligus struktural.
Tidak sebatas agama yang mengurus ihwal urusan personal, tapi juga menjadi pilar bagi sistem sosial seperti diterapkan di Madinah.
Di Madinah, Nabi membuktikan bahwa ketika Islam menjadi kekuatan negara jadi kekuatan negara (masyarakat), kelompok yang berbeda haluan budaya bahkan keyakinan mendapatkan perlindungan. Tata kelola pemerintahan yang benar dirumuskan, dijangkarkan di atas prinsip keterbukaan (openness), empati (empathy), kepositifan (positiveness), dan kesetaraan (equality). Dinamika sosial Nampaknya sudah menjadi ketentuan sejarah bahwa perubahan sosial yang dahsyat sebelumnya selalu mengandaikan terlebih dahulu hadirnya hijrah. Bukan hanya dialami oleh Muhammad SAW, melainkan juga nabi-nabi sebelumnya. Hijrah sebagai sunatullah dalam rangka menyongsong fajar peradaban baru yang menghadirkan harapan sekaligus mengejawantahkan mimpi-mimpi tentang kehidupan yang lebih bagus.
Tentu tema utama perubahan yang diusung para nabi harus berangkat dari visi keagamaan. Dari spiritualisme yang menjadi landasan dasar fungsi profetiknya. Kalau merujuk pada The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism Max Weber (18641920), agamalah yang berjasa melahirkan perubahan sosial yang paling spektakuler dalam peradaban manusia. Agama tidak saja menjanjikan surga, tapi pada saat yang sama menyuntikkan kesadaran tentang perlunya sebuah tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan etika.
Di sinilah nilai penting tafsir ulang ajaran agama, agar agama dapat terus beradaptasi dengan kehidupan. Perubahan sosial sebagai spirit utama hijrah harus kita maknai sebagai upaya revitalisasi teks agama agar kehadirannya membawa berkah bagi semesta. Tafsir agama harus terus disegarkan kembali seiring dengan pergeseran dinamika sosial tanpa menghilangkan elan vital nilai-nilai universalnya. Agama terus berdialektika dengan manusia dan kompleksitas persoalan kemanusiaan bahkan secara `ekstrem’. Karen Amstrong menggunakan idiom Tuhan (god) dalam A History of God untuk perubahan itu.
Tuhan (atau pemahaman masyarakat tentang tuhan) terus `berevolu si’. Kita simak pembacaan Karen Amstrong tentang realitas agama (Tuhan) kaitannya dengan perubahan sosial di dunia muslim.
Kaum muslim tidak mempunyai banyak waktu atau energi untuk mengembangkan pemahaman tradisional mereka tentang Tuhan. Mereka sibuk dalam upaya mengejar ketertinggalan dari Barat. Di Barat, `Tuhan’ dipandang sebagai suara keterasingan; di dunia Islam suara tersebut berasal dari proses kolonial. Karena tercerabut dari akar budaya sendiri, orangorang merasa kehilangan arah dan putus asa.
Sebagian pembaharu muslim berupaya mempercepat langkah kemajuan dengan cara paksa meletakkan Islam pada posisi minor’.
Dalam melakukan perubahan sosial, seperti pernah diidentifikasi Nurcholis Madjid, ada banyak hal yang harus diperhatikan karena besarnya krisis akibat perubahan sosial yang ada di sekitar: 1) deprivasi relatif, yaitu perasaan teringkari; 2) dislokasi, yaitu perasaan tidak punya tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang; 3) disorientasi, yaitu perasaan tidak mempunyai pegangan hidup akibat yang ada selama ini tidak lagi dapat dipertahankan karena terasa tidak cocok. 5) Maka perubahan sosial dengan krisis-krisis yang ditimbulkannya itu, jika tidak ditangani dengan baik, akan menciptakan lahan yang sangat potensial bagi tumbuh suburnya radikalisme, fanatisme, sektarianisme, dan fundamentalisme yang dapat mengancam fakta sosial yang majemuk.Alhasil, peralihan tahun baru Islam agar tidak hanya menyisakan sekadar pidato, harus ada agenda besar untuk melakukan penyadaran yang lebih substansial baik dalam konteks keumatan ataupun kebangsaan. Agenda tentang kesadaran transformasi sosial kebangsaan. Jika tidak, semuanya hanya akan berhenti sebatas upacara! Tahun baru Islam satu Muharam pun hanya menyisakan `rutinitas ceramah’ para dai di atas mimbar keindonesiaan yang semakin gelap.
Sumber, Media Indonesia 2 November 2013