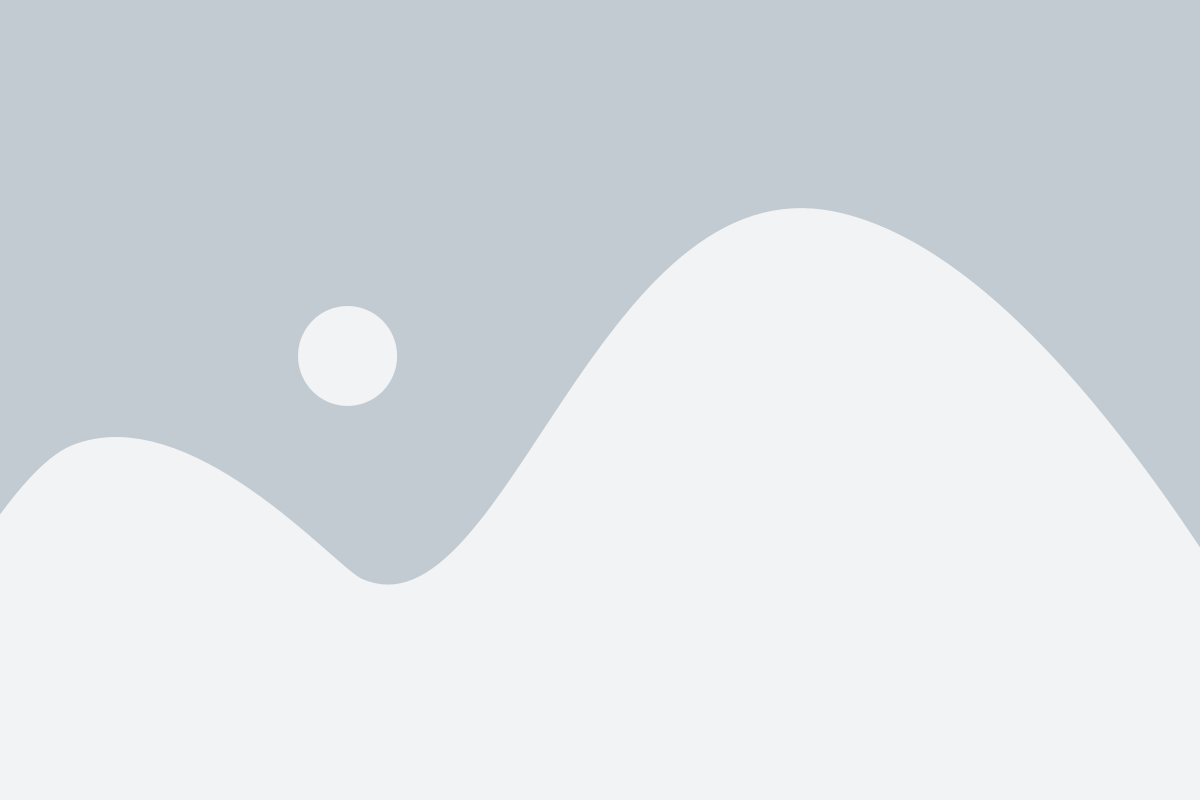Korupsi dibenci, tetapi dicari. Demikian gambaran problematika korupsi yang begitu popular dan akrab di telinga masyarakat, yang sudah menjadi fenomena sosial, merambah ke semua level kehidupan. Diperkirakan, usia korupsi itu sudah terhitung tua, seiring dengan usia prostitusi. Sampai saat ini pun, korupsi dengan pelbagai perangkat pendukung dan beragam penghalusannya, seperti uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelicin atau pelumas, dan uang pelancar tetap menjadi perhatian banyak pihak.
Bentuk-bentuk korupsi seperti itu, tampaknya sudah menjadi model dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teori moral, yang sangat nista, rendah, hina, dan tidak manusiawi, yaitu yang disebut A Glass of Water Theory, Teori Segelas Air Minum. Teori ini menyebutkan, bahwa kebutuhan biologis dan seksual pada manusia dianggap sebagai kebutuhan terhadap segelas air di kala haus. Jadi, kapan dan di mana saja, kalau memang perlu, bisa dilakukan. Memang sangat ironis, karena sepanjang sejarah kehidupan, manusia tidak henti-hentinya mengecam praktik korupsi, bahkan berupaya untuk mengenyahkannya. Namun sejalan dengan itu pula, manusia pun tidak jera dan tidak henti-hentinya korupsi. Di sini dua situasi yang secara diametral benar-benar terjadi: ”Korupsi dibenci, tetapi sekaligus juga dicari”. Memang hampir di sepanjang masa, di setiap negara, juga di setiap wilayah kekuasaan, terutama rezim yang lama berkuasa, dikenal adanya praktik korupsi. Ada benarnya tentang adagium kekuasaan yang dikemukakan Julian Pitt: unlimited power tend to corrupt — kekuasaan yang tak terbatas cenderung korup.
Korupsi itu memang merupakan penyakit yang sangat kronis, menyebar di berbagai belahan dunia dan lapisan bangsa. Dalam pemerintahan Islam pun pernah diguncang badai korupsi. Antara lain pada akhir Dinasti Abbasiyah, Khalifah Rasyid Billah lengser dari kekuasaannya karena mendapat mosi tidak percaya (sahbu tsiqah) dari Majelis Syura, gara-gara menggelapkan uang pajak Selanjutnya dalam perkembangan terakhir, terdapat sejumlah negara yang dikenal sebagai negara korup yaitu: Afrika, zaman Rezim Mobutu, Tiongkok, Nigeria, Pakistan, Kenya, Banglades, RRC, Kamerun, Venezuela, Rusia, India dan Indonesia. Akar persoalan yang menjadikan korupsi sebagai penyakit kronis masyarakat, yang sulit dicari pengo-batannya itu, apakah terkait dengan problema ekonomi, sistem budaya, sistem politik, sistem hukum, atau terletak pada moralitas bangsanya.
Korupsi Sebagai Penyakit Moral
Sejak zaman dahulu sampai saat ini, penyakit korupsi itu sudah begitu mengkristal, ada dalam setiap dekade pemerintahan. Pada masa kerajaan tempo dulu, terjadi penindasan dan pemerasan yang dilakukan para priyayi terhadap rakyat jelata, berupa pemungutan upeti secara semena-mena. Begitu pula pada zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan zaman Orde Reformasi, pada saat pemerintah memiliki komitmen kuat memberantas korupsi, yakni dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor dan KPK. Ironisnya, korupsi meskipun dibungkus dengan bahasa dan istilah-istilah yang sublim, jiwa dan semangatnya tetap merajalela, menyeret pejabat-pejabat tinggi dan pejabat tinggi negara setingkat menteri, level gubernur sampai bupati. Bahkan menyeret pula kalangan penegak hukum, yang semestinya menjadi pengawal dan aktor penegakkan hukum dan keadilan. Akhir-akhir ini terseret pula para wakil rakyat yang konon disebut-sebut sebagai koboy-koboy senayan, pegiat sekaligus sebagai pengawal pemerintah. Begitu juga ranah pendidikan, termasuk lingkungan kampus dan pendidikan tingkat dasar dan menengah, dengan kasus NEM, ikut pula melengkapi menjamurnya masalah korupsi, seakan-akan korupsi mewabah sebagai “watak alam” manusia, yang hampir ”mustahil” dapat diberantas, seakan-akan “korupsi hanya bisa dihapus di surga”.
Ditilik dari akar persoalannya, fenomena korupsi itu bisa jadi merupakan luapan dan problema ekonomi, mungkin cerminan dari sistem budaya, ekses dari sistem politik. Atau mungkin sebagai akibat dari sistem hukum.. Namun demikian, apapun akar persoalannya, baik problema ekonomi, sistem budaya, sistem politik, maupun sistem hukum, sebenarnya dimensi korupsi yang paling vital adalah dimensi nilai. Kita lihat negara-negara maju, yang sistem hukumnya sudah permanen, dalam arti kaedah hukumnya sudah berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis, seperti kebanyakan di negara Barat, betapa pun kecilnya, praktik korupsi itu tetap ada.
Di Indonesia, norma hukum serupa yang diperkirakan dapat membentengi dan menjera praktik korupsi tampaknya sudah cukup memadai. Begitu pula berbagai tawaran mekanisme yang diajukan pun cukup banyak, seolah-olah “tikus pun tidak bisa lewat”. Tetapi nyatanya, jangankan tikus, “gajah pun ternyata mampu menyusup dan menggondol” uang negara. Dengan demikian, benteng terakhir yang diandalkan dapat membendung penyakit korupsi ini tidak hanya bergantung pada banyaknya regulasi, tetapi yang paling mendasar adalah ranah moralitas, yakni moral pelaku. Karena dimensi moral seseorang menjadi wilayah kunci yang paling menentukan motivasi, pilihan, dan target suatu tindakan, termasuk tindakan korupsi. Di sini kontrol pribadi (self control) dipertaruhkan. Dalam artian, setiap pribadi harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan pola perilakunya secara etis dan bermoral.
Penguatan Moral Sebagai Benteng Mencegah Korupsi
Dalam perspektif ajaran Islam, kemampuan pengendalian diri itu mendapat tekanan yang paling kuat, di samping perlunya kontrol sosial untuk memperkokohnya. Pelbagai ketentuan normatif yang terkandung dalam al-Qur’an dan prosedur pene-gakannya, pada umumnya bermuara pada kesadaran diri, yang bersifat moral ke-timbang pada kontrol dari luar yang berbentuk sanksi. Jadi, kontrol pribadi yang kokoh jauh lebih dahsyat, efektif, fungsional dan tahan lama dalam memperbaiki pola perilaku, baik perilaku individu maupun perilaku masyarakat. Di sini moral seseorang itu tidak terlepas dari keyakinan dan pertanggungjawaban nurani. Apabila pertang-gungjawaban nurani ini sudah tertanam dalam diri seseorang, apapun statusnya, maka kehati-hatian (ikhtiat) akan selalu melekat di dalam dadanya. Khalifah Umar Ibn Kkattab termasuk petinggi negara yang selalu berhati-hati dalam memiliki harta. Dalam melakukan kontrolling Umar Ibn Khattab selalu menanyakan: Aina laka hadza? –Dari mana engkau dapatkan barang ini? Dalam hubungan ini, Umar Ibn Khattab pernah memerintahkan untuk mengembalikan barang hadiah, yang diterima seorang pejabat dari seseorang pembayar zakat. “Kembalikanlah barang itu ke Bait al-Maal! Sebab kalau bukan karena jabatanmu, mustahil dirimu akan menerima hadiah.
Begitu pula sikap kehati-hatian itu selalu dilakukan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz (Khalifah Dinasti Umayah). Diceritakan, bahwa pada masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, seorang pengawas Bait al-Maal tanpa suatu sebab yang jelas mengha-diahkan sebuah kalung emas untuk putri khalifah. Karena prinsip kehati-hatiannya, dan Khalifah Umar Ibn Adul Aziz merasa hal itu tidak patut diterimanya, maka ketika terlihat putrinya mengenakan kalung pemberian ini, seketika itu pula khalifah bertanya: Aina laka hadza? (dari mana engkau dapatkan barang ini)? Kemudian sang putri menjawab, ini hadiah yang pantas diterima sebagai putri khalifah. Dengan serta merta putrinya diperintahkan untuk menanggalkan kalung itu. ‘Takutlah wahai anakku yang tercinta, bahwa kelak engkau akan datang ke hadapan Mahkamah Tuhan dengan barang yang engkau curangi ini dan akan diselidiki dengan seksama”, ujar khalifah menasihati. Segeralah kalung itu pun dikembalikan oleh sang putri ke Bait al-Maal.
Dua contoh kasus kehati-hatian yang dipegang teguh oleh kedua khalifah, yang banyak memiliki kesamaan, meskipun berbeda generasi itu, memberikan gambaran, bahwa keimanan yang kokoh dengan benteng ihsan itu jelas-jelas memiliki kemampuan tinggi dalam mengendalikan moralitas seseorang, sehingga dalam kiprah dan perilaku apa pun tidak sembrono dan serampangan. Alhasil, dengan keimanan yang kuat, seseorang akan dapat mengendalikan dan menggerakan pilihan-pilihan hidup-nya, termasuk akan mampu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi. Dengan demikian, korupsi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diberantas. Hal ini sekaligus pula menolak asumsi, bahwa ”korupsi hanya dapat dihapus di surga”. Jika korupsi itu diidentikan dengan wabah penyakit kronis yang dapat menular kepada siapa saja yang tidak kebal, maka sejak dini perlu adanya langkah preventif ”imunisasi” berupa penguatan keimanan. Sementara itu, keimanan seseorang akan selalu terpelihara, bahkan selalu dalam puncak peningkatannya, manakala selalu dihiasi dengan ihsan. Wallahu’alam
*Penulis adalah Profesor bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, dosen Pranata Sosial Hukum Islam dan Peradilan Agama pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.